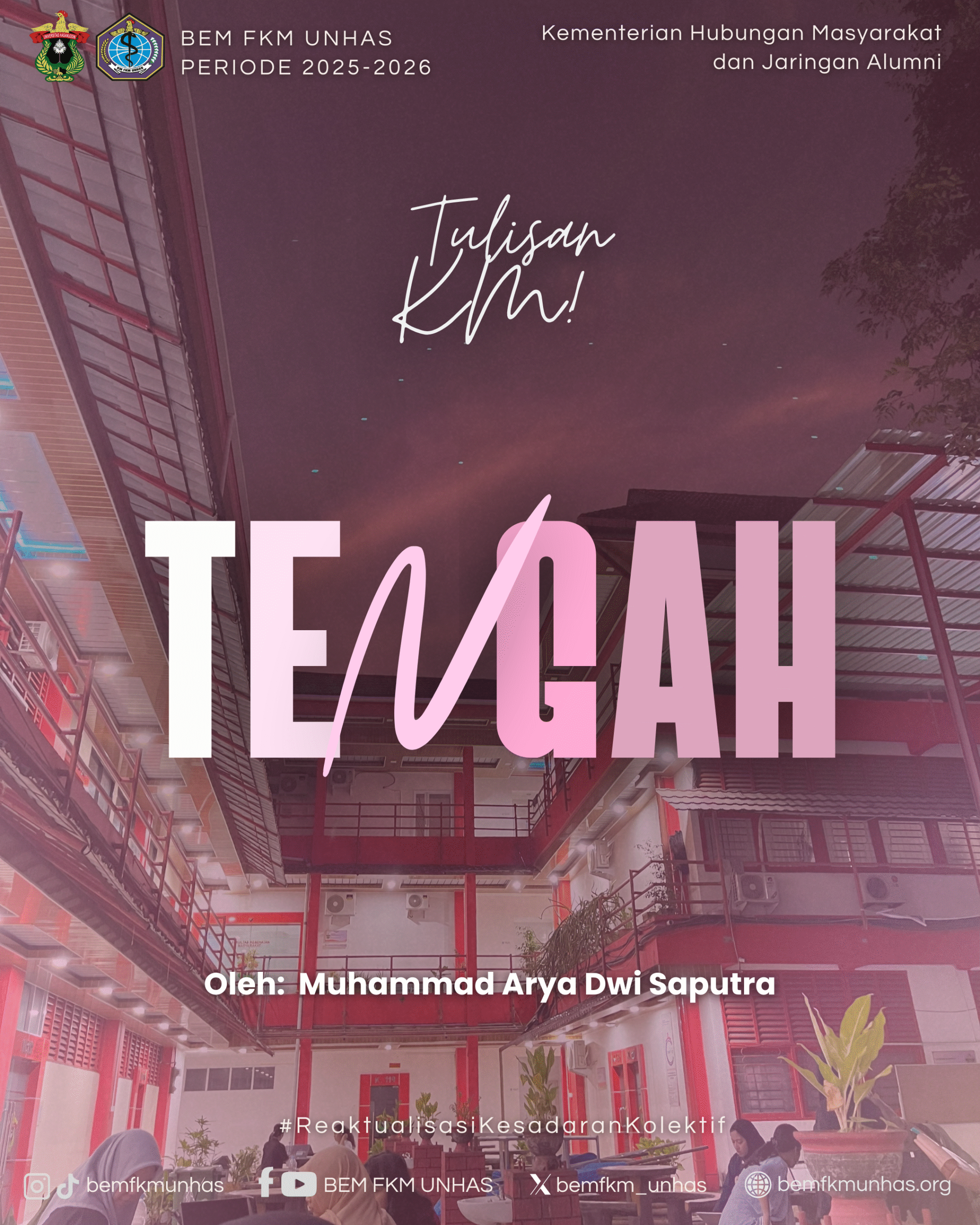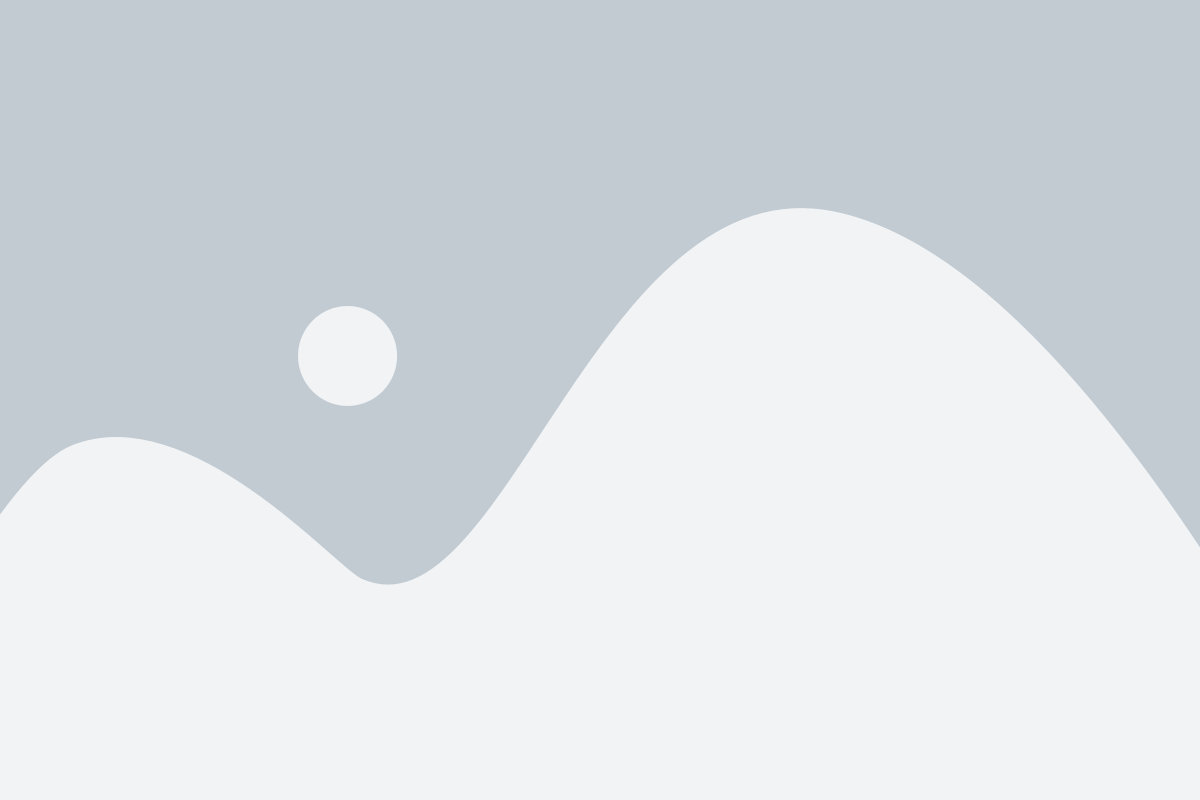
Realitas Gender di Bawah Bayang-Bayang Neoliberalisme
Pernahkah kita bertanya, mengapa semakin banyak perempuan masuk ke dunia kerja, namun beban domestik mereka justru tidak berkurang? Di balik retorika pemberdayaan perempuan yang digembar-gemborkan era neoliberal, tersembunyi kontradiksi yang mengakar: sistem ekonomi yang menjanjikan kebebasan individual justru menciptakan bentuk-bentuk penindasan baru yang lebih halus dan terselubung. Neoliberalisme, dengan logika pasar bebasnya, telah mengubah cara kita memahami gender, bukan lagi sebagai relasi sosial yang perlu diubah secara struktural, melainkan sebagai identitas yang bisa “diberdayakan” melalui partisipasi dalam ekonomi pasar. Namun apakah pemberdayaan semacam ini benar-benar membebaskan, ataukah justru menjadi jebakan baru yang memperdalam ketimpangan?
Neoliberalisme menghadirkan narasi seduktif tentang “girl power” dan entrepreneur wanita yang sukses, seolah-olah emansipasi perempuan dapat dicapai melalui kesuksesan individual di pasar kerja. Ideologi ini mempromosikan feminisme yang Nancy Fraser sebut sebagai “feminisme neoliberal” yakni sebuah versi feminisme yang telah dikosongkan dari kritik strukturalnya terhadap kapitalisme dan patriarki. Perempuan didorong untuk menjadi “CEO of their own lives,” untuk mengoptimalkan diri mereka sendiri sebagai modal manusia yang kompetitif. Namun di balik glamor ini, jutaan perempuan kelas pekerja menghadapi prekarisasi kerja, upah rendah, dan eksploitasi yang sistematis tanpa jaminan sosial yang memadai.
Salah satu dampak paling nyata dari neoliberalisme terhadap gender adalah feminisasi kemiskinan dan prekarisasi tenaga kerja perempuan. Dalam ekonomi neoliberal yang mengutamakan fleksibilitas dan efisiensi, perempuan yang utamanya dari kelas ekonomi bawah menjadi pekerja yang paling rentan, mereka bekerja di sektor informal, dengan kontrak sementara, tanpa jaminan kesehatan atau pensiun. Di Indonesia, jutaan perempuan bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja rumah tangga migran, atau pekerja lepas dengan upah di bawah standar. Apakah ini yang dimaksud dengan pemberdayaan? Atau justru ini adalah bentuk eksploitasi yang dilegitimasi oleh wacana “kesempatan kerja” dan “kemandirian ekonomi”?
Selain itu, neoliberalisme telah mengkomodifikasi tubuh dan reproduksi perempuan dalam cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Industri kecantikan, fertilitas, dan reproduksi dengan bantuan teknologi menjadi pasar bernilai miliaran dolar yang memanfaatkan insekuritas dan kebutuhan perempuan. Tubuh perempuan tidak lagi dipahami sebagai bagian dari diri yang utuh, melainkan sebagai proyek yang harus terus diperbaiki, diinvestasikan, dan dioptimalkan agar tetap “marketable.” Wacana self-care dan wellness yang populer saat ini, meskipun tampak emansipatoris, sebenarnya adalah strategi neoliberal untuk membuat individu bertanggung jawab penuh atas kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri—mengalihkan tanggung jawab negara kepada pasar dan individu.
Dalam ranah kebijakan publik, neoliberalisme telah menyusutkan peran negara dalam menyediakan layanan sosial yang esensial bagi kesetaraan gender. Privatisasi layanan kesehatan, pendidikan, dan perawatan anak membuat akses terhadap layanan-layanan ini menjadi komoditas yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membayar. Perempuan dari kelas menengah ke atas mungkin bisa “membeli” kebebasan mereka dengan menyewa pengasuh anak atau asisten rumah tangga, namun ini hanya memindahkan beban reproduksi sosial kepada perempuan lain yang lebih miskin—seringkali perempuan migran atau dari daerah pedesaan. Bukankah ini hanya menciptakan hierarki baru di antara perempuan, alih-alih solidaritas untuk transformasi sosial yang sejati?
Paradoks neoliberalisme dan gender juga terlihat dalam cara sistem ini mengkooptasi bahasa kesetaraan untuk melanggengkan ketidaksetaraan. Perusahaan-perusahaan multinasional dengan bangga menampilkan CEO perempuan atau menerapkan kebijakan “gender diversity,” sementara di saat yang sama membayar pekerja perempuan mereka dengan upah rendah dan mengeksploitasi buruh perempuan di negara-negara Global South. “Lean in” dan “break the glass ceiling” menjadi mantra yang mengalihkan fokus dari ketidakadilan struktural menuju tanggung jawab individual—seolah-olah perempuan yang tidak berhasil adalah karena mereka tidak cukup berusaha, bukan karena sistem yang memang dirancang untuk menguntungkan segelintir elit. Ketika kapitalisme berpura-pura feminis, kita harus bertanya: feminis untuk siapa?
Resistensi terhadap neoliberalisme gender memerlukan kebangkitan kesadaran kolektif bahwa pembebasan perempuan tidak bisa dicapai melalui partisipasi individual dalam pasar yang eksploitatif. Gerakan-gerakan seperti International Women’s Strike, kampanye untuk upah layak bagi pekerja rumah tangga, dan perjuangan untuk layanan publik yang universal menunjukkan bahwa alternatif masih mungkin. Kita membutuhkan feminisme yang anti-kapitalis, yang memahami bahwa kesetaraan gender tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekonomi, redistribusi kekayaan, dan penghapusan sistem eksploitasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah perempuan bisa “sukses” dalam sistem neoliberal, melainkan bagaimana kita bersama-sama membangun sistem alternatif yang membebaskan semua orang, tanpa terkecuali.
Di titik ini, kita dihadapkan pada pilihan fundamental: apakah kita akan terus menerima ilusi pemberdayaan yang ditawarkan neoliberalisme, atau kita berani membayangkan dan memperjuangkan transformasi struktural yang sesungguhnya? Neoliberalisme telah gagal mewujudkan janjinya tentang kebebasan dan kesejahteraan—yang ada hanya ketimpangan yang semakin dalam, prekarisasi yang meluas, dan komodifikasi yang menyeluruh atas kehidupan kita. Pembebasan perempuan, dan pembebasan semua orang yang tertindas, menuntut kita untuk melampaui logika pasar dan membangun solidaritas lintas kelas, ras, dan bangsa. Hanya dengan demikian, kita bisa menciptakan dunia di mana kesetaraan gender bukan sekadar retorika, melainkan realitas yang hidup dalam setiap aspek kehidupan sosial kita.
Referensi:
Fraser, N. (2013). “Fortunes of Feminism: From State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis.” Verso Books.
Eisenstein, H. (2009). “Feminism Seduced: How Global Elites Use Women’s Labor and Ideas to Exploit the World.” Paradigm Publishers.
Federici, S. (2012). “Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle.” PM Press.
Oksala, J. (2013). “Feminism and Neoliberal Governmentality.” Foucault Studies, No. 16, pp. 32-53.
Roberts, A. (2015). “The Political Economy of ‘Transnational Business Feminism’: Problematizing the Corporate-led Gender Equality Agenda.” International Feminist Journal of Politics, 17(2), 209-231.
McRobbie, A. (2009). “The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change.” SAGE Publications.
Standing, G. (2011). “The Precariat: The New Dangerous Class.” Bloomsbury Academic.
World Bank. (2012). “World Development Report 2012: Gender Equality and Development.” Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4391