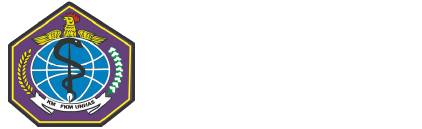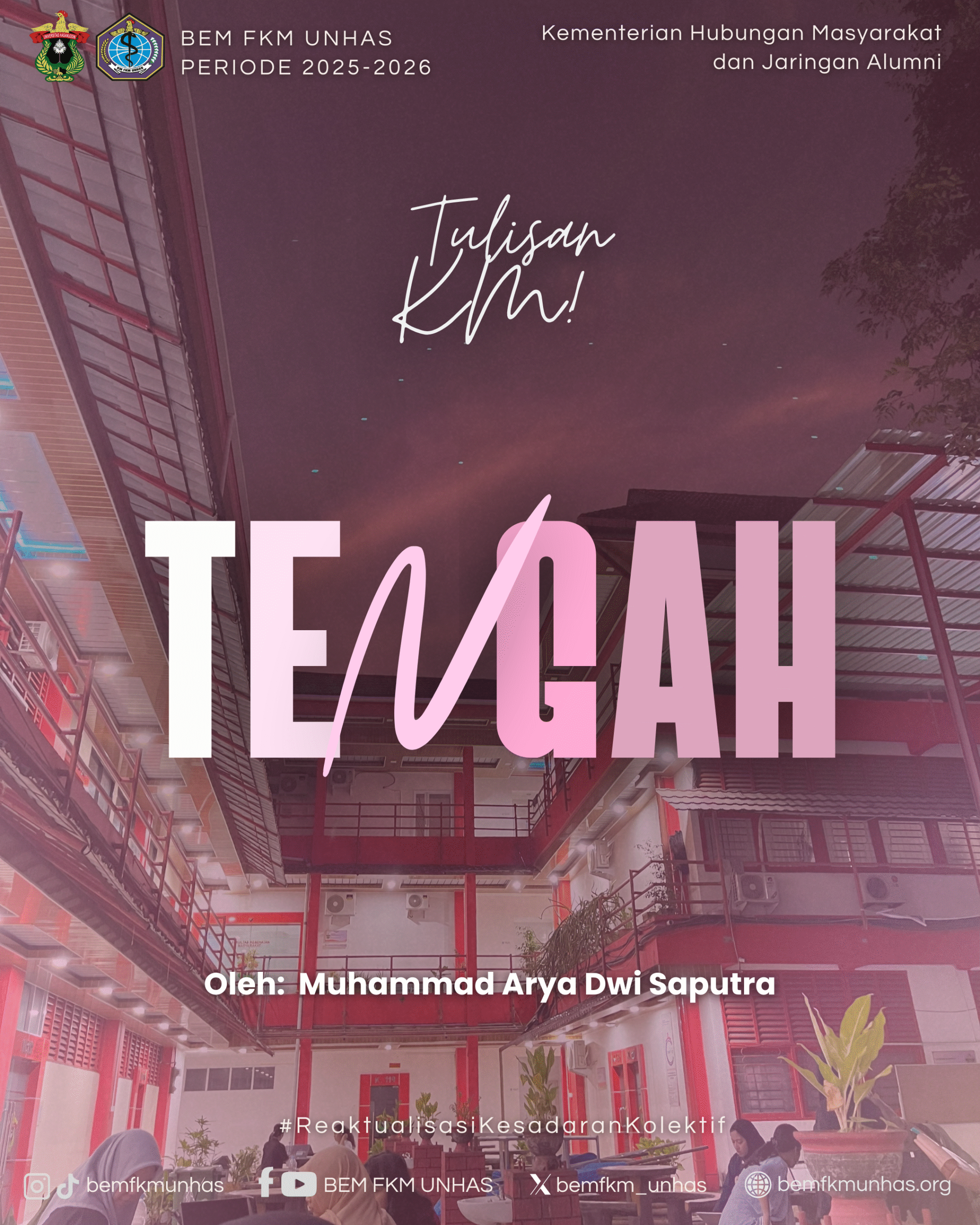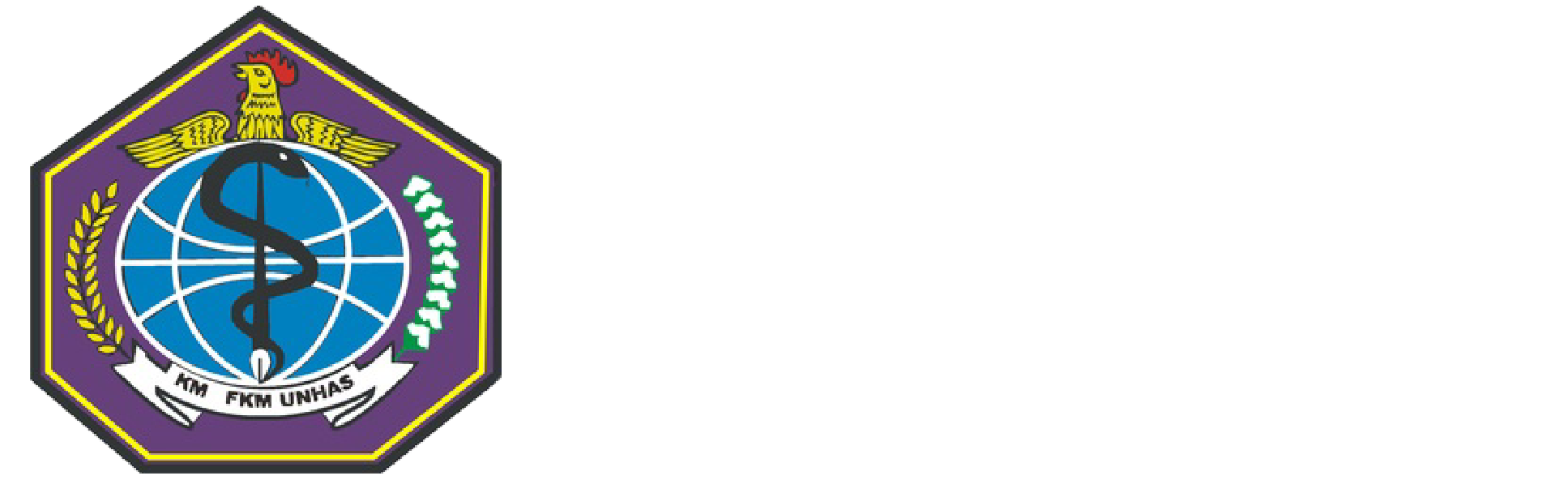Kapitalisme dan Ekokrisis: Mengurai Simpul Eksploitasi Alam
Eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu aspek paling mencolok dari dampak negatif kapitalisme terhadap lingkungan. Dalam sistem kapitalis, dorongan untuk mencapai keuntungan maksimal mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan skala besar. Kegiatan seperti penebangan hutan, penambangan, dan pengeboran minyak dilakukan tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjangnya terhadap lingkungan. Misalnya, praktik penebangan hutan yang tidak terkontrol tidak hanya menyebabkan hilangnya tutupan hutan yang penting bagi keseimbangan ekosistem, tetapi juga mengakibatkan kerugian habitat bagi berbagai spesies. Kehilangan habitat ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup spesies-spesies tersebut, tetapi juga menyumbang pada perubahan iklim global karena berkurangnya kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida. Selain itu, proses penambangan dan pengeboran juga menimbulkan kerusakan ekosistem yang serius, mempengaruhi keanekaragaman hayati dan keseimbangan alam secara keseluruhan. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam dalam kapitalisme tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan lokal, tetapi juga memberi dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim global dan ekosistem secara keseluruhan.Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Murray Bookchin, yang menghubungkan polusi udara dan air sebagai akibat langsung dari hukum pasar yang merusak. Kapitalisme, menurut Bookchin, menciptakan insentif untuk eksploitasi lingkungan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya. Barry Commoner menambah kritik ini dengan menulis bahwa teknologi yang merusak lingkungan berakar kuat dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik kita. Kritik-kritik ini menunjukkan bagaimana kapitalisme, dengan dorongan kuat untuk produksi dan keuntungan, sering kali mengabaikan konsekuensi ekologis dari aktivitas industri.
Sejarah pengelolaan, atau lebih tepatnya “eksploitasi”, sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan penerbitan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pembukaan pintu investasi pada awal pemerintahan Orde Baru ini membawa dampak besar terhadap eksploitasi berbagai sumber daya alam di Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan hidup secara besar-besaran. Pemerintah Orde Baru mengadopsi ideologi modernis dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan diartikan sebagai usaha mengubah masyarakat dari tradisional menjadi modern, dengan fokus utama pada pertumbuhan ekonomi. Untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi ini, pemerintah kemudian mengeksploitasi berbagai sumber daya alam yang tersedia.
Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Gagasan Rene Descartes ini menandai perubahan besar dalam cara manusia memandang hubungannya dengan hal-hal di luar dirinya, termasuk alam. Pola pikir rasional yang diusung oleh gagasan ini membawa dampak besar, memunculkan optimisme bahwa manusia mampu menaklukkan alam. Manusia tidak lagi tunduk pada alam, tetapi dengan kemampuan rasionalnya, dapat mengubah alam sesuai kebutuhannya. Alam dan segala sesuatu di luar diri manusia kemudian dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, hanya manusia yang dianggap memiliki nilai, sedangkan yang lain tidak.
Penurunan kualitas lingkungan beriringan dengan manusia yang semakin eksploitatif terhadap alam, dari tradisional ke modern. Di masa tradisional, alam adalah kekuatan yang menentukan, membuat manusia hanya objek. Namun, masyarakat modern, dengan kepercayaan positivistiknya, meyakini bahwa kekuasaan terhadap realitas ada di tangan manusia, bukan alam. Ini menciptakan pergeseran menyedihkan di mana alam hanya menjadi korban dari ambisi manusia.
Industrialisasi, sebagai akar permasalahan, dipicu oleh kapitalisme dan mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara massif. Kapitalisme berperan sebagai pendorong utama di balik dorongan untuk mencapai masyarakat modern yang bergantung tidak hanya pada modal finansial, tetapi juga sumber daya alam. Proses ini terus berlanjut seiring dengan dominasi paradigma pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis. Selain eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, dampak lanjutan dari industrialisasi yang didorong oleh kapitalisme adalah munculnya berbagai jenis polusi dan pencemaran lingkungan. Hal ini kemudian menghasilkan konsekuensi lanjutan seperti kelangkaan sumber daya dan penurunan kapasitas alam untuk mendukung keberlangsungan hidup di bumi. Dengan kata lain, kapitalisme mempercepat laju eksploitasi sumber daya alam dan mendorong degradasi lingkungan yang serius demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kapitalisme telah mencapai tahap perkembangan yang meluas secara global, di mana kekuatan dominan suatu negara-bangsa masih memonopoli sebagian besar sumber daya dan pasar. Sifat kapitalisme yang tidak mengenal batas untuk pertumbuhan dan pengembangan dirinya sendiri menjadi pendorong utama di balik fenomena ini. Tidak ada batasan yang diakui dalam hal mencapai keuntungan maksimal, akumulasi kekayaan, perluasan wilayah pengaruh, atau konsumsi. Bumi, dalam pandangan kapitalisme, tidak lagi dianggap sebagai rumah bagi manusia dan spesies lainnya yang perlu dijaga, melainkan sebagai sumber daya alam yang harus dieksploitasi demi memperluas ekonomi tanpa batas. Dalam konteks ini, tujuan utama kapitalisme adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal, bahkan jika itu berarti mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, paradigma ekspansi tanpa batas dalam kapitalisme telah mengubah pandangan terhadap bumi menjadi sumber daya yang tak terbatas untuk dimanfaatkan, tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjangnya bagi keberlangsungan hidup manusia dan spesies lainnya.
REFERENSI:
Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, Dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Mozaik Humaniora, 20(1), 57-69.
Laleno, F. F. (2017). Etika Global Guna Mengendalikan Kapitalisme Global. Logos, 14(2), 68-88.
Tampubolon, Y. H., & Purba, D. F. (2022). Kapitalisme Global sebagai Akar Kerusakan Lingkungan: Kritik terhadap Etika Lingkungan. Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 9(1), 83-104.