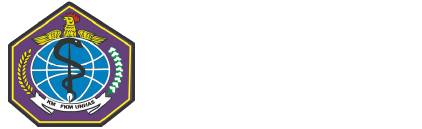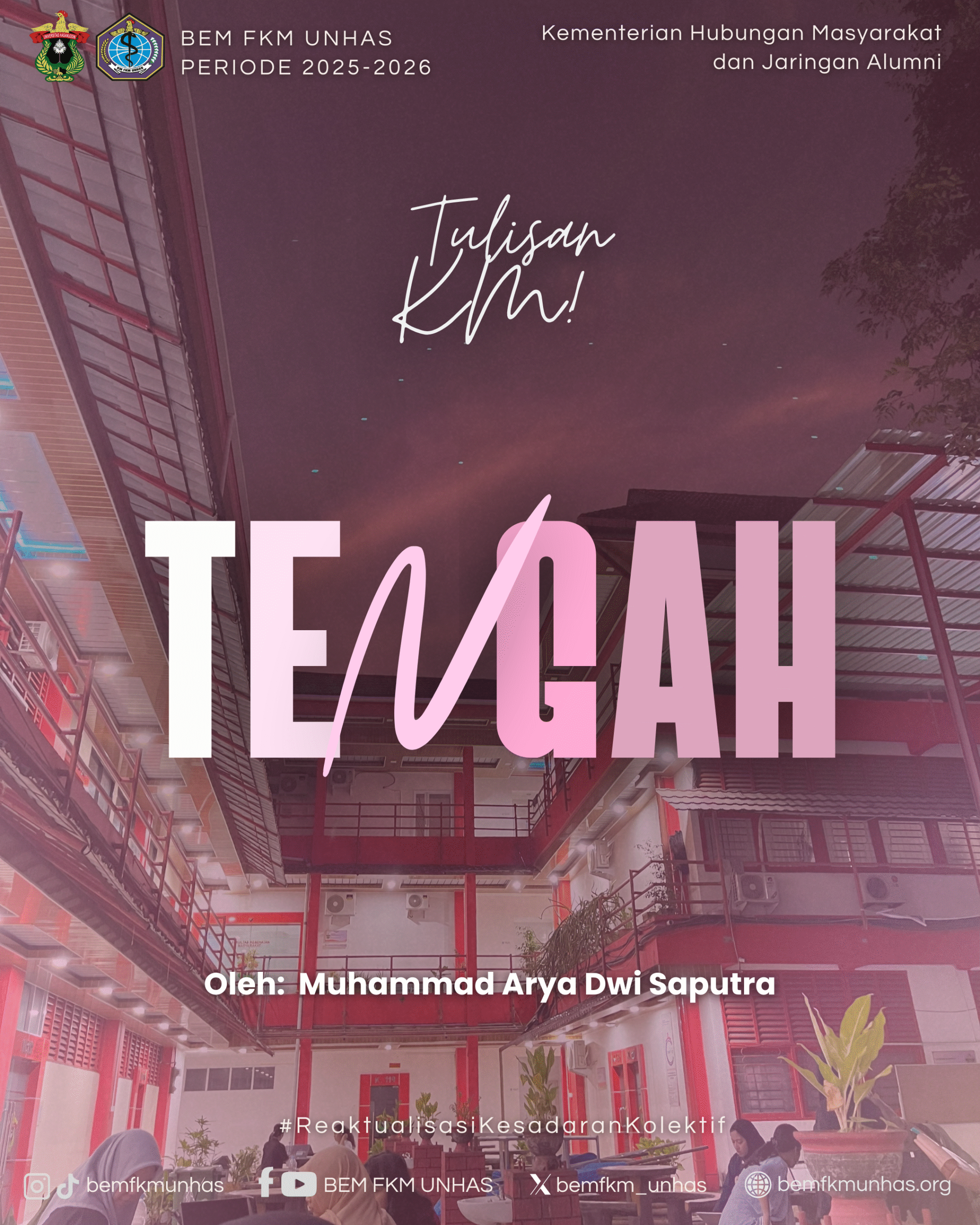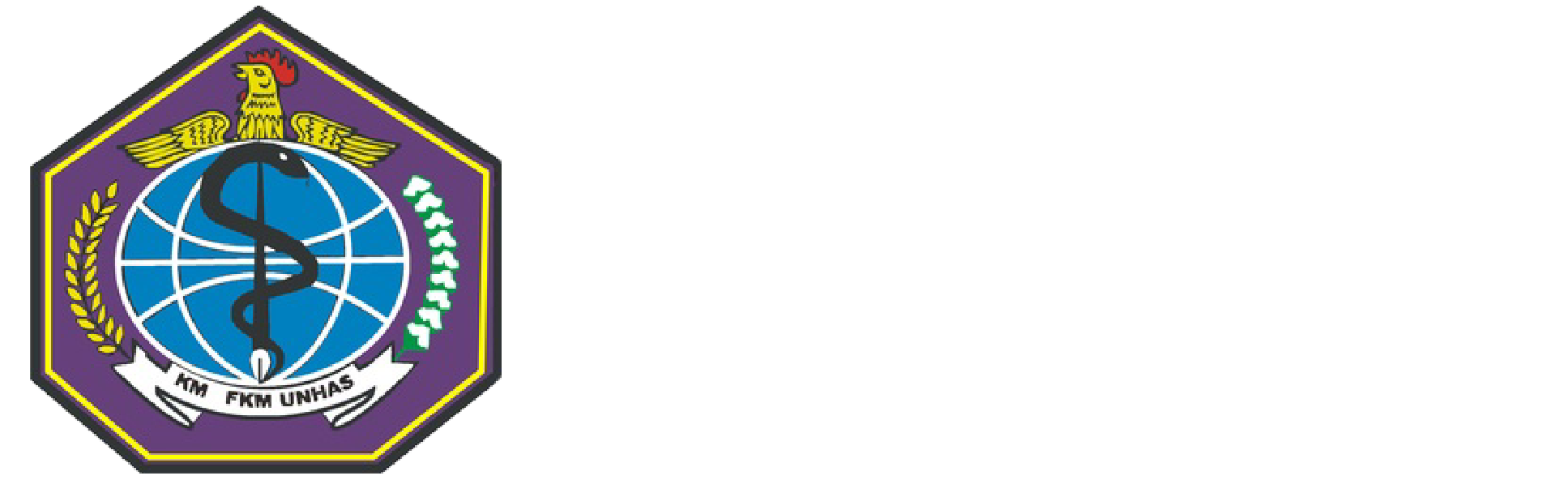Baru-baru ini, berbagai organisasi perempuan dan gerakan sosial di seluruh dunia melaksanakan demonstrasi dan aksi besar-besaran sebagai bentuk protes dan melawan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun ini dilakukan tidak hanya terjadi pada 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP).
Di Indonesia, berdasarkan laporan CATAHU dari Komnas Perempuan, tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, data ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan oleh korban, keluarga, atau pendamping (CATAHU Komnas Perempuan, 2023). Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es, bisa jadi lebih luas dan lebih mendalam daripada yang tercatat, dengan banyaknya kasus yang tidak pernah terungkap dan dilaporkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih merupakan masalah struktural yang belum mendapatkan penanganan oleh negara.
Sebelum membahas lebih lanjut, penulis mengundang pembaca untuk merefleksikan kembali pemahaman kita tentang konsep neoliberalisme. Di akhir tulisan, penulis akan memberikan beberapa solusi sebelum menarik kesimpulan. Oleh karena itu, tulisan ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan dasar dan sederhana:
Apakah konsep Neoliberalisme berubah?
Neoliberalisme pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Jerman aliran Feurbach yang mengkritisi sistem ekonomi liberal klasik. Neoliberalisme di Jerman menolak kebebasan pasar bebas murni dan menekankan nilai-nilai humanistik. Namun, neoliberalisme yang diterapkan di dunia saat ini sangat berbeda dengan konsep awalnya yang diterapkan di Jerman. Kini, neoliberalisme seringkali diidentikan dengan deregulasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara dalam ekonomi. Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat di negara Chili, di mana neoliberalisme diterapkan dengan tujuan memajukan tatanan perekonomiannya, namun dalam konsep prakteknya yang diadopsi tidak sejalan dengan teori, prakteknya lebih mirip dengan liberalisme klasik yang terbukti gagal di Jerman. Menurut Ridha (2021) “Dalam realisasinya, neoliberalisme bergantung pada modifikasi politik dan adaptasi lembaga negara untuk menjaga pasar beroperasi secara optimal. Ada dilema dalam konseptualisasi neoliberalisme karena pasar tidak pernah muncul secara murni tanpa campur tangan non-pasar”.
Lalu, bagaimana konsep Neoliberalisme di Indonesia?
Di Indonesia, neoliberalisme mulai diterapkan setelah krisis ekonomi moneter pada tahun 1997, tentu saja dengan campur tangan IMF yang mendesak penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Neoliberalisme pertama kali ada di Indonesia sejak penandatanganan kontrak karya dengan PT. Freeport pada masa Presiden Soeharto (Arianto, 2009). Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Soeharto menandatangani Letter of Intent (LOI) yang berisikan manifestasi dari Washington Consensus, kebijakan ini menyebabkan privatisasi BUMN dan memunculkan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar. Neoliberalisme dianggap mengadopsi akumulasi primitif yang didalamnya terdapat penyingkiran dan perampasan seperti yang terjadi di era pra-kapitalisme. Dalam praktiknya, neoliberalisme lebih cenderung menguntungkan kapitalis besar, semakin memperburuk ketidaksetaraan sosial, dan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.
Neoliberalisme bukan hanya tentang kebijakan ekonomi, tetapi lebih merupakan upaya untuk memulihkan keuntungan kelas kapitalis, khususnya di sektor keuangan, setelah krisis struktural pasca-Perang Dunia II. Hal ini terwujud dalam dua fase. Pertama, stabilisasi ekonomi makro yang melibatkan penghapusan subsidi barang publik, pemangkasan pekerjaan publik, dan pemotongan belanja sosial seperti pendidikan. Kedua, penyesuaian struktural yang melibatkan liberalisasi perdagangan dan keuangan, deregulasi, dan privatisasi badan-badan ekonomi publik (Pontoh, 2021).
Neoliberalisme & Kekerasan terhadap Perempuan
Tidak dipungkiri bahwa penerapan neoliberalisme merugikan banyak kalangan, dampaknya lebih dirasakan oleh kaum perempuan. Hal ini tak lepas dari kuatnya konstruk sosial yang menghegemoni pemikiran masyarakat konservatif sehingga otak-otak patriarki terpelihara dengan dengan kental. Pada dasarnya, perempuan tidak hanya dihadapkan pada tantangan ekonomi, tetapi juga harus menghadapi berbagai hambatan yang diciptakan oleh sistem yang tidak mendukung kemajuan mereka.
Patriarki dan neoliberalisme saling berinteraksi dalam membentuk ketidakadilan bagi perempuan. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi domestik, sedangkan laki-laki menjadi “pencari nafkah utama”. Ketika perempuan terpaksa bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, posisi mereka hanya dianggap sebagai “pencari nafkah tambahan”. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam pengupahan, di mana upah laki-laki lebih tinggi karena komponen tunjangan keluarga (istri dan anak), sementara perempuan, meskipun telah menikah atau berkeluarga, tetap dipandang sebagai pekerja lajang.
Dalam konstelasi lingkungan perburuhan di level pabrik, misalnya. Sangat sulit untuk menciptakan posisi tawar bagi buruh perempuan. Kesulitan naik pangkat, menjadi salah satu contohnya. Seringkali kenaikan pangkat hanya bisa diakses oleh buruh laki-laki dengan asumsi yang tidak mendasar. Buruh perempuan dianggap tidak konsisten dalam bekerja, biasanya setelah menikah atau melahirkan, buruh perempuan akan mengundurkan diri, sehingga tidak perlu diberi kenaikan pangkat. Perbedaan akses ini berujung mendorong terjadinya perbedaan tingkat upah dan potensi pendapatan buruh perempuan terhadap buruh laki-laki (Amin, 2014).
Data dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kesenjangan upah antar gender di Indonesia berkisar ±20%. Selain itu, perempuan sering didomestikasi, maka sebagian besar tenaga kerja perempuan dipandang tergolong berketerampilan rendah. Sebagian besar perempuan yang dipaksa bekerja di luar rumah memilih pekerja yang berkaitan dengan pekerjaan (domestik) mereka, seperti pekerja rumah tangga, pelayan toko, atau pengurus anak. Pekerjaan-pekerjaan ini umumnya tidak dilindungi oleh hukum yang menjamin hak-hak dasar mereka, seperti upah yang layak dan jaminan keselamatan kerja.
Neoliberalisme yang membuat kompetisi pasar yang semakin ketat dan juga mendorong perusahaan padat karya untuk berstrategi agar terus memperoleh keuntungan, salah satunya dengan cara: mempekerjakan buruh perempuan dalam suatu skema kontrak. Sejak tahun 2000-an, banyak perusahaan di Indonesia telah menerapkan mekanisme pasar tenaga kerja fleksibel (LMF/Labour Market Flexibility) melalui sistem alih daya pekerja (outsourcing). Sistem kontrak didasarkan pada asumsi bahwa mempekerjakan buruh perempuan secara tetap jauh lebih ‘mahal’ dibandingkan dengan buruh laki-laki, terutama bagi mereka yang telah menikah, sebab nantinya perusahaan berkewajiban memberikan hak maternitas seperti cuti kehamilan, cuti melahirkan, maupun cuti haid.
Misal soal cuti haid, yang dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 telah diatur. Namun, implementasi terhadap peraturan tersebut di lapangan masih sangat problematis. Untuk mengambil jatah cuti haid, pekerja harus menunjukkan kapas/celana dalam yang menunjukkan buruh yang bersangkutan sedang haid. Ironisnya, para buruh sendiri banyak tidak tahu-menahu soal regulasi cuti haid. Padahal faktanya, perempuan yang bekerja di industri sering mengalami cedera (tertusuk, teriris mesin pemotong)— dikarenakan kurang fokus ketika menahan nyeri haid. Beberapa dari mereka mengaku pernah menangis sebab harus berdiri sepanjang 8 jam (apalagi jika ditambah lembur)— bahkan ada pula yang pingsan sebab tidak kuat menahan nyeri haid. Hak cuti haid, hak maternitas, dan masalah penanggulangan kekerasan seksual gaungnya memang tidak sebesar bahasan soal regulasi upah, hubungan kerja, status kerja, tunjangan, dan permasalahan pemenuhan hak normatif lainnya.
Dampak Neoliberalisme terhadap Kesejahteraan Perempuan
Penerapannya tidak hanya berdampak pada sektor publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang semakin diprivatisasi. Perempuan, yang sering dianggap sebagai pengelola urusan domestik dan ekonomi keluarga, sangat merasakan langsung dampak dari penghapusan subsidi dan meningkatnya biaya hidup. Ketika pemerintah mencabut subsidi bahan bakar (BBM) misalnya, secara berantai akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya, maka perempuanlah yang memikul beban ekonomi keluarga sebab bertanggung jawab atas urusan dapur rumah tangga (Rasdiana, 2022). Inilah mengapa perempuan seringkali menjadi korban dari kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada kesejahteraan keluarga.
Fenomena buruh migran perempuan juga merupakan kontribusi dari neoliberalisme itu sendiri. Karena neoliberalisme menghancurkan basis ekonomi rakyat, baik pertanian maupun industri kecil, maka banyak keluarga yang kehilangan topangan ekonomi. Misalnya, perempuan dari desa yang terpaksa mencari pekerjaan di kota atau bahkan ke luar negeri untuk menopang ekonomi keluarga mereka, akibat kehancuran ekonomi berbasis pertanian dan industri kecil (Hidayat, dkk., 2024). Dalam banyak kasus, perempuan yang bekerja di luar rumah seringkali terjebak dalam posisi rentan, baik dalam konteks ekonomi maupun kekerasan.
Neoliberalisme mendorong komodifikasi perempuan, menjadikan tubuh mereka sebagai objek seksual dan eksploitatif. Ini nampak dalam maraknya perdagangan perempuan dan komoditifikasi tubuh perempuan sebagai objek eksploitasi seksual (pornografi, pelacuran, promosi barang/sales promotion girl dan lain-lain). Terlebih lagi, permasalahan kekerasan seksual seringkali dinarasikan sebagai sesuatu yang normal, wajar, sehingga tidak perlu dilebih-lebihkan sebab dianggap bisa diselesaikan secara personal (normalisasi). Kasus kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang sudah biasa terjadi sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Walaupun UU TPKS atau UU No. 12 tahun 2022 ini telah disahkan, pengawalan terhadap kasus kekerasan seksual ini lantas menjadi sulit karena korban dan saksi bungkam ketika dimintai keterangan, sehingga proses tindak lanjut terhadap kekerasan seksual tidak pernah tuntas. Neoliberalisme sangat memperkuat pasar bebas tanpa regulasi yang memadai, seringkali memunculkan ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi perempuan dengan akses terbatas pada pekerjaan yang layak dan upah yang adil dan setara. Olehnya itu, penulis merangkumkan poin-poin:
- Persoalan kekerasan berbasis gender (terhadap Perempuan) tidak disebabkan hanya oleh ketiadaan atau tidak memadainya pengaturan hukum ataupun kebijakan-kebijakan yang ada.
- Persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan struktural yang mengakar kuat dan menjadi bagian integral dari fungsi keseharian masyarakat kapitalis.
- Walaupun kebijakan atau hukum telah disahkan, hal yang keliru ketika kita menempatkan hukum sebagai satu-satuya solusi utama dan final dalam penyelesaian kasus kekerasan tanpa mendasarkan pada gerakan massa untuk menuntut perubahan sistem masyarakat secara keseluruhan.
Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya alternatif:
- Advokasi terhadap hak-hak perempuan menjadi penting untuk digalakkan.
- Pendidikan perspektif gender dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan peranan buruh perempuan baik di level organisasi, serikat, maupun di level relasi industrial yang lebih luas, atau bahkan di luar itu, misal dalam keluarga.
- Agenda alternatif yang didorong, misalnya, adalah mengupayakan penciptaan kekuatan kelas yang relatif seimbang antara kapital dan pekerja. Hal ini didapat dengan penetapan tujuan untuk mengubah negara neoliberal menjadi negara developmental klasik. Posisi ini mendorong pengembangan ekonomi berorientasi dalam negeri berdasarkan hubungan yang sehat dan kreatif antara pertanian dan industri (Habibi, 2014).
Namun tentu ini bukan satu-satunya opsi. Perlu untuk mengeksplorasi alternatif lain. Tentu saja, alternatif yang dibangun dari, oleh, dan untuk perjuangan akar rumput.
“Keberanian dan kemandirian perempuan tidak selalu ditentukan oleh sejauh mana aksesnya terhadap kekayaan, tetapi sejauh mana ia sadar dan mau memperjuangkan kepentingannya sebagai perempuan. Namun, level penindasan akan sangat ditentukan oleh derajat eksploitasi kelas, semakin dalam eksploitasi kelas semakin tinggi level penindasan.” — Zely Ariane
Sebagai penutup, mari kita mengupayakan untuk melampaui segala relasi sosial-produksi status quo. Perjuangan terhadapnya mungkin jalan terjal yang berliku, namun dalam keharmonisan langgam geraklah hal ini dimungkinkan.
Referensi
Perempuan, Komnas. 2023. Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan . Catatan Tahunan, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Mahardhika, Perempuan. 2017. Infografik Hasil Penelitian Pelanggaran Hak Maternitas di KBN Cakung. Infografik, Jakarta: Perempuan Mahardhika.
Mundayat, Aris Arif. 2008. “Moral Ekonomi Perempuan Pabrik: Dinamika Kehidupan di Tempat Kerja.” In Bertahan Hidup di Desa atau Tahan Hidup di Kota : Balada Buruh Perempuan, by Aris Arif Mundayat, Erni Agustini and Margaret Aliyatul Maimunah, 1-34. Jakarta: Women Research Institute.
Pontoh, C. H. (2021). Kapitalisme-Neoliberal Sebagai Proyek Kelas: Sebuah Analisa Marxis. In Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di Indonesia. Pustaka IndoPROGRESS. https://indoprogress.com/download/neoliberalisme-konsep-dan-praktiknya-di-indonesia/
Ridha, M. (2021). Sekali Lagi tentang Neoliberalisme sebagai Konsep. In Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di Indonesia. Pustaka IndoPROGRESS. https://indoprogress.com/download/neoliberalisme-konsep-dan-praktiknya-di-indonesia/
Amin, Mudzakkir (2014). Kegalauan Feminisme di Hadapan Neoliberalisme. Pustaka IndoPROGRESS. https://indoprogress.com/2014/02/kegalauan-feminisme-di-hadapan-neoliberalisme/
Habibi, M. (2014, Dec). The Development of Relative Surplus Population in the Peripheral Accumulation: Political Economy of Agricultural Development and Industrialization in Indonesia [Research Paper]. https://thesis.eur.nl/pub/17363/Muchtar-Habibi.pdf.
Rasdiana, R. (2022). Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Tana Mana, 3(1), 48-62.
Hidayat, R., Nutfa, M., & Ariyani, R. (2024). Perempuan Dalam Program Perubahan Iklim: Jerat Budaya Neoliberal Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 8(4).