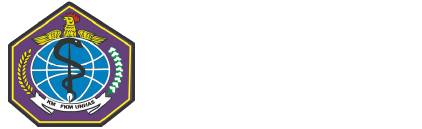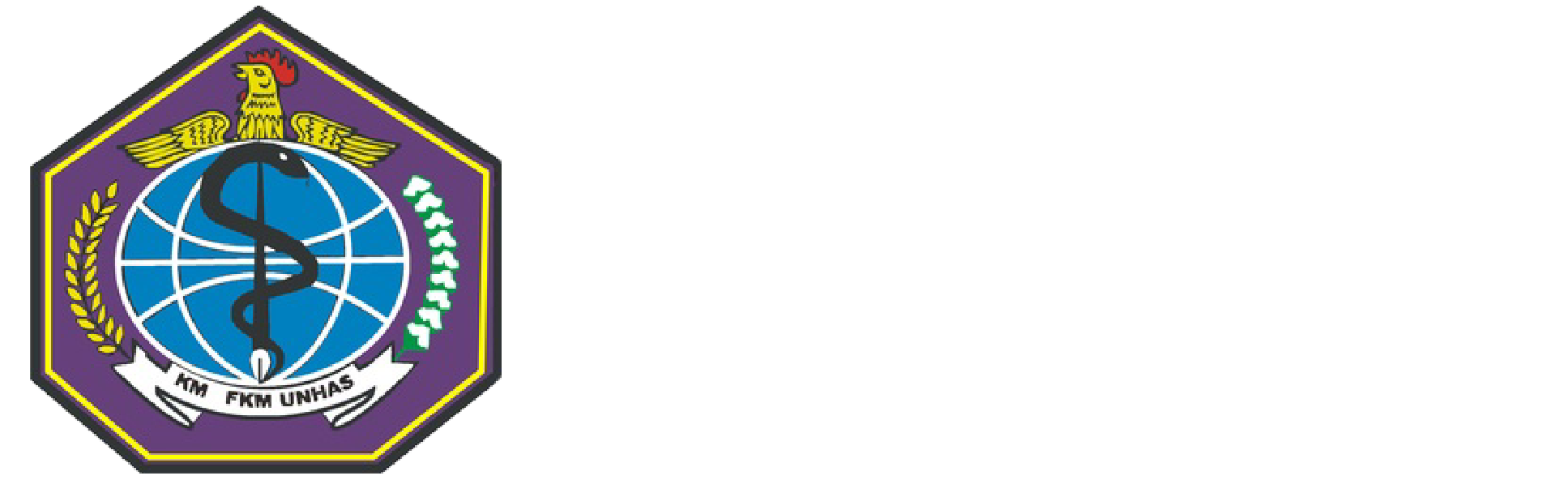Emansipasi di Tengah Krisis Neoliberalisme: Membangun Kesadaran dan Solidaritas Sosial
Dalam beberapa dekade terakhir, neoliberalisme telah menjadi paradigma dominan dalam kebijakan ekonomi dan sosial di banyak negara. Menurut Harvey (2007), prinsip utama neoliberalisme menekankan bahwa manusia dapat mencapai potensi terbaiknya melalui kebebasan individual entrepreneurial dan keahlian dalam kerangka institusional yang mempunyai karakter private property rights yang kuat, free markets dan free trade.
Neoliberalisme tidak hanya memengaruhi struktur ekonomi, tetapi juga membentuk cara berpikir masyarakat. Ideologi ini menempatkan individu sebagai aktor rasional yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan atau kegagalannya, seolah-olah faktor sosial dan struktural tidak memiliki peran. Akibatnya, ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar, sementara kelompok pekerja mengalami ketidakamanan kerja akibat sistem kontrak fleksibel dan lemahnya perlindungan sosial. Pendidikan pun mengalami komersialisasi, dimana kualitas dan akses terhadapnya ditentukan oleh kemampuan ekonomi, bukan oleh hak sebagai warga negara.
Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, gerakan emansipatoris hadir sebagai pendekatan yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari pengetahuan yang bersifat pasif dan dogmatis. Pemikiran ini mengajak individu untuk terlibat secara kritis, aktif, dan reflektif terhadap isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, gerakan ini mendorong individu untuk tidak hanya menerima pengetahuan yang diberikan, tetapi juga mempertanyakan, mengevaluasi, dan mengambil tindakan terhadap ketidakadilan sosial yang mereka amati. Dasar filosofis dari pemikiran ini berakar pada teori pendidikan kritis yang diusung oleh Paulo Freire, yang menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan. Freire (2005) berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada proses transfer pengetahuan semata, tetapi harus menjadi ruang dialog yang memungkinkan individu mengembangkan kesadaran kritis (conscientização), yaitu kemampuan untuk memahami struktur sosial yang menindas serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih adil.
Manifestasi nyata dari gerakan emansipatoris dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Misalnya gerakan Zapatista pada tahun 1994, merupakan sebuah gerakan yang berasal dari wilayah Chiapas, Meksiko. Gerakan ini awalnya berfokus pada penindasan yang dilakukan terhadap suku Indian yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, fokus perjuangan Zapatista melebar untuk melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko terhadap masyarakat di berbagai lapisan sosial. Dalam upayanya, gerakan ini berorientasi pada pembangunan otonomi daerah, yaitu dengan membentuk komunitas adat dan mengorganisir masyarakat Chiapas, serta mempromosikan pendidikan dan kesehatan di wilayah mereka. Selain itu, mereka juga memperjuangkan hak atas tanah, hak perempuan, tenaga kerja, perdagangan, perumahan, serta akses terhadap pasokan bahan bakar, sambil tetap memelihara seni, bahasa, dan tradisi asli sebagai bagian dari identitas dan keadilan sosial yang mereka tegakkan.
Demikian pula di Indonesia, gerakan emansipatoris juga dapat dilihat dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan. Salah satunya yaitu Solidaritas Perempuan Sumbawa di Desa Tarusa. Gerakan ini diwujudkan melalui program pendidikan kritis yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kondisi sosial dan budaya patriarki yang membatasi peran mereka. Melalui pendekatan dialog, refleksi, dan aksi nyata, gerakan ini mendorong perempuan untuk tidak pasif menerima peran tradisional, tetapi untuk mengembangkan kepemimpinan, berpikir kritis, dan berani menantang struktur sosial yang menindas. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai alat pembebasan intelektual yang menumbuhkan kesadaran akan ketidakadilan dan mendorong perubahan sosial yang lebih setara. Gerakan ini membuktikan bahwa pendidikan kritis dapat menjadi jembatan bagi pemberdayaan perempuan dan transformasi sosial di tingkat akar rumput.
Kedua gerakan tersebut memperlihatkan bahwa emansipasi tidak hanya bersifat teoritis, melainkan diwujudkan dalam praktik nyata melalui pembentukan komunitas yang mandiri, partisipatif, dan egaliter. Selain itu, gerakan pendidikan kritis di berbagai negara juga menjadi contoh nyata upaya melawan komodifikasi pendidikan dengan menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang pembentukan kritis, bukan sekadar pabrik tenaga kerja.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa neoliberalisme telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang bersifat sistemik melalui ketimpangan ekonomi, eksklusi sosial, dan hilangnya nilai solidaritas. Gerakan emansipatoris hadir sebagai jembatan yang menghubungkan kesadaran dan tindakan menuju tatanan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Gerakan ini menawarkan jalan keluar yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praksis, melalui pendidikan pembebasan, aksi kolektif, dan pembangunan alternatif ekonomi berbasis keadilan. Di Indonesia, semangat emansipatoris ini harus terus ditumbuhkan melalui pendidikan kritis, advokasi lingkungan, gerakan gender, serta inisiatif sosial yang berpihak pada rakyat. Dengan membangun kesadaran dan solidaritas lintas kelompok, gerakan emansipatoris dapat menjadi kekuatan transformatif yang menuntun bangsa keluar dari belenggu neoliberalisme menuju masa depan yang lebih adil, setara, dan beradab.