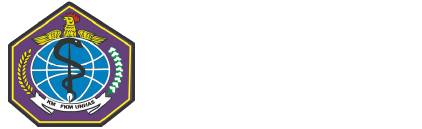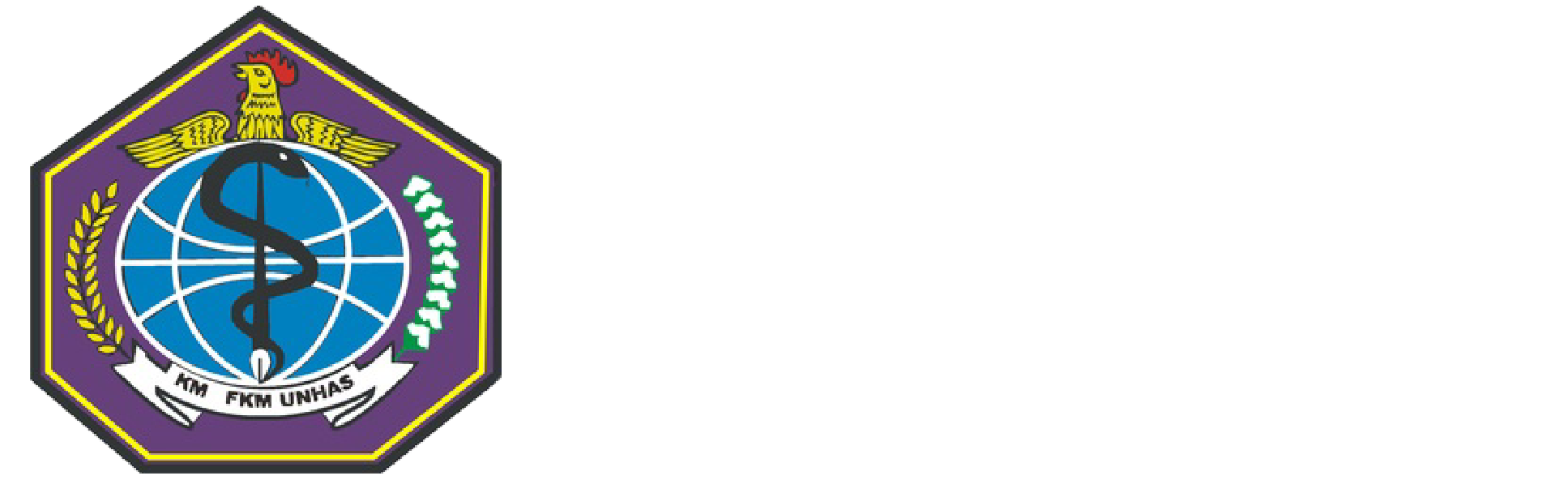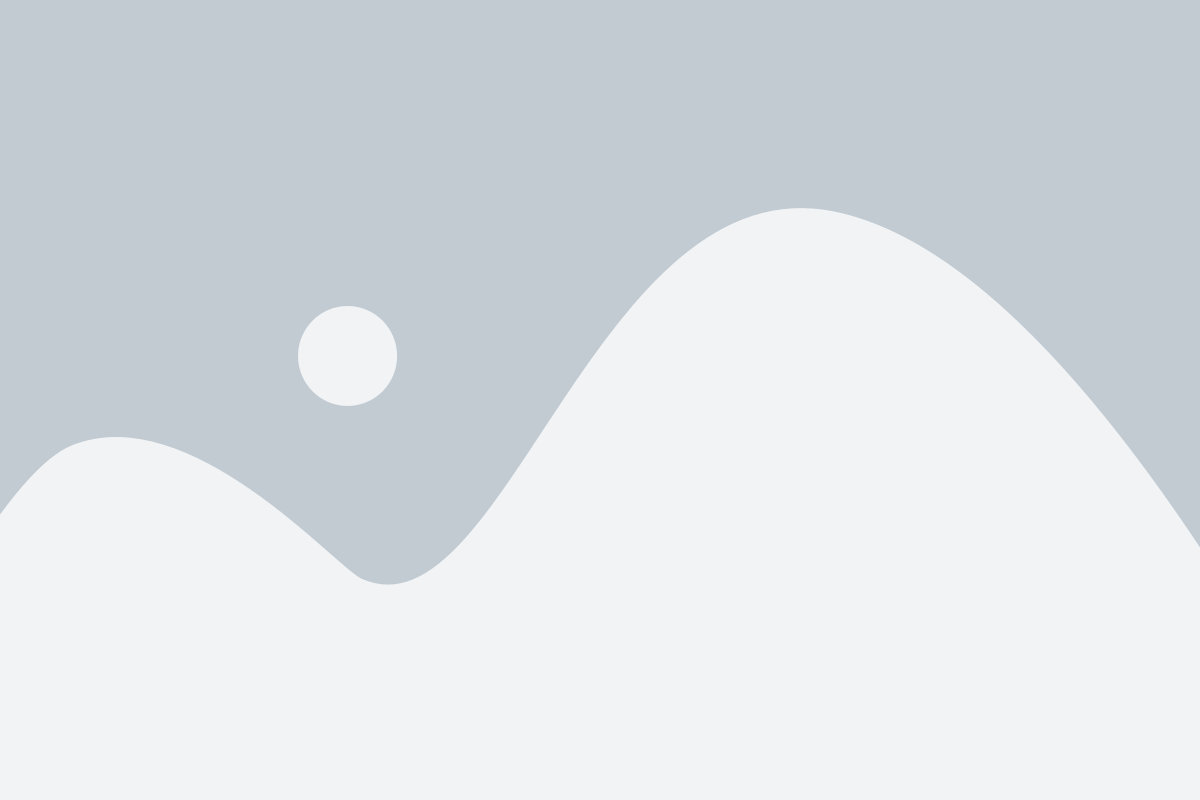
Hari Tani Nasional: Dekonstruksi Reforma Agraria Neoliberal dan Resistensi Agraria di Sulawesi Selatan
Dari Cita-Cita ke Pengkhianatan
Peringatan Hari Tani Nasional yang bersumber dari momentum historis Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, hari ini telah berubah menjadi ritual tahunan yang kosong. Di balik retorika pemerintah tentang komitmen reforma agraria, tersembunyi sebuah realitas pahit. Sebuah proyek deagrarianisasi sistematis yang mengorbankan kedaulatan petani di altar akumulasi modal. Kajian ini berupaya membongkar paradigma neoliberal yang membajak agenda reforma agraria, mengidentifikasi instrumen-instrumen negara yang menjadi alat perampasan, serta memetakan gejolak konflik agraria di Sulawesi Selatan sebagai bukti kegagalan model pembangunan yang anti-rakyat.
Romantisme UUPA 1960 dan Kekecewaan Kontemporer
UUPA 1960 merupakan puncak dari perjuangan kolektif untuk mendekolonisasi hukum agraria warisan kolonial yang feodal dan kapitalistik. UU ini dengan visioner menempatkan tanah sebagai fungsi sosial, bukan komoditas semata. Namun, enam dekade kemudian, jiwa dan raga UUPA tersebut telah dikhianati oleh rezim-rezim yang berkuasa. Implementasinya tidak lebih dari simulakra sebuah tiruan yang kehilangan substansi aslinya. Hari Tani pun terdegenerasi menjadi seremoni yang justru mengaburkan akar persoalan ketimbang menyelesaikannya.
Distorsi Neoliberal: Ketika Reforma Agraria Berubah Menjadi Legalisasi Perampasan
Klaim pemerintah mengenai keberhasilan reforma agraria melalui pencapaian target sertifikasi tanah adalah sebuah hegemoni diskursus yang berbahaya. Program seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digembar-gemborkan sebagai solusi, pada hakikatnya adalah bentuk depolitisasi dari agenda reforma agraria yang sejati. Program ini mengubah masalah struktural yang bersifat politis yakni ketimpangan penguasaan dan akses menjadi sekadar persoalan administratif dan teknis. Alih-alih mendistribusikan tanah kepada kaum tak bertanah (landless), program ini justru mengukuhkan status quo kepemilikan dan membuka pintu bagi komodifikasi tanah yang lebih masif. Reforma agraria versi pemerintah saat ini bukanlah alat untuk memutus mata rantai ketergantungan dan keterbelakangan petani, melainkan sebuah mesin untuk melicinkan jalan bagi penetrasi modal dengan mengamankan kepastian hukum bagi investor.
Sulawesi Selatan: Episentrum Perlawanan terhadap Akumulasi Melalui Perampasan
Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menempatkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan konflik agraria tertinggi di Indonesia (37 konflik pada 2024) bukanlah sebuah kebetulan statistik. Ini adalah konsekuensi logis dari agresifnya model pembangunan ekstraktif dan ekspansif di kawasan ini. Tingginya angka konflik tersebut merupakan indikator nyata dari kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak agraria warga negaranya. Setiap konflik yang tercatat merepresentasikan sebuah episode perlawanan lokal terhadap dispossesi yang dilakukan oleh negara dan korporasi.
Penyimpangan yang Terinstitusionalisasi: Reforma Agraria Palsu
Penyimpangan yang terjadi bukanlah kesalahan teknis, melainkan sebuah kesengajaan kebijakan (policy by design) yang berorientasi pada akumulasi kapital. Pergeseran dari redistribusi tanah (asset reform) ke legalisasi aset (administrative reform) adalah bentuk pelemahan secara sistematis terhadap agenda redistributif UUPA. Dalam paradigma ini, negara tidak lagi hadir sebagai pelindung rakyatnya, tetapi sebagai kaki tangan modal yang memfasilitasi proses perampasan ruang hidup rakyat dengan mengatasnamakan investasi dan pembangunan.
Instrumen Kekerasan Negara yang Dilegalkan
Negara tidak lagi menggunakan kekerasan secara kasar saja, tetapi telah menyempurnakannya melalui seperangkat instrumen hukum dan kebijakan yang tampak rasional, namun pada dasarnya represif.
- Bank Tanah (Land Bank): Di balik kemasannya yang teknokratis, Bank Tanah berpotensi menjadi mesin sentralisasi penguasaan tanah oleh negara. Mekanisme ini berisiko mengalienasi tanah-tanah yang seharusnya didistribusikan untuk reforma agraria sejati, justru untuk dijadikan komoditas dalam pasar tanah atau dijual maupun disewakan kepada korporasi besar. Ini adalah bentuk modern dari enclosure of the commons yang dilembagakan.
- Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kedua instrumen ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama. UU Cipta Kerja berfungsi sebagai pemangkas hak-hak rakyat dan perlindungan lingkungan, sementara PSN adalah lokasi dimana pencabutan hak tersebut diimplementasikan. Proyek-proyek seperti infrastruktur masif, kawasan industri, dan pertambangan telah menjadi alat legitimasi untuk mengusir masyarakat dari tanah leluhurnya. Konsep “kepentingan umum” dengan curang dibajak maknanya menjadi identik dengan “kepentingan korporasi”.
Kronologi Krisis: Kasus-Kasus Konflik Agraria di Sulsel sebagai Bukti Negara yang Memusuhi Rakyatnya
- Mafia Tanah di Makassar: Kasus Bara‑Baraya menjadi contoh nyata. Warga yang telah puluhan tahun menempati tanah di sana tiba-tiba digugat dengan menggunakan sertifikat pengganti yang diduga bermasalah. Sertifikat tersebut diterbitkan pasca laporan kehilangan yang mencurigakan, sementara tanahnya sudah terjual ke pihak lain. Meski status lahan masih diperdebatkan, pengadilan tetap memerintahkan eksekusi terhadap ratusan warga. Fenomena ini menunjukkan bagaimana birokrasi pertanahan yang korup dan aparat penegak hukum yang lemah telah menciptakan ekosistem yang subur bagi premanisme properti. Mafia tanah adalah aktor non-state yang diuntungkan oleh kekosongan dan kelemahan kedaulatan negara di sektor agraria.
- Konflik lahan di Polongbangkeng merupakan konflik agraria yang mencerminkan benturan antara kedaulatan pangan, hak petani atas lahan produktif, dengan kepentingan institusi besar seperti perusahaan perkebunan (PTPN XIV), yang menguasai lahan melalui HGU (Hak Guna Usaha). Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perkebunan tebu dan penggunaan komersial lainnya telah menyebabkan petani kehilangan akses atas tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Namun, konflik ini tidak hanya sebatas perebutan klaim kepemilikan, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara menggunakan aparatus kekerasannya untuk melindungi kepentingan korporasi. Pada panen tebu 2025, ratusan aparat dikerahkan untuk mengamankan lahan yang diklaim PTPN XIV. Kehadiran aparat dalam jumlah besar, alih-alih meredam ketegangan, justru menimbulkan bentrokan dan menegaskan posisi negara yang represif terhadap rakyat kecil. Praktik ini memperlihatkan bahwa konflik agraria di Takalar tidak bisa dilepaskan dari persekutuan antara korporasi dan aparat keamanan, yang secara sistematis merampas hak petani dan melemahkan perjuangan mereka.
- Ancaman Tambang Emas di Lima Kabupaten: Ekspansi industri ekstraktif ini adalah wujud dari imperialisme ekologis dimana modal datang, mengeksploitasi, mencemari, dan pergi setelah sumber daya habis, meninggalkan kerusakan permanen dan masyarakat yang tercerabut. Kebijakan energi transisi justru berpotensi mempercepat ekstraksi ini, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak (ICW, 2023).
- Reklamasi Pulau Lae-Lae adalah wujud nyata pengkhianatan negara terhadap rakyat pesisir. Dimulai sejak proyek Center Point of Indonesia (CPI) diluncurkan pada awal 2010, reklamasi mulai mengancam wilayah tangkap nelayan dan ekosistem pesisir. Pada 2016, warga Pulau Lae-Lae mulai melakukan penolakan terbuka, termasuk aksi protes dan gugatan hukum, namun pemerintah tetap mengabaikan suara mereka. Atas nama kota kelas dunia, negara justru memfasilitasi perampasan ruang hidup nelayan demi kepentingan investor. Reklamasi merusak ekosistem, menggusur komunitas, dan menjadi simbol kolonialisasi ruang oleh modal.
Dampak Sosial: Trauma Multidimensi yang Diwariskan
Konflik agraria tidak hanya melahirkan persoalan ekonomi berupa hilangnya akses terhadap tanah dan sumber penghidupan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang kompleks dan berlapis. Kemiskinan hanyalah salah satu wajah dari akibat konflik, sebab yang lebih mendalam adalah proses kemiskinan struktural yang diwariskan lintas generasi. Selain itu, masyarakat yang identitas kulturalnya terikat erat dengan tanah dipaksa tercerabut dari akar tradisi mereka. Dalam konteks komunitas agraris, tanah bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga ruang sosial dan kultural yang menyimpan sejarah, nilai, dan identitas kolektif. Ketika tanah dirampas, yang hilang bukan hanya lahan, tetapi juga keberlangsungan budaya dan jati diri komunitas.
Dampak lain yang kerap luput dari perhatian adalah beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan. Dalam banyak komunitas tani, perempuan berperan penting sebagai penjaga benih, pengetahuan lokal, dan pengelola pangan keluarga. Hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya alam membuat mereka kehilangan ruang untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus memaksa mereka menanggung double burden: mengurus rumah tangga di tengah situasi krisis dan pada saat yang sama kehilangan basis ekonomi untuk menopang keluarga. Kondisi ini memperparah ketimpangan gender dalam masyarakat pedesaan.
Lebih jauh lagi, konflik agraria meninggalkan luka sosial yang dalam. Generasi muda yang tumbuh di tengah konflik menyaksikan secara langsung bagaimana aparat negara, yang seharusnya melindungi rakyat, justru menjadi bagian dari represi. Situasi ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai generasi trauma anak-anak dan remaja yang melihat masa depan mereka hancur karena perampasan tanah, intimidasi, dan kekerasan. Trauma kolektif ini berisiko diwariskan dan memperpanjang siklus ketidakadilan agraria di masa depan.
Solusi dan Tuntutan: Rebut Kedaulatan Rakyat, Wujudkan Reforma Agraria Sejati Adil Gender
Memperingati Hari Tani tidak cukup hanya dengan seremoni atau retorika pemerintah. Momentum ini harus dijadikan pijakan untuk menegaskan kembali agenda kerakyatan: merebut kembali kedaulatan rakyat atas tanah dan ruang hidup. Reforma agraria sejati hanya bisa diwujudkan bila negara berhenti menjadi alat akumulasi modal dan kembali pada mandat konstitusi serta UUPA 1960.
Pertama, redistribusi tanah untuk rakyat kecil harus dikedepankan, bukan sekadar sertifikasi tanah yang justru melanggengkan monopoli. Tanah yang dikuasai oleh negara melalui Bank Tanah, HGU korporasi, maupun proyek strategis harus segera dialihkan untuk petani tak bertanah, buruh tani, masyarakat adat, dan perempuan tani. Tanah adalah sumber kehidupan, bukan komoditas yang diperjualbelikan
Hentikan proyek perampasan ruang hidup rakyat. PSN, tambang emas di lima kabupaten Sulsel, reklamasi Lae-Lae dan Untia, serta berbagai proyek infrastruktur spekulatif harus segera dievaluasi dan dihentikan bila terbukti merampas lahan rakyat. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang berpihak pada rakyat, menjaga ekosistem, dan memperkuat kedaulatan pangan, bukan menyerahkan sumber daya kepada investor.
Lawan kriminalisasi petani dan rakyat pejuang agraria. Setiap represi aparat kepada rakyat yang membela tanahnya adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Negara harus menindak mafia tanah, menghentikan intimidasi aparat, dan memberikan perlindungan hukum bagi petani, nelayan, serta masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidupnya.
Wujudkan reforma agraria adil gender. Perempuan tani harus diakui sebagai subjek penuh reforma agraria, dengan hak yang sama atas tanah dan sumber daya. Tanpa keterlibatan dan kepemimpinan perempuan, reforma agraria sejati tidak akan pernah terwujud.
Hari Tani adalah momentum untuk menegaskan bahwa tanah bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan simbol kedaulatan, keadilan, dan martabat rakyat
Referensi:
LBH Makassar. (2023). “Aliansi Gerak: Makassar Tidak Ada Tanah, Tidak Ada Reforma Agraria, Tidak Akan Ada Suara Rakyat!”
LBH Makassar. (2024). “Sulawesi Selatan Darurat Agraria dan Demokrasi: Selamatkan Konstitusi dan Jalankan Reforma Agraria Sejati yang Adil Gender!”
Kompas.com. (2025). “37 Konflik Tanah Terjadi di Sulawesi Selatan, Terbanyak se-Indonesia.”
Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). “Membedah Ancaman Korupsi dan Kerusakan Lingkungan di Balik Transisi Energi.”
Akbar, A., et al. (2022). “Bank Tanah dalam Pusaran Neoliberalisasi Agraria di Indonesia.” Jurnal Agraria dan Pertanahan rakyat).