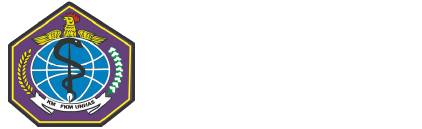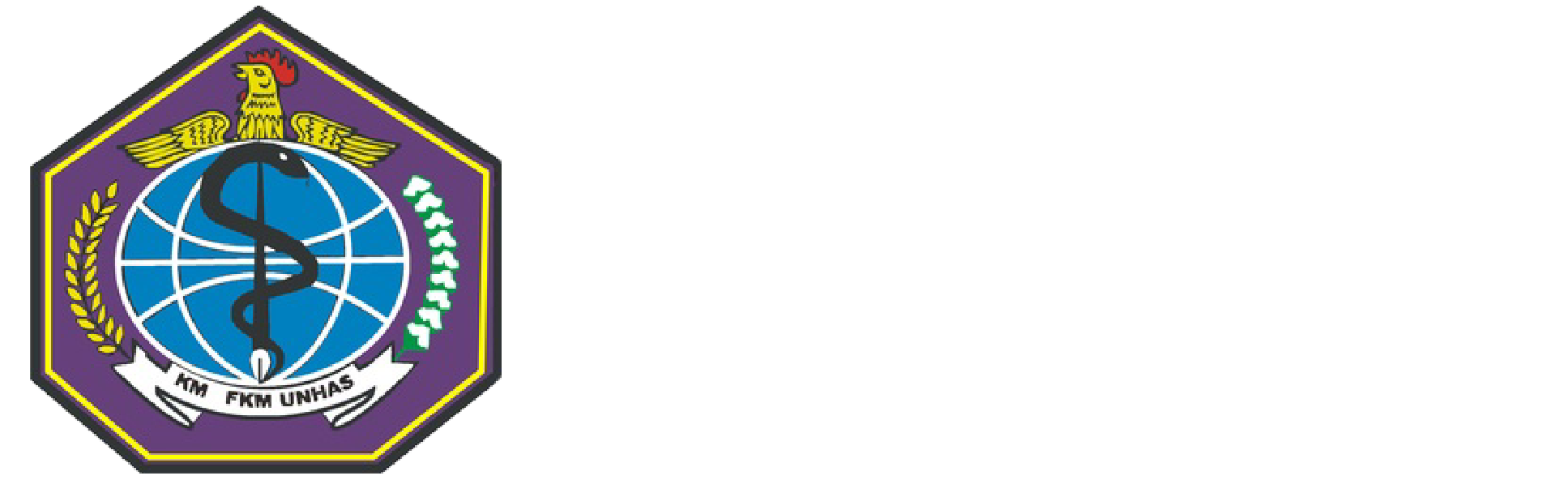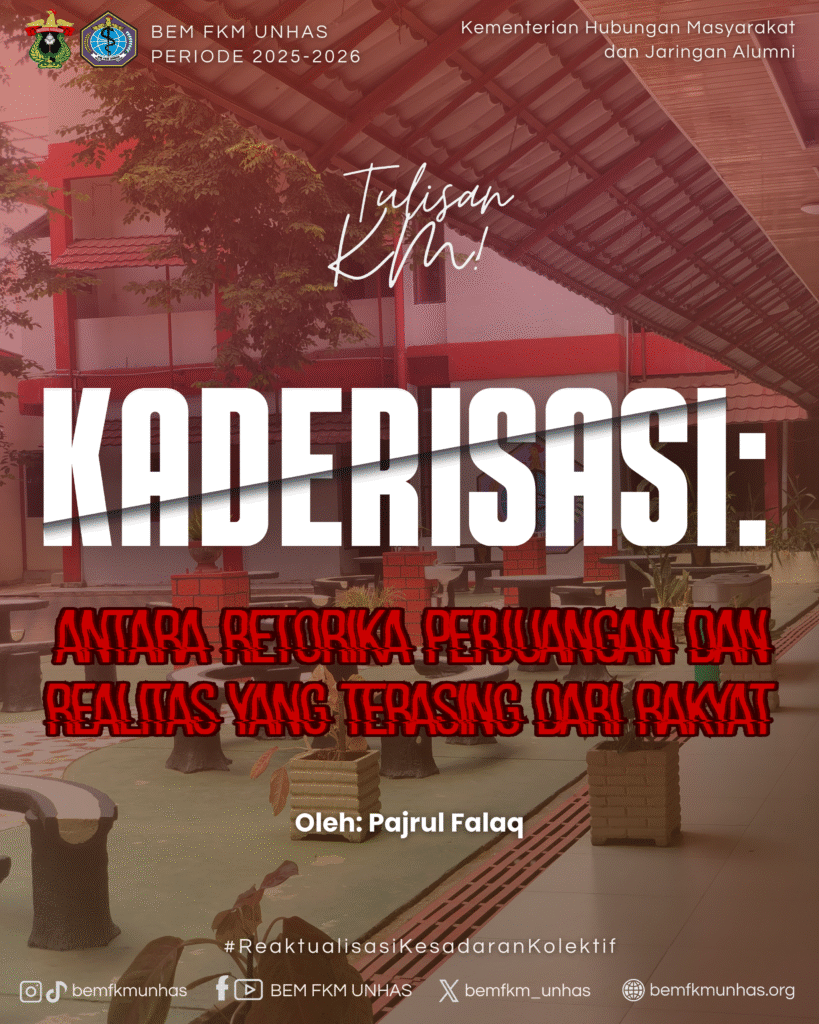
Kaderisasi: Antara Retorika Perjuangan dan Realitas yang Terasing dari Rakyat
Kaderisasi seringkali dielu-elukan sebagai ruang alternatif untuk membentuk kader progresif yang berkomitmen membela kaum tertindas. Ia diklaim sebagai arena pendidikan politik, penguatan ideologi, dan pembentukan militansi gerakan. Namun, praktik yang berlangsung di banyak organisasi hari ini justru menampilkan paradoks: kaderisasi lebih menyerupai ruang penjejalan materi ketimbang proses pembentukan kesadaran kritis dan praksis transformatif. Alih-alih menjadi sarana perjuangan, kaderisasi kerap berfungsi sebagai mekanisme reproduksi habitus akademik yang elitis, formalistik, dan terputus dari denyut nadi rakyat.
Dalam kerangka teori Antonio Gramsci, kader yang lahir dari model seperti ini cenderung menjadi intelektual tradisional mereka yang terjebak dalam wacana, simbol, dan legitimasi akademik, tanpa menjadi intelektual organik yang melekat dengan perjuangan kelas tertindas. Kaderisasi akhirnya sekadar melahirkan kader yang “pintar berbicara” namun minim keberpihakan praksis. Materi-materi ideologi, filsafat, atau sejarah pergerakan memang penting, tetapi jika ia tidak bersentuhan dengan realitas konkret, kaderisasi hanya memperpanjang jarak antara mahasiswa dengan rakyat yang katanya hendak dibela.
Kesenjangan ini terjadi karena kaderisasi lebih dilihat sebagai ritual organisasi ketimbang proses politik dan sosial. Kegiatan kaderisasi banyak dipenuhi diskusi kelas, ceramah, atau simulasi yang tidak pernah benar-benar mengasah kepekaan sosial kader. Padahal, pendidikan politik yang sejati seharusnya berakar pada pengalaman nyata; sebagaimana Paulo Freire tekankan dalam Pedagogy of the Oppressed, pendidikan transformatif lahir dari dialog dengan realitas penindasan, bukan dari ruang kelas yang steril.
kaderisasi yang stagnan dalam ruang teoritis berpotensi menghasilkan habitus akademis yang elitis. Menurut Pierre Bourdieu, habitus yang terbentuk dalam ruang sosial yang homogen akan memperkuat dominasi simbolik. Kader kemudian lebih menginternalisasi nilai elitisme kampus atau organisasi daripada memahami dinamika struktural masyarakat. Akibatnya, mereka tidak mampu menjadi agen perubahan sosial karena tidak memiliki keterampilan advokasi, pemberdayaan, maupun basis massa yang riil.
Tidak hanya itu realitas lapangan mengungkapkan banyak metode kaderisasi justru terjebak dalam pola yang itu-itu saja, seolah menjadi tradisi sakral yang tak boleh digugat. Kaderisasi berhenti pada pengulangan ritual, formalitas agenda, dan penjejalan materi yang jauh dari esensi pembebasan. Akibatnya, proses kaderisasi kehilangan daya transformasi dan justru mereproduksi keterasingan kader dari rakyat.
Masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga kultural. Banyak organisasi menginternalisasi budaya kaderisasi lama sebagai identitas dan kebanggaan. Pola ini diwariskan turun-temurun tanpa refleksi kritis, sehingga perubahan dianggap sebagai ancaman terhadap “keaslian” tradisi organisasi. Padahal, budaya yang didewakan ini justru mematikan daya inovasi dan membuat organisasi gagal menjawab tantangan zaman. Di sinilah letak paradoksnya organisasi yang mengklaim progresif justru bersikap konservatif terhadap proses kaderisasinya sendiri.
Metode kaderisasi yang stagnan menjauhkan kader dari tujuan awalnya. Alih-alih membentuk pengorganisir rakyat, kaderisasi kerap hanya menghasilkan mahasiswa yang fasih berbicara, lihai berdiskusi, dan menguasai jargon ideologi, namun minim keterampilan praktis untuk berjuang bersama rakyat. Ruang kaderisasi yang diidealkan sebagai sarana pembebasan malah terjebak menjadi arena seleksi eksklusif yang memperkuat hierarki simbolisme, dan pembentukan habitus elitis.
Jika merujuk pada gagasan Paulo Freire, pendidikan pembebasan tidak mungkin lahir dari ruang yang steril dan hierarkis. Pendidikan sejati adalah proses dialogis yang menghubungkan pengetahuan dengan realitas penindasan Kecenderungan untuk mempertahankan pola lama ini menunjukkan bahwa kaderisasi bukan hanya soal metode, tetapi juga struktur kuasa dan budaya organisasi. Banyak pihak enggan mengubahnya karena pola tersebut memberi legitimasi dan kenyamanan bagi mereka yang sudah mapan di dalam struktur. Akhirnya, kaderisasi tidak lagi menjadi alat pembebasan, tetapi mekanisme reproduksi kekuasaan internal.
Lebih parahnya lagi, metode kaderisasi yang dijalankan justru sering mendahului konsep yang dirumuskan. Alih-alih merancang metode berdasarkan analisis kebutuhan, tujuan ideologis, dan konteks sosial, organisasi cenderung mempertahankan pola lama dan memaksa konsep untuk menyesuaikan diri dengan metode yang ada. Akibatnya, konsep kaderisasi tidak lahir secara dialektis dari realitas dan kebutuhan zaman, melainkan menjadi justifikasi formal bagi metode yang sudah terlanjur mapan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kaderisasi di banyak organisasi telah kehilangan sifatnya sebagai ruang eksperimentasi progresif. Metode yang semestinya menjadi alat justru berubah menjadi doktrin. Ia diperlakukan sebagai tradisi yang suci dan tak boleh dipertanyakan. Akhirnya, proses pendidikan politik yang seharusnya fleksibel dan kontekstual malah membeku dalam format-format lama materi padat dalam ruang kelas, simulasi formalistik, dan tahapan kaderisasi yang lebih menekankan pengukuhan status dibanding pembentukan kesadaran kritis.
Di titik ini, metode kaderisasi menjadi penjara bagi konsep. Organisasi yang mestinya adaptif terhadap dinamika sosial malah terjebak dalam fetisisme metodologis sebuah kecenderungan untuk mengkultuskan metode, bukan tujuan. Konsep yang seharusnya menjadi landasan filosofis dan strategis dipaksa menyesuaikan diri dengan rutinitas teknis yang diulang setiap tahun. Akibatnya, kaderisasi kehilangan relevansi dan daya dobraknya ia tidak lagi menjadi sarana pembebasan, melainkan sekadar mekanisme reproduksi budaya organisasi yang elitis.
Secara teoritis, hal ini bisa dilihat melalui perspektif Pierre Bourdieu tentang habitus dan reproduksi sosial. Metode kaderisasi yang mengulang pola lama akan melanggengkan habitus tertentu dalam organisasi membentuk kader untuk meniru cara berpikir, berbicara, dan bergerak sesuai pola lama, bukan untuk merumuskan strategi baru. Ini menjadikan organisasi mahasiswa lebih sibuk menjaga kontinuitas simbolik ketimbang melakukan refleksi kritis terhadap efektivitas gerakannya.
Lebih jauh lagi, kondisi ini juga menunjukkan adanya struktur kuasa internal. Mereka yang pernah mengalami metode lama akan cenderung mempertahankannya karena metode tersebut memberi legitimasi terhadap posisi mereka. Di sini, kaderisasi berfungsi bukan hanya sebagai ruang pendidikan politik, tetapi juga sebagai instrumen kontrol dan reproduksi hierarki. Maka, tak mengherankan jika pembaruan konsep sering ditolak atau dianggap tidak perlu.
Jika pola seperti ini terus dibiarkan, kaderisasi akan terus menjauh dari tujuannya sebagai ruang alternatif untuk mencetak kader progresif. Pendidikan politik sejati, sebagaimana ditegaskan Paulo Freire, haruslah dialogis, kontekstual, dan memberdayakan. Metode bukan tujuan, melainkan alat untuk membumikan konsep dalam realitas konkret. Kita perlu membalik logika ini konsep harus menjadi pijakan utama, sementara metode bersifat dinamis dan selalu diperbarui sesuai kebutuhan perjuangan rakyat.
Kacaunya lagi, metode kaderisasi yang terus diulang-ulang itu tidak pernah benar-benar dievaluasi secara mendalam. Tidak ada refleksi serius apakah metode tersebut masih mampu menjawab tujuan mulia kaderisasi yakni membentuk kader progresif yang berkomitmen pada perjuangan rakyat tertindas. Tidak ada pertanyaan kritis apakah metode itu masih relevan dengan realitas sosial-politik hari ini, ataukah ia hanya sekadar tradisi yang dijalankan demi menjaga kontinuitas simbolik organisasi.
Ketiadaan evaluasi membuat kaderisasi terjebak menjadi ritual kosong. Agenda-agenda pengkaderan sering disusun seperti formalitas rutin tahunan ada panitia, ada materi, ada tahapan tetapi tidak ada refleksi tentang sejauh mana kaderisasi benar-benar mengubah kesadaran kader, memperkuat ideologi perjuangan kader, atau membangun basis massa. Organisasi sibuk memastikan kaderisasi berjalan lancer, banyak kader yang lulus yang dinilai dari proses yang sangat normatif secara teknis, tetapi melupakan pertanyaan mendasar: apakah kaderisasi benar-benar efektif membentuk kader yang berpihak dan punya pijakan idepogis, atau justru sekadar mencetak intelektual elitis yang jauh dari tujuan mulia kaderisasi.
Fenomena ini menyingkap problem mendasar dalam budaya organisasi mahasiswa yakni anti refleksi dan anti pembaruan. Banyak pihak menganggap metode kaderisasi lama sudah teruji hanya karena diwariskan dari generasi ke generasi, padahal ketidakmampuan untuk mengevaluasi dan memperbarui metode adalah tanda kematian intelektual sebuah organisasi. Metode yang tidak dikaji ulang akan kehilangan konteksnya, menjadi kaku, dan akhirnya tidak relevan dengan tantangan gerakan saat ini.
Dalam perspektif Paulo Freire, pendidikan pembebasan hanya mungkin lahir dari proses refleksi dan aksi yang terus-menerus. Tanpa refleksi, kaderisasi berubah menjadi proses “perbankan” pendidikan, di mana kader dianggap wadah kosong untuk diisi materi, bukan subjek aktif yang mengkritisi realitas. Lebih jauh, Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa habitus organisasi yang homogen dan tidak pernah dikritisi akan menghasilkan reproduksi simbolik—yakni pengulangan struktur lama tanpa ada lompatan kesadaran. Inilah yang terjadi: metode lama terus diulang tanpa evaluasi, menghasilkan kader-kader dengan pola pikir yang sama, tanpa kemampuan adaptasi dan inovasi.
Ketika evaluasi tidak pernah dilakukan, organisasi kehilangan peluang untuk melakukan pembaruan strategi gerakan. Padahal, realitas sosial berubah cepat: represi negara semakin canggih, eksploitasi rakyat semakin brutal, dan kapitalisme merambah segala lini kehidupan. Namun, kaderisasi yang tidak reflektif hanya mengulang pola lama yang tidak lagi sesuai dengan medan pertempuran hari ini.
Dari titik kesadaran inilah perlu dilakukan perombakan radikal. Pengaderan yang progresif harus dimulai proses pembentukan kader organik yang mengacu pada gagasan Antonio Gramsci yakni kader yang tidak hanya menguasai teori, tetapi melekat dan berakar dalam perjuangan kelas tertindas. Pendidikan politik harus diarahkan untuk mencetak pengorganisir rakyat, bukan intelektual yang hanya fasih berbicara di ruang diskusi.
Untuk mencapai tujuan ini, metode kaderisasi harus dibalik orientasinya: dari model ceramah dan penghafalan menuju pendidikan berbasis realitas sosial. Setiap kaderisasi perlu memberikan porsi besar, setidaknya hampir separuh waktunya, untuk turun langsung ke basis rakyat seperti buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, komunitas miskin kota, dan wilayah terdampak perampasan ruang hidup. Pengalaman langsung di lapangan akan menjadi bahan analisis dan refleksi, sehingga materi ideologi, filsafat, dan strategi gerakan tidak lagi mengambang, melainkan berakar pada realitas yang dihadapi rakyat. Kader harus dilatih untuk melakukan riset sosial sederhana memetakan persoalan struktural, mengenali aktor dominan, serta merumuskan strategi perlawanan bersama.
Kurikulum pengaderan juga harus disusun secara dialektis antara teori dan praksis. Materi analisis sosial, sejarah pergerakan, dan filsafat perjuangan penting untuk mengasah kesadaran kritis, tetapi harus diimbangi dengan pelatihan keterampilan organisasi, advokasi, manajemen aksi, penggunaan media, dan pengorganisasian massa. Setiap sesi materi harus diakhiri dengan praktik langsung atau rencana tindak lanjut agar tidak berhenti di ruang diskusi. Metode pembelajaran pun perlu dirombak: diskusi kelompok kecil, studi kasus nyata, simulasi aksi, hingga teater rakyat bisa menggantikan pola ceramah satu arah yang membosankan dan mematikan kreativitas peserta.
Selain itu, diperlukan sistem mentor kolektif yang menempatkan kader senior sebagai pendamping aktif bagi peserta pengaderan. Setiap kader baru tidak hanya berinteraksi dengan panitia secara formal, tetapi memiliki mentor yang siap membimbing, berbagi pengalaman lapangan, dan membangun hubungan solidaritas. Hal ini akan membantu kader baru memahami gerakan secara lebih nyata, serta memperkuat kultur kolektif yang egaliter, bukan hierarkis.
Reformasi kaderisasi juga harus menyentuh aspek evaluasi. Selama ini evaluasi kaderisasi hanya menjadi formalitas untuk menentukan kelulusan, padahal seharusnya menjadi ruang refleksi mendalam tentang efektivitas metode dan relevansi materi. Evaluasi harus mencakup kemampuan praksis kader: sejauh mana peserta dapat menganalisis situasi politik, membangun jaringan massa, atau mengorganisir kampanye dan aksi. Refleksi kolektif pasca-pengaderan wajib diadakan untuk mengkritisi metode, memberi ruang bagi peserta menyampaikan pandangan mereka secara setara, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pembaruan metode kaderisasi di tahun berikutnya.
Di samping pembaruan teknis, pengaderan progresif menuntut transformasi kultural. Budaya senioritas dan glorifikasi tradisi lama harus dihapuskan karena hanya melanggengkan feodalisme internal organisasi. Pengaderan harus membangun kultur dialogis, kesetaraan, dan militansi kolektif. Ritual simbolik yang tidak relevan perlu diganti dengan kerja konkret: proyek advokasi, pendampingan komunitas, riset lapangan, dan kampanye isu strategis. Setiap angkatan kaderisasi seharusnya meninggalkan kontribusi nyata bagi rakyat, bukan hanya foto dokumentasi acara.
REFERENSI :
- Paulo Freire. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.
- Paulo Freire. (1996). Letters to Cristina: Reflections on My Life and Work. Routledge.
- Henry A. Giroux. (1983). Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition. Bergin & Garvey.
- Antonio Gramsci. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.
- Peter D. Thomas. (2009). The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony, and Marxism. Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage.
- Pierre Bourdieu. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press.
- John D. McCarthy & Mayer N. Zald. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology, 82(6), 1212–1241.
- Frances Fox Piven & Richard Cloward. (1977). Poor People’s Movements: Why They Succeed, How They Fail. New York: Vintage Books.
- Doug McAdam, Sidney Tarrow, & Charles Tilly. (2001). Dynamics of Contention. Cambridge University Press.
- Ivan Illich. (1971). Deschooling Society. New York: Harper & Row.
- Bell Hooks. (1994). Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom. Routledge.
- Hery Setyawan. (2013). Gerakan Mahasiswa: Strategi dan Taktik Organisasi. Yogyakarta: Resist Book.
- Mujiburrahman & Zainal Abidin Bagir. (2014). Gerakan Sosial di Indonesia: Perspektif, Konsep, dan Pengalaman. Yogyakarta: CRCS.
- Wilson. (2012). Politik Rakyat dan Gerakan Sosial. Yogyakarta: Resist Book.