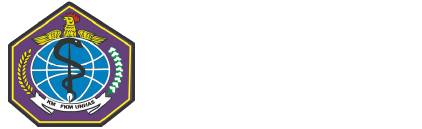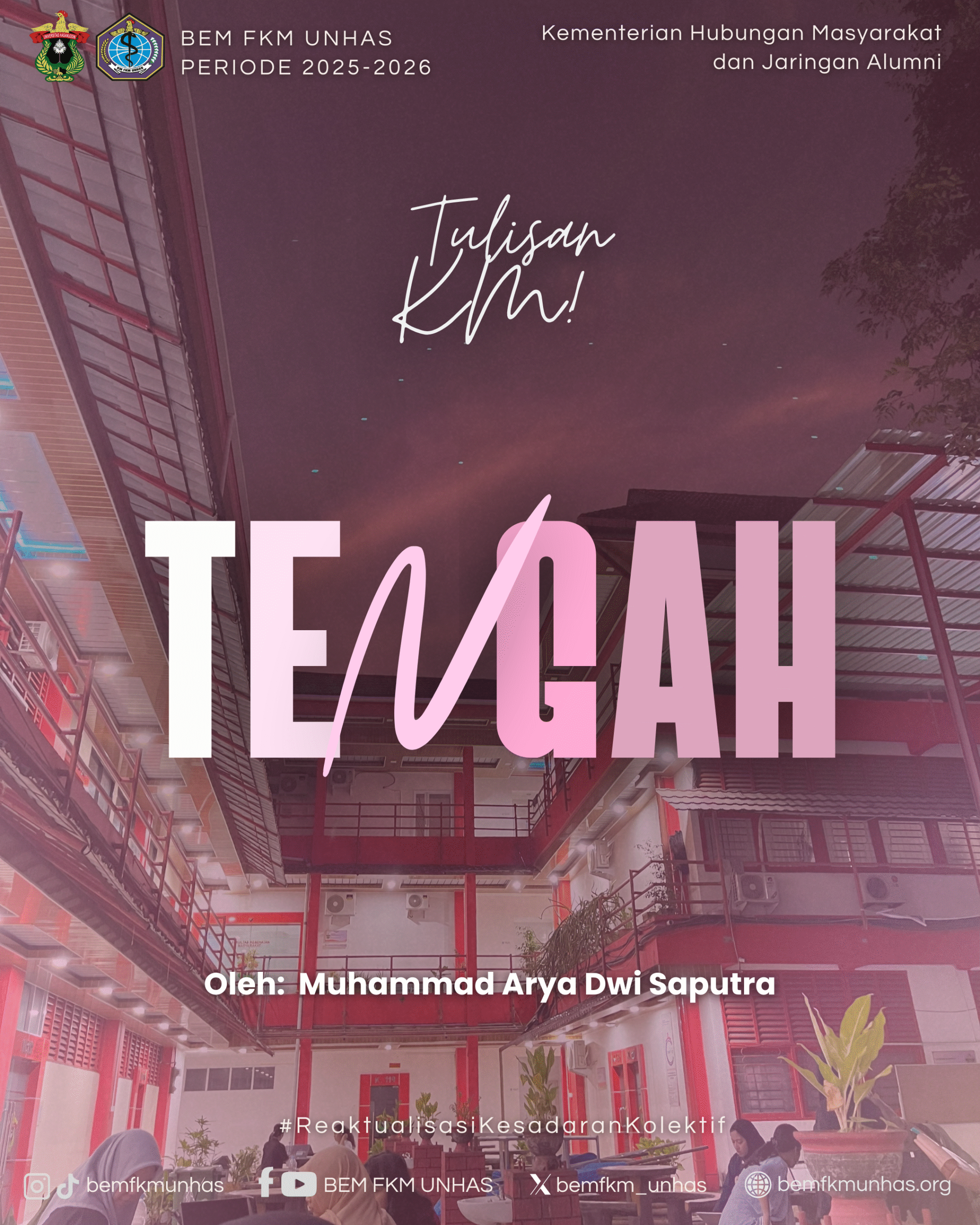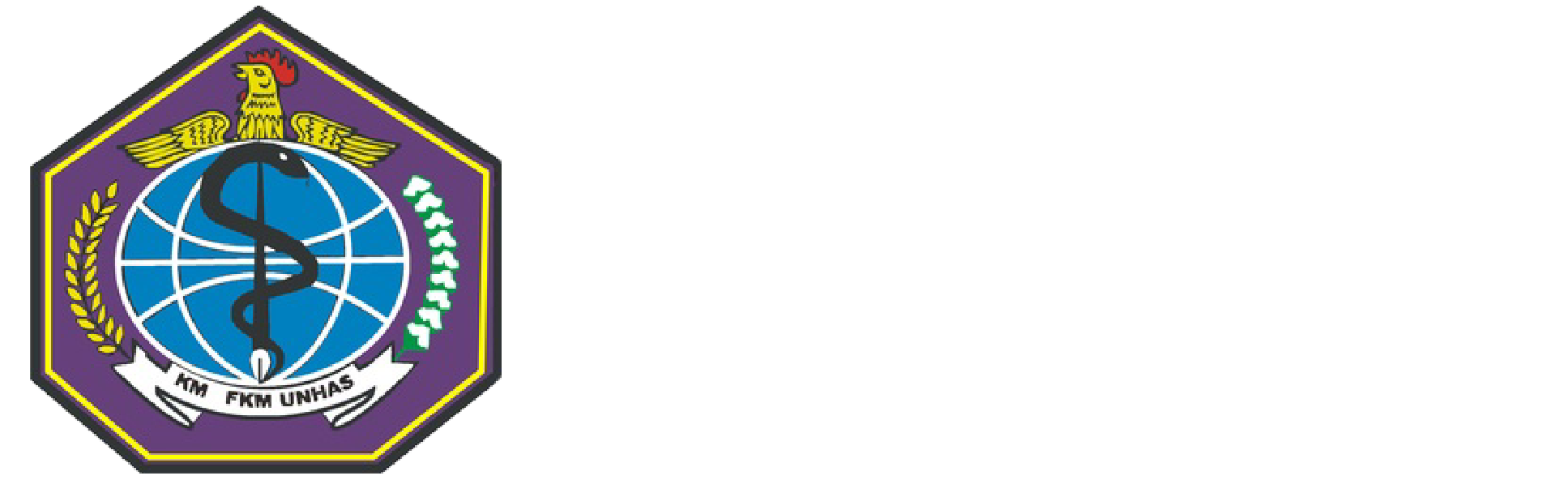Kapitalisme sebagai sistem ekonomi mendominasi hampir semua sudut dunia. Bagi sebagian besar kita, kapitalisme begitu menjadi bagian dari kehidupan kita sampai-sampai ia tak lagi kasat mata, layaknya udara yang kita hirup. Kita tidak menyadarinya, seperti ikan tidak menyadari air tempat mereka berenang. Etos, pandangan, dan nilai-nilai internal kapitalismelah yang kita serap dan biasakan siring kita tumbuh bersamanya. Tanpa disadari, kita belajar bahwa kerakusan, eksploitasi atas buruh, dan kompetisi (antar manusia, bisnis, bangsa) bukan hanya bisa dimaklumi, melainkan baik bagi masyarakat karena turut membuat perekonomian kita berfungsi secara efisien.
Dalam pengertian yang paling singkat, kapitalisme adalah suatu sistem sosial dan ekonomi di mana para pemilik kapital (atau kapitalis) mengambil surplus produk yang dihasilkan oleh produsen langsung (atau buruh), yang membuat akumulasi kapital bagi para pemilik tersebut. Produksi mengejawantahkan bentuk material dan produksi komoditas bagi pasar dengan tujuan menciptakan laba dan mendorong akumulasi. Individu-individu dalam sistem ini mengejar kepentingan pribadi mereka, yang hanya diimbangi oleh pesaing mereka dan kekuatan-kekuatan impersonal dari pasar.
Sebagai sistem global, kapitalisme membentuk sebuah ruang abstrak. Maksudnya, ruangan dunia bisnis, baik berskala nasional maupun internasional dan ruang tentang kekuasaan uang dan politik. dalam hal ini para kapitalis berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dan menambah pundi-pundi kekayaan dan politiknya dengan melakukan segala cara ekspansi. Untuk melakukan ekspansi besar-besaran tentunya membutuhkan sebuah alat agar ekspansi dapat berjalan dengan mulus demi mempertahankan kekuasaan uang mereka.
Berangkat dari perkembangan globalisasi tersebut, tentunya juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Saat ini, manusia melakukan serangkaian penindasan yang ditutupi dengan maksud-maksud kemuliaan. Hal ini menjadi senjata utama kapitalis dalam melakukan eksploitasi dan ekspansi besar-besaran terhadap suatu objek yang menurut mereka dapat menambah pundi-pundi kekayaan bagi para pemilik modal. Dimana dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi segala sesuatu dapat dengan mudah dilakukan dengan melakukan penelitian di dalam sektor-sektor ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi.
Berbicara tentang teknologi, kapitalisme jauh dari kata netral. Kapitalisme senantiasa mendukung teknologi tertentu yang dapat memperbesar laba, akumulasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan jelas kapitalisme punya riwayat menggencarkan teknologi yang paling merusak lingkungan. Dalam ketergesaannya untuk berekspansi, kapitalisme secara sistematis melahirkan teknologi-teknologi penghasil limbah dalam jumlah besar. Karena teknologi bertujuan memuaskan pertumbuhan, kapitalisme cenderung lebih memilih teknologi-teknologi yang memaksimalkan asupan sumber daya dan energi secara keseluruhan demi memuaskan hasrat kepentingan ekonomi secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan oleh Donella Meadows dan rekan-rekan penulisnya dalam The Limits of Growth: 30 Year Update: “jika tujuan tersirat sebuah masyarakat adalah mengeksploitasi alam, memperkaya elite, dan mengabaikan jangka panjang, maka masyarakat itu akan mengembangkan teknologi dan pasar yang merusak lingkungan, memperlebar kesenjangan kaya-miskin, mengoptimalkan perolehan jangka pendek. Singkatnya masyarakat itu mengembangkan teknologi dan pasar yang mempercepat keruntuhan alih-alih mencegahnya”.
Industrialisasi adalah salah satu contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia saat ini, dimana industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri sebagai sektor utamanya. Dimana industri dan alat-alat produksinya dikendalikan oleh pemilik modal dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar, pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha sekuat mungkin untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Industri yang menjadi sektor utama dalam industrialisasi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dimana hal ini membuat berkurangnya lahan pertanian yang subur karena pembangunan industri membutuhkan lahan yang begitu luas, bukan hanya itu industri dapat menimbulkan pencemaran, terutama pencemaran udara, air, tanah, dan pencemaran suara. Begitu pula limbah yang dihasilkan dari industri yang tidak melalui proses pengolahan dapat berdampak kepada kesehatan masyarakat yang tinggal disekitar daerah tersebut.
Proses modernisasi yang tidak dapat menghindar dari proses akumulasi kapital oleh sekelompok kecil golongan ini kemudian membawa konsekuensi lebih lanjut pada terjadinya dominasi dan eskploitasi sumberdaya secara luar biasa. Ketika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, yang akan terjadi adalah kesenjangan yang semakin melebar serta degradasi lingkungan yang semakin mendekati titik nadir. Hal ini tentu menjadi ancaman tidak hanya bagi sebuah bangsa tetapi juga seluruh masyarakat manusia. Tidak hanya generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang.
Modernitas, industrialisasi, dan kapitalisasi merupakan tiga hal yang berjalan satu tarikan nafas. Betapa tidak, proses modernisasi senantiasa mensyaratkan adanya industrialisasi sebagai motor penggerak utama. Sementara itu untuk mendukung proses industrialisasi, dibutuhkan eksploitasi berbagai sumber daya alam secara masif. Hal inilah yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya kemerosotan lingkungan hidup Selanjutnya untuk melakukan industrialisasi dibutuhkan kecukupan modal sehingga pintu investasi perlu dibuka lebar. Ketika investasi telah dibuka lebar, tidak dapat dihindari bahwa ruang tersebut akan didominasi oleh para pemilik modal dibandingkan masyarakat lokal. Pada titik inilah ketimpangan sudah dimulai dan seterusnya akan menjadi sebuah proses dominasi.
Kemerosotan lingkungan hidup, bukanlah hal baru bagi dunia tetapi sudah terjadi sepanjang catatan sejarah, dengan akibat-akibat negatif yang mendalam bagi sejumlah peradaban kuno. Yang membuat era modern lebih menonjol dalam hal ini adalah bahwa kini penghuni lebih banyak. Kita memiliki banyak teknologi yang sanggup menciptakan kerusakan lebih besar dan lebih cepat dan kita memiliki sistem ekonomi yang tak kenal batas.
Lebih dari yang sudah-sudah, kian banyak orang meyakini kemerosotan sistem daya-dukung kehidupan di bumi tengah menuntun kita kearah bencana. Bagi semua orang yang peduli akan nasib bumi, telah tiba waktunya untuk menghadapi kenyataan: bukan sekadar kenyataan mengerikan dari perubahan iklim dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup lainnya, tetapi kenyataan adanya kebutuhan mendesak untuk mengubah hubungan mendasar antara manusia dan bumi. Mengingat daya rusak dari pertumbuhan yang menyebabkan banyak hutan di daerah sedang digunduli
Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Penurunan mutu lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup kian hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan yang disebabkan manusia. Faktor akibat peristiwa alam dapat berupa letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Sedangkan penyebab kerusakan lingkungan akibat manusia umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti kerusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah dan lain-lain.
Berdasarkan data kerusakan lingkungan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sejumlah pencemaran lingkungan yang paling banyak ditangani sepanjang 2019 laporan yang diterima YLBHI, pencemaran lingkungan didominasi akibat proyek pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Rahma Mery mengatakan ada 24 kasus pencemaran lingkungan, diikuti 16 kasus tentang pengurusan sumber daya alam dalam 12 kasus terkait pelanggaran tata ruang (CNN). Selain akibat proyek PLTU, pencemaran juga terjadi akibat aktivitas tambang dan pembakaran hutan. Kondisi ini menurut YLBHI, diperburuk dengan kebijakan perubahan tata ruang yang mengesampingkan keadaan ekologi.
Fenomena ekologi ini menyebabkan perubahan iklim yang berawal dari pemanasan global. Dimana pemanasan global adalah keadaan dimana suhu bumi mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca itu akan memerangkap panas di bumi sehingga terjadi kenaikan suhu. Hal tersebut akhirnya memengaruhi keadaan iklim yang berdampak kepada perubahan pola cuaca.
Di Indonesia, aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, salah satunya adalah Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal ini menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Berdasarkan dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa lingkungan hidup sangat memiliki makna yang begitu luas karena menyangkut keseluruhan interaksi kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, serta manusia dengan manusia yang memiliki dampak langsung pada alam, serta dengan manusia makhluk hidup lain yang ada di alam semesta. Pada konteks interaksi ini manusia memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar karena perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam dan makhluk hidup lain akan sangat menentukan kualitas lingkungan hidup (Keraf 2005:26)
Kenyataannya masih banyak persoalan lingkungan yang cukup serius, polusi atau pencemaran lingkungan hidup menjadi salah satu contoh, dimana pencemaran udara, air dan tanah ini tak lepas dari aktivitas di sektor perindustri. Dampak akibat dari produksi alat-alat pabrik ini dapat menyebabkan sebuah pencemaran lingkungan. Dimana pencemaran lingkungan hidup ini sangat menimbulkan dampak yang begitu serius, dimana polusi yang ditimbulkan atau dihasilkan memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat kembali normal.
Indonesia sebagai Negara yang banyak mengalami berbagai masalah industri seperti lokasi industri yang berada di tengah pemukiman, menggeser lahan pertanian, pencemaran lingkungan, dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan keberadaan industri harus dikaji kembali jangan sampai masalah seperti ini terus berlanjut sehingga menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Melihat banyak sekali kawasan industri yang lokasinya berada di sekitar perkotaan banyak menimbulkan masalah, terutama yang menghasilkan bahan pencemaran dalam bentuk limbah cair dan asap industri. Lokasi pabrik yang berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga masalah yang muncul begitu banyak.
Berdasarkan permasalahan diatas, dapat diketahui bahwa ada dua pokok persoalan yang harus diatasi untuk keluar dari aktivitas ekologi yaitu merubah paradigma sumber daya dan menghilangkan ketimpangan akses atas sumber daya serta ketimpangan manfaat dan resiko atas eksploitasi sumber daya alam. Adapun untuk berupaya merealisasikan hal tersebut dapat dilakukan melalui reformasi kelembagaan yang lebih berpihak ke upaya terwujudnya keadilan. Oleh karena itu pentingnya memelihara institusi-institusi keadilan agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar politik pengelolaan lingkungan. Prinsip-prinsip dasar ilmiah inilah yang nantinya akan berfungsi sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah:
- Prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mendorong upaya untuk sejauh mungkin menghindari berbagai kebijakan yang akan membawa dampak yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme yang dijalankan pada prinsip ini secara spirit sesungguhnya juga mendasarkan pada prinsip utilitarian, bahwa kebijakan yang baik adalah yang mampu mempromosikan kebijakan dan meminimalkan keburukan. Apabila kondisi kerusakan adalah suatu hal yang masih dapat dihindari, hal ini menuntut perhatian moral dari setiap orang untuk dilaksanakan. Berkaitan dengan generasi yang akan datang, jauh lebih mudah untuk menemukan hal-hal apa saja yang menjadi sumber kesengsaraan orang-orang dimasa depan.
- Prinsip inklusifitas dan konektivitas, prinsip ini menekankan pentingnya melihat persoalan lingkungan sebagai sebuah persoalan yang selalu memiliki ketertarikan dengan berbagai persoalan yang lain, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hukum dll. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara eksklusif atau terpisah sama sekali dengan persoalan-persoalan yang lain, yang tidak jarang hal ini melampaui batas-batas administratif kewilayahan.
- Prinsip sustainabilitas. Prinsip ini menegaskan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Aspek inilah yang akan memberikan daya dukung pada keberadaan manusia baik sekarang atau yang akan datang.
- Prinsip keadilan. Prinsip ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara adil, baik dalam distribusi manfaat maupun distribusi risiko pada generasi sekarang atau yang akan datang.
- Prinsip partisipasi. Keterlibatan warga Negara dalam pengelolaan sumber daya menjadi hal yang tidak dapat ditolak di tengah arus besar-besaran demokrasi. Hal ini dilakukan dengan tetap menempatkan Negara sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan sumber daya.
Melalui adopsi prinsip-prinsip dasar tersebut dalam berbagai kebijakan politik pengelolaan lingkungan diharapkan kondisi ke arah perubahan yang lebih ekosentris dan memenuhi aspek keadilan lingkungan dapat terwujud. Dengan demikian, secara perlahan namun pasti, komitmen kearah terwujudnya keadilan intragenerasi dan intergretasi dapat terlaksana.
DAFTAR PUSTAKA
Laily Muthmainnah, Rizal Mustansyir, Sindung Tjahyadi. 2020. Kaptalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan dan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. Mozaik Hummaniora Vol 20(1): 57-69.
Magdoff Fred, Foster JB. 2018. Lingkungan Hidup dan Kapitalisme sebuah pengantar. Serpong: Marjin Kiri
Nurhaidah, M. Insya Musa. 2015. Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan. Jurnal Pesona Dasar Vol. 3 No. 3, April 2015, hal 1-14.
Prasetyo, Eko. 2020. Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerak. Yogyakarta: Insist Press
Siling, Tonga. 2017. Modul Kesehatan Lingkungan Kawasan Industri. Medan.