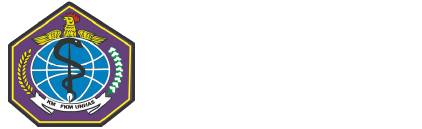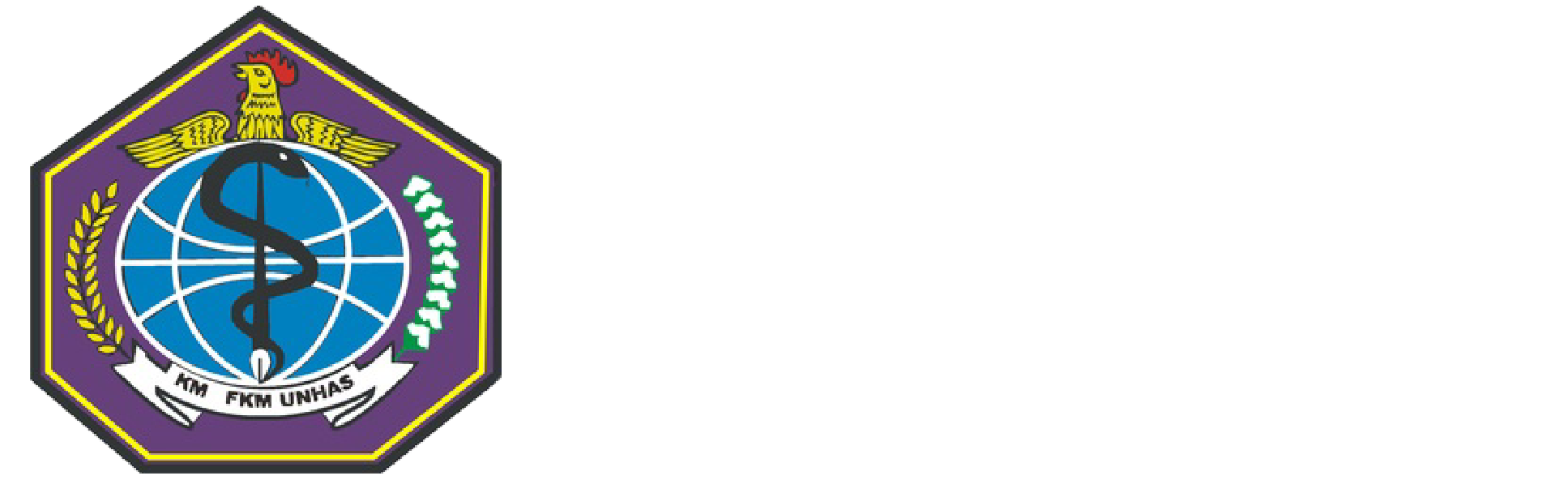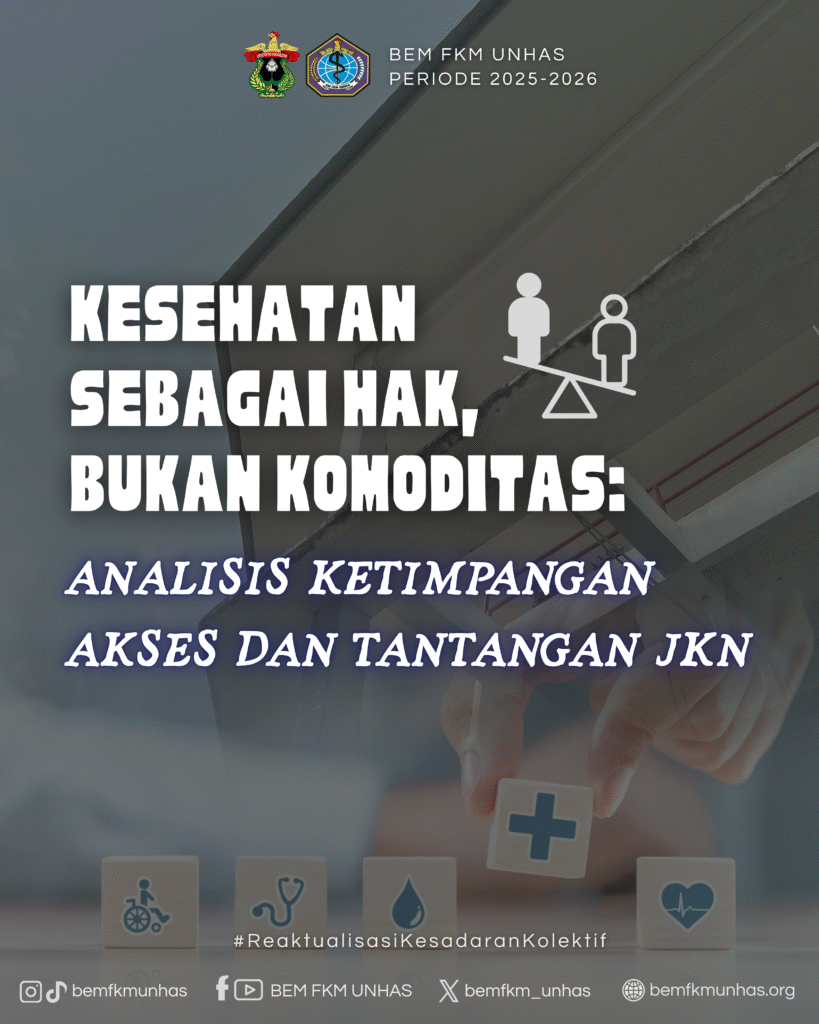
Kesehatan Sebagai Hak, Bukan Komoditas: Analisis Ketimpangan Akses dan Tantangan JKN
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional atas pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak tersebut diperkuat dalam Pasal 34 ayat (3) yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Secara normatif, konstitusi telah menempatkan kesehatan sebagai hak dasar rakyat, bukan barang mewah atau privilese yang hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu. Namun, dalam realitasnya, hak ini masih jauh dari terwujud.
Akses kesehatan bukan hanya soal ketersediaan rumah sakit atau dokter, tetapi juga tentang sejauh mana masyarakat mampu menjangkau layanan secara geografis, ekonomi, maupun sosial. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemudahan akses ke rumah sakit sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan status ekonomi. Hanya 12,5% responden di pedesaan yang melaporkan akses mudah ke rumah sakit, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 53,8% responden di perkotaan. Ketimpangan semakin nyata ketika dilihat dari distribusi tenaga kesehatan. Hingga Agustus 2025, jumlah dokter di Jawa Barat mencapai 30.908 orang, disusul Jawa Timur dengan 26.832 dokter. Sebaliknya, Maluku hanya memiliki 1.164 dokter dan Papua bahkan lebih rendah dengan 985 dokter (SISDKM, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa lokasi sangat menentukan kemudahan akses, di mana masyarakat di wilayah timur Indonesia menjadi kelompok yang paling dirugikan karena fasilitas dan tenaga kesehatan sangat terbatas.
Selain disparitas geografis, faktor ekonomi menjadi penghalang besar dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Penduduk miskin sering kali menunda atau bahkan tidak mencari pertolongan medis karena keterbatasan biaya. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 perbedaan akses terlihat berdasarkan status ekonomi, di mana hanya 17,0% responden dari kelompok ekonomi terbawah yang melaporkan kemudahan akses, sedangkan pada kelompok ekonomi teratas, angka ini mencapai 57,7%. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesetaraan layanan.
Data BPS Maret 2025 mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa (8,47% populasi nasional). Di Sulawesi Selatan, angka kemiskinan mencapai 698.130 jiwa atau 7,60% populasi. Menurut BPS, penduduk miskin adalah individu yang rata-rata pengeluarannya berada di bawah ambang Garis Kemiskinan. Pada Maret 2023, nilai Garis Kemiskinan per kapita ditetapkan sebesar Rp550.458 per bulan, sedangkan untuk tingkat rumah tangga, batas tersebut mencapai Rp2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan.” Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi berimplikasi langsung pada keterlambatan maupun terhambatnya akses layanan kesehatan, sehingga diperlukan intervensi sistemik untuk menjamin masyarakat tetap terlindung.
Sebagai jawaban atas problem akses dan pembiayaan, pemerintah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Secara konsep, JKN digagas sebagai sistem berbasis gotong royong: yang sehat menolong yang sakit, yang mampu menanggung yang tidak mampu, dan negara menjamin tidak ada yang tertinggal. Peserta JKN terbagi dalam beberapa skema: Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah, Pekerja Penerima Upah (PPU) yang iurannya ditanggung pemberi kerja dan pekerja, serta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang membayar secara mandiri. Dengan kerangka tersebut, JKN diharapkan mampu memastikan semua warga negara, tanpa kecuali, dapat mengakses layanan kesehatan.
Namun, pelaksanaan JKN menunjukkan bahwa sistem ini belum benar-benar menjawab masalah struktural. Pada Januari 2025, jumlah peserta nonaktif di Kota Makassar tercatat 317 ribu jiwa (20,6% dari total peserta di kota tersebut). Secara nasional, peserta nonaktif mencapai 56,87 juta jiwa atau 20,42% dari total peserta JKN. Angka ini meningkat dibandingkan laporan Desember 2024 yang mencatat 55,43 juta jiwa (19,9%). Dari jumlah tersebut, sekitar 14,98 juta peserta nonaktif akibat tunggakan iuran, dengan segmen PBPU (peserta mandiri) menyumbang angka terbesar yaitu 14,79 juta jiwa. Sisanya, 40,45 juta peserta dinonaktifkan akibat mutasi data, baik karena validasi ulang pada segmen PBI, penghentian subsidi daerah, atau dampak pemutusan hubungan kerja pada segmen PPU. Data ini memperlihatkan bahwa puluhan juta warga kehilangan hak jaminan kesehatannya bukan karena mereka menolak program, melainkan karena sistem yang gagal merespons dinamika sosial-ekonomi masyarakat secara adaptif.
Selain persoalan kepesertaan, masalah keuangan JKN juga tidak kalah pelik. Data BPJS Kesehatan per Juni 2024 menunjukkan bahwa rasio klaim terhadap iuran mencapai 105,9%, artinya klaim yang harus dibayarkan lebih besar daripada iuran yang terkumpul. Ketidakseimbangan ini menimbulkan potensi defisit struktural yang membahayakan keberlanjutan program. Alih-alih menjamin layanan yang merata, JKN justru membuka ruang bagi diskriminasi pelayanan peserta BPJS kerap dipandang sebagai “pasien kelas dua” di beberapa fasilitas kesehatan. Dengan kata lain, sistem yang dirancang untuk mengatasi ketidakadilan justru melahirkan bentuk ketidakadilan baru.
Privatisasi layanan kesehatan mempertegas kondisi ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari sekitar 2.813 rumah sakit di Indonesia, 63,5% (1.787 unit) dikelola oleh sektor swasta. Dominasi swasta dalam penyediaan layanan kesehatan menggeser peran negara dan memperkuat orientasi profit dalam ekosistem kesehatan. Rumah sakit swasta yang bermitra dengan BPJS sekalipun seringkali menempatkan efisiensi keuangan di atas prinsip pelayanan. Biaya rawat inap, harga obat, hingga layanan penunjang medis kerap membebani keluarga miskin, bahkan mereka yang sudah tercatat sebagai peserta JKN.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan di Indonesia perlahan digiring menjadi komoditas. Logika neoliberal menempatkan layanan medis bukan sebagai hak rakyat yang wajib dijamin negara, melainkan sebagai barang dagangan yang hanya bisa diakses jika memiliki kemampuan finansial. Inilah wajah nyata neoliberalisme kesehatan: pelayanan publik yang seharusnya universal dan non-diskriminatif berubah menjadi ruang transaksi yang sarat kepentingan kapital.
Dengan melihat berbagai kenyataan tersebut, jelas bahwa JKN bukanlah solusi final untuk menjawab problem ketidakadilan akses kesehatan. Program ini lebih dekat pada solusi semu sekilas tampak menjawab persoalan, namun pada praktiknya tetap menyisakan celah ketidaksetaraan. Hak kesehatan rakyat seolah dijamin, tetapi di saat yang sama negara justru melimpahkan beban ke pundak masyarakat melalui skema iuran dan mekanisme pasar.
BEM FKM Unhas menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan yang menghalangi rakyat dalam memperoleh hak kesehatannya. Penolakan ini bukan hanya terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi juga terhadap realitas sosial di mana akses layanan masih tidak merata, biaya kesehatan kian memberatkan, dan fasilitas belum sepenuhnya inklusif bagi kelompok rentan. Bagi kami, kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh dikomodifikasi, melainkan harus dijamin negara dan diakses setara oleh seluruh warga. Sebagai lembaga kemahasiswaan KM FKM Unhas, BEM FKM Unhas mengemban tanggung jawab untuk melahirkan kader-kader transformatif yang cerdas secara intelektual, kritis membaca realitas, peka terhadap ketidakadilan, dan berani menyuarakan kebenaran. Kader yang dimaksud bukan sekadar penguasa wacana, melainkan penggerak yang mampu mengorganisir potensi mahasiswa secara kolektif, melahirkan gagasan progresif, dan mengartikulasikannya dalam gerakan nyata demi memastikan kesehatan benar-benar hadir sebagai hak rakyat, bukan privilese segelintir orang. Dengan itu, BEM FKM Unhas menegaskan bahwa perjuangan atas hak kesehatan bukanlah formalitas, melainkan bagian dari perlawanan dan emansipasi menuju akses kesehatan yang setara bagi semua.
REFERENSI:
Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025. Jakarta: BPS.
Kementerian Kesehatan RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes.
Luz, C. (2025). Neoliberalism and Health Reform. Jakarta: Indepth Press.
Megatsari, H., et al. (2019). Akses layanan kesehatan di Indonesia: Sebuah kajian ketimpangan. Jurnal Kesehatan Masyarakat.
Riskesdas. (2018). Riset Kesehatan Dasar Nasional. Jakarta: Kemenkes RI.
SISDKM. (2025). Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan Manusia. Jakarta: Kemenkes.