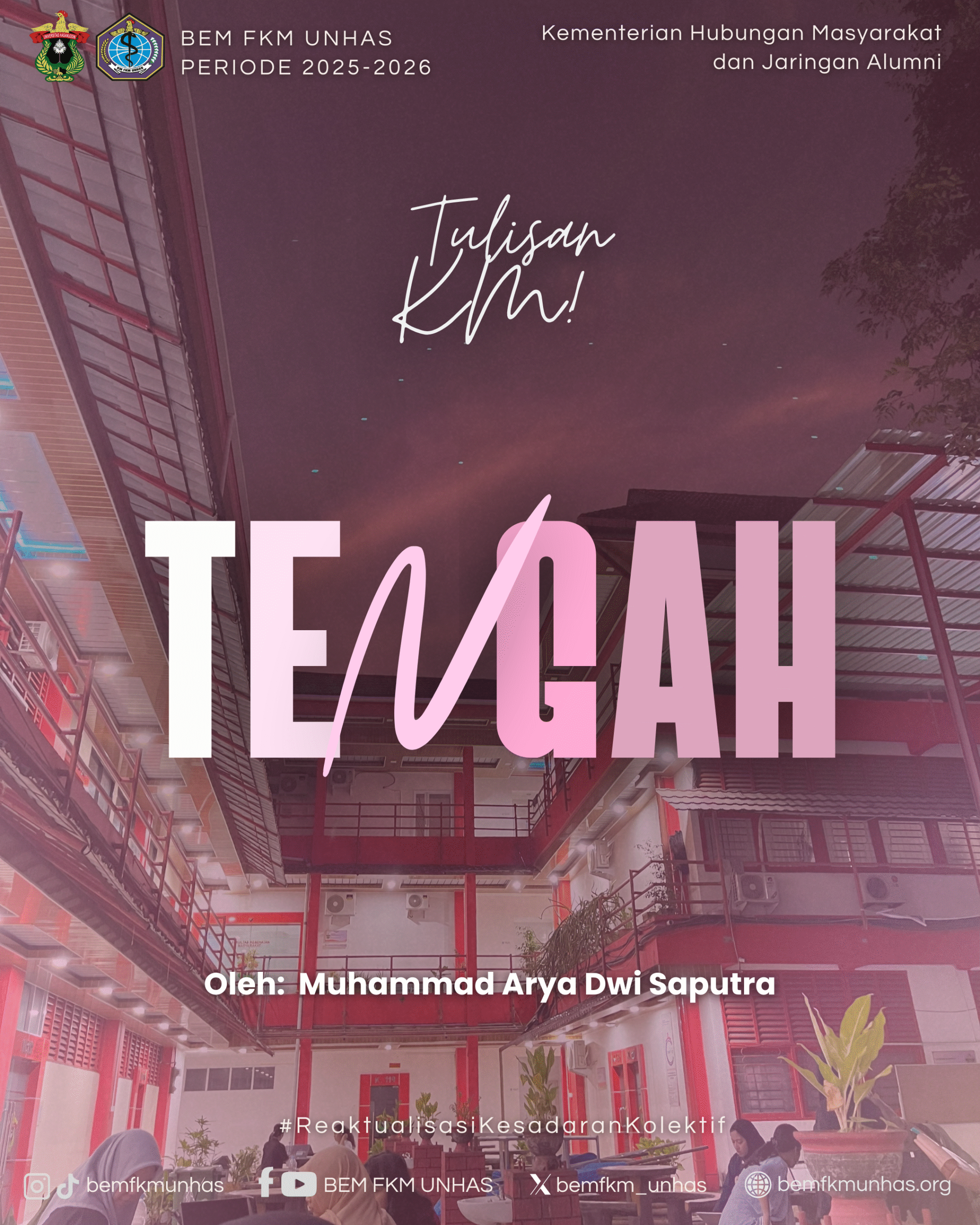Luka November: Kritik atas Gagalnya Kebijakan dan Hilangnya Nurani Negara
Polemik Sistem Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi (MBG) yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi untuk menekan angka stunting justru kembali menuai sorotan tajam pada November 2025. Masalah utamanya bukan sekadar di pelaksanaan, tapi di fondasi kebijakannya mulai dari tata kelola yang amburadul hingga penempatan tenaga profesional yang tidak jelas. Birokrasi program ini kerap menutup mata terhadap pentingnya kompetensi teknis dalam pelayanan gizi masyarakat.
Kritik semakin banyak diberikan ketika Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan, menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami “kelangkaan” sarjana gizi, sehingga tenaga gizi di dapur umum bisa digantikan oleh lulusan bidang lain seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, atau pengolahan makanan. Pernyataan ini dianggap tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang kepala lembaga yang seharusnya memahami esensi profesi gizi. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 justru menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 34.553 ahli gizi aktif, sementara Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia (AIPGI) mencatat ada 133 program studi S1 Gizi yang masih produktif melahirkan ribuan lulusan baru setiap tahun. Dengan angka sebesar itu, menyebut Indonesia “kekurangan” ahli gizi jelas menyesatkan publik.
Lebih ironis lagi, pandangan bahwa sarjana bidang lain bisa menggantikan peran ahli gizi memperlihatkan betapa lemahnya penghargaan negara terhadap profesionalisme keilmuan. Seorang ahli gizi tidak hanya belajar teori, tetapi memahami secara detail kebutuhan energi per jenjang usia, perhitungan nilai gizi per menu, serta integrasi nutrisi dalam teknik memasak, hal-hal yang tidak bisa disubstitusi oleh lulusan bidang lain yang hanya menguasai aspek teoritis. Ketika seorang pejabat publik menganggap semua ilmu gizi bisa “diwakilkan” oleh rumpun lain, itu menunjukkan cara pandang yang simplistik terhadap rumpun ilmu lain. Pernyataan tersebut justru memperlihatkan disorientasi kebijakan: negara tampak tidak memahami esensi masalah gizi, tapi tetap ingin mengelolanya secara seremonial.
Isu ini memperlihatkan kelemahan struktural dalam perencanaan SDM kesehatan. Alih-alih memperkuat sistem distribusi tenaga ahli melalui mekanisme nasional seperti Nusantara Sehat, pemerintah justru memilih jalan pintas mengisi kekosongan dengan tenaga yang tidak kompeten. Padahal, program MBG semestinya menjadi tonggak perbaikan gizi berbasis keilmuan, bukan ajang percobaan kebijakan populis. Tanpa kesadaran terhadap nilai profesionalisme dan validitas ilmu gizi, program ini berisiko menjadi proyek simbolik yang gagal menjawab akar persoalan stunting dan ketimpangan layanan kesehatan.
Penobatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Polemik penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional memunculkan gelombang kritik tajam dari publik dan kalangan akademik. Banyak pihak menilai langkah ini mencederai memori kolektif bangsa terhadap masa kelam Orde Baru. Dalam wacana publik, Soeharto dikenal bukan hanya sebagai simbol stabilitas, tetapi juga sebagai figur yang mewariskan sistem kekuasaan otoriter sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada masa pemerintahannya, korupsi bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem politik dan ekonomi yang tertutup tanpa pengawasan publik. Akibatnya, kesenjangan sosial makin lebar, pembangunan ekonomi hanya terkonsentrasi di Jawa, sementara daerah lain dibiarkan tertinggal. Program transmigrasi yang digadang sebagai pemerataan, justru memicu konflik horizontal di banyak wilayah. Krisis moneter 1998 menjadi puncak kegagalan sistem tersebut, memperlihatkan rapuhnya ekonomi yang dibangun di atas praktik nepotisme dan rantai kekuasaan.
Lebih jauh, masa pemerintahan Soeharto juga diwarnai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM). Dari pembantaian massal 1965 yang menewaskan hingga 1,5 juta orang, operasi militer di Aceh dan Timor Timur, penembakan misterius (Petrus) pada 1980-an, hingga tragedi Tanjung Priok dan kerusuhan Mei 1998, semuanya menunjukkan pola kekerasan negara yang sistematis. Kasus Marsinah, tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, serta penculikan aktivis 1998 menjadi simbol betapa negara menggunakan kekerasan untuk membungkam kritik. Luka-luka sejarah ini belum sembuh, banyak keluarga korban masih menuntut keadilan dan pengakuan
Menimbang catatan kelam tersebut,penobatan Soeharto dinilai memperlemah pesan moral negara terhadap upaya penegakan HAM dan mempertegas paradoks dalam politik memori Indonesia.Hal ini seperti menghapus penderitaan jutaan korban dan mengaburkan pelajaran penting dari sejarah bangsa: bahwa kekuasaan tanpa kontrol melahirkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan struktural. Penghargaan semacam ini, alih-alih memperkuat identitas nasional, justru membuka luka lama yang belum pernah benar-benar disembuhkan. Lebih jauh, keputusan untuk memberi gelar pahlawan kepada Soeharto dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap para korban dan nilai-nilai demokrasi, serta pengkhianatan terhadap reformasi itu sendiri. Tindakan ini juga merupakan bentuk pengaburan sejarah yang berbahaya bagi generasi muda, karena berpotensi menormalkan kekuasaan otoriter dan menghapus jejak penderitaan rakyat. Gelar pahlawan seharusnya diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat bukan kepada pemimpin yang masa jabatannya diwarnai oleh represi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyatnya.
Undang-Undang KUHAP: Darurat Hukum dan Privasi Warga
Pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh DPR RI pada 18 November 2025 menandai salah satu titik balik sekaligus kemunduran dalam arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Alih-alih menghadirkan perbaikan mendasar terhadap problem lama seperti penyalahgunaan wewenang dan lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum, KUHAP baru justru memperkuat sentralisasi kekuasaan di tangan kepolisian. Hal ini mengkhawatirkan karena berlangsung di tengah sistem hukum yang masih lemah dalam mekanisme pengawasan yudisial dan partisipasi publik.
Secara substansi, pasal-pasal dalam KUHAP baru memberikan kewenangan yang sangat luas kepada aparat penyidik. Pasal 44 memperbolehkan penyitaan benda bergerak tanpa izin pengadilan dengan alasan “keadaan mendesak”, di mana kondisi “mendesak” itu sendiri ditentukan secara subjektif oleh penyidik. Begitu pula Pasal 136 ayat (2) yang mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan “untuk kepentingan penyidikan” tanpa batasan jenis tindak pidana dan tanpa kejelasan mekanisme pengawasan. Ketentuan ini berarti bahwa penyadapan dapat dilakukan terhadap siapa pun, kapan pun, tanpa izin hakim membuka peluang pelanggaran hak privasi warga secara masif.
Lebih jauh, Pasal 140 ayat (2) mengizinkan pemblokiran rekening, data daring, atau media sosial tanpa izin pengadilan atas dasar “situasi berdasarkan penilaian penyidik.” Hal ini menjadi celah besar yang bisa digunakan untuk menjustifikasi tindakan sewenang-wenang, mengingat tidak adanya ukuran objektif mengenai “situasi” tersebut. Sementara dalam konteks hukum modern yang menjunjung tinggi due process of law, tindakan perampasan hak sipil semestinya hanya bisa dilakukan melalui mekanisme peradilan yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Pasal 93, 99, dan 100 tentang penangkapan dan penahanan menunjukkan penurunan standar perlindungan hak tersangka. Penahanan dapat dilakukan atas dasar alasan subjektif seperti “tidak kooperatif” atau “memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta,” padahal kedua alasan itu sangat bergantung pada penilaian pribadi penyidik. Kondisi ini membuka ruang kriminalisasi warga, seseorang bisa saja ditahan hanya karena gugup, diam, atau tidak mampu menjawab pertanyaan dengan lancar.
Kekhawatiran tersebut semakin beralasan karena KUHAP baru tetap mempertahankan pola lama yang minim judicial scrutiny. Seperti ditekankan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, rancangan ini tidak mengubah konsep dasar bahwa penangkapan, penahanan, dan tindakan paksa lainnya dapat dilakukan tanpa persetujuan hakim pada tahap awal. Dalam praktik, mekanisme “izin pengadilan” pasca tindakan sering kali hanya bersifat administratif sekadar formalitas surat menyurat tanpa pemeriksaan substantif. Artinya, kekuasaan merampas kemerdekaan seseorang masih berada di tangan aparat eksekutif, bukan lembaga yudisial, sebuah anomali serius dalam sistem demokrasi hukum.
Persoalan tidak berhenti di sana. Pasal 6, Pasal 7 ayat (3)–(5), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) menetapkan Polri sebagai penyidik utama di seluruh perkara pidana, menempatkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik khusus di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian. Langkah ini berpotensi menggerus independensi lembaga penyidik lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Perikanan, dan sebagainya, karena semua proses berkas perkara harus melalui penyidik Polri. Dengan demikian, KUHAP baru secara tidak langsung menciptakan “superioritas kelembagaan” kepolisian menjadikan Polri bukan sekadar pelaksana hukum, melainkan pengendali arah pembuktian perkara di semua lini.
Ketentuan lain seperti Pasal 16 yang memuat mekanisme undercover buy dan control delivery juga menimbulkan persoalan baru. Meskipun dijelaskan bahwa praktik ini hanya berlaku untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, rumusan pasal tetap kabur dan inkonsisten dengan Undang-Undang Narkotika. Ketidakjelasan batas antara tahap penyelidikan dan penyidikan membuat warga bisa menjadi target tindakan “khusus” bahkan sebelum status tersangka ditetapkan sebuah bentuk kriminalisasi dini yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
Kritik publik terhadap RUU ini sempat ditanggapi secara kontraproduktif oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menuduh informasi seputar pasal-pasal bermasalah sebagai hoaks. Meski kemudian ia mengoreksi ucapannya, sikap defensif tersebut mencerminkan resistensi politik terhadap partisipasi publik yang kritis. Padahal, seperti dijelaskan Koalisi, keempat isu utama yang dikritik penyadapan tanpa batas, pemblokiran tanpa izin pengadilan, penyitaan subjektif, dan penangkapan tanpa kontrol yudisial merupakan hasil pembacaan faktual terhadap naskah RUU, bukan disinformasi.
Bahkan dalam siaran persnya, Koalisi menegaskan bahwa RUU KUHAP 2025 gagal melakukan pembaruan fundamental setelah 44 tahun revisi. Alih-alih menguatkan posisi pengadilan sebagai penjaga keadilan, ia justru melanggengkan praktik-praktik otoritarian yang membiarkan aparat eksekutif bertindak tanpa pengawasan efektif. Koalisi juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto menunda pemberlakuan KUHAP baru setidaknya satu tahun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), demi memberi waktu bagi revisi substansi, sosialisasi, dan pelatihan aparat agar tidak terjadi kekacauan hukum di lapangan.
KUHAP baru ini menegaskan pergeseran paradigma dari hukum yang seharusnya melindungi warga negara, menjadi hukum yang memprioritaskan stabilitas dan kontrol kekuasaan. Bila dibiarkan, ini berpotensi melahirkan sistem hukum represif bergaya baru: otoritarianisme berbaju legalitas. Dalam konteks demokrasi pasca-reformasi, hal ini bukan sekadar kegagalan teknokratik, melainkan kemunduran moral dan konstitusional yang serius.
Kasus Irene Sokoy: Kegagalan Sistem Kesehatan dan Ketimpangan di Timur Indonesia
Kasus tragis Irene Sokoy, seorang ibu muda asal Jayapura yang meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Papua, mengguncang nurani publik dan menjadi potret paling nyata kegagalan negara dalam menjamin hak dasar atas kesehatan. Irene bersama keluarganya berkeliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain mulai dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara namun tidak satu pun yang memberinya pelayanan medis memadai. Alasan yang disampaikan pihak rumah sakit pun seragam: tidak ada dokter spesialis kandungan, ruang rawat penuh, dan kendala administratif BPJS. Setelah berjam-jam mencari pertolongan di tengah malam, Irene akhirnya meninggal dunia, bersama bayi yang seharusnya ia lahirkan dengan selamat.
Peristiwa ini mengungkap disfungsi mendalam dalam sistem pelayanan kesehatan di Papua mulai dari buruknya koordinasi antar fasilitas kesehatan, lemahnya sistem rujukan, hingga ketimpangan distribusi tenaga medis. Kematian Irene bukan sekadar akibat kelalaian individu, melainkan refleksi dari struktur kebijakan yang gagal menjangkau masyarakat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Rasio dokter di wilayah Papua hanya 0,13 per 1.000 penduduk, jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk. Lebih dari 60 persen rumah sakit di Papua tidak memiliki dokter spesialis tetap, dan sebagian besar tenaga medis yang bertugas di wilayah ini merupakan kontrak jangka pendek yang sering kali tidak diperpanjang karena alasan anggaran maupun keamanan.
Kronologi dan dampak sosial dari kematian Irene memperlihatkan kesenjangan struktural antara narasi pembangunan kesehatan nasional dengan realitas di lapangan. Pemerintah pusat memang terus menggaungkan program pemerataan melalui Nusantara Sehat, namun implementasinya terbukti tidak menjawab akar masalah. Banyak tenaga kesehatan mengeluhkan fasilitas yang tidak layak, keterbatasan peralatan medis, serta beban kerja yang tidak sebanding dengan dukungan operasional. Ketika akses kesehatan bergantung pada kesiapan individu dan keberuntungan geografis, maka hak hidup masyarakat menjadi taruhan politik dan kebijakan.
Lebih jauh, tragedi Irene Sokoy juga harus dibaca dalam konteks ketimpangan historis pembangunan di wilayah timur Indonesia. Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Papua mencapai 565 per 100.000 kelahiran hidup, sementara di Papua Barat sebesar 343 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi (AKB) di Papua tercatat 35 per 1.000 kelahiran hidup, dan Papua Barat 27 per 1.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup. Tingginya angka ini berkaitan erat dengan minimnya layanan neonatal, keterbatasan tenaga medis, serta sulitnya akses transportasi bagi ibu hamil dan bayi di daerah terpencil. Dalam kondisi seperti ini, kematian Irene bukanlah kejadian yang baru, melainkan puncak dari krisis kesehatan struktural yang sudah lama diabaikan.
Tragedi ini seharusnya menjadi alarm moral dan politik bagi pemerintah. Alih-alih berfokus pada proyek-proyek populis seperti “Makan Bergizi” atau digitalisasi layanan kesehatan, negara semestinya memprioritaskan pemerataan infrastruktur kesehatan dan jaminan tenaga medis yang kompeten di daerah 3T. Irene Sokoy meninggal bukan karena takdir, melainkan karena kegagalan sistemik yang menempatkan hak hidup perempuan Papua di urutan terakhir prioritas pembangunan nasional. Kasus ini menjadi cermin suram kebijakan kesehatan Indonesia, bahwa di tengah klaim kemajuan dan digitalisasi, masih ada warga negara yang harus kehilangan nyawa hanya karena sistem yang abai dan negara yang tidak hadir saat dibutuhkan.
Rentetan persoalan yang terjadi sepanjang bulan November 2025 memperlihatkan bahwa arah kebijakan publik Indonesia sedang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, publik dihadapkan pada beragam krisis moral dan struktural: mulai dari tata kelola Program Makan Bergizi (MBG), keputusan kontroversial pemerintah yang menobatkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, hingga pengesahan RUU KUHAP yang memperkuat dominasi aparat dan melemahkan kontrol peradilan. Belum reda gelombang kritik terhadap tiga isu tersebut, muncul pula tragedi kemanusiaan di Papua melalui kasus Irene Sokoy, yang menyingkap wajah getir sistem kesehatan di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan hal tersebut BEM FKM Unhas menyatakan sikap :
- Pemerintah harus menghentikan praktik substitusi profesi yang merendahkan kompetensi ahli gizi dan segera menata ulang tata kelola program secara transparan dan profesional. Kami menuntut agar kebijakan gizi nasional dikembalikan pada landasan keilmuan, memperkuat distribusi tenaga ahli melalui sistem rekrutmen berbasis kompetensi, serta menghapus praktik birokratis yang menyingkirkan peran akademisi gizi.
- Kami menolak penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, mendesak pemerintah melakukan kajian ulang karena bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran sejarah. Mendesak pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang belum mendapatkan keadilan.
- Kami memandang pengesahan Undang-Undang KUHAP 2025 sebagai ancaman serius terhadap prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang KUHAP ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang aparat, melemahkan peran yudikatif, dan mengikis jaminan hak privasi warga. Kami menuntut untuk menunda penerapannya melalui penerbitan Perppu dan memerintahkan revisi substantif dengan melibatkan masyarakat sipil dan pakar hukum independen.
Kami menyatakan duka atas kematian Irene Sokoy sebagai simbol kegagalan negara memenuhi hak dasar atas kesehatan. Pemerintah harus bertanggung jawab atas buruknya tata kelola sistem kesehatan di Papua dan wilayah 3T lainnya. Kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi tenaga medis, peningkatan fasilitas rumah sakit daerah, serta jaminan layanan kesehatan yang setara bagi semua warga negara tanpa diskriminasi geografis