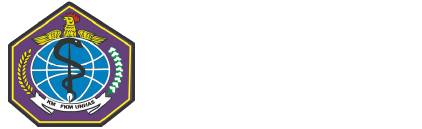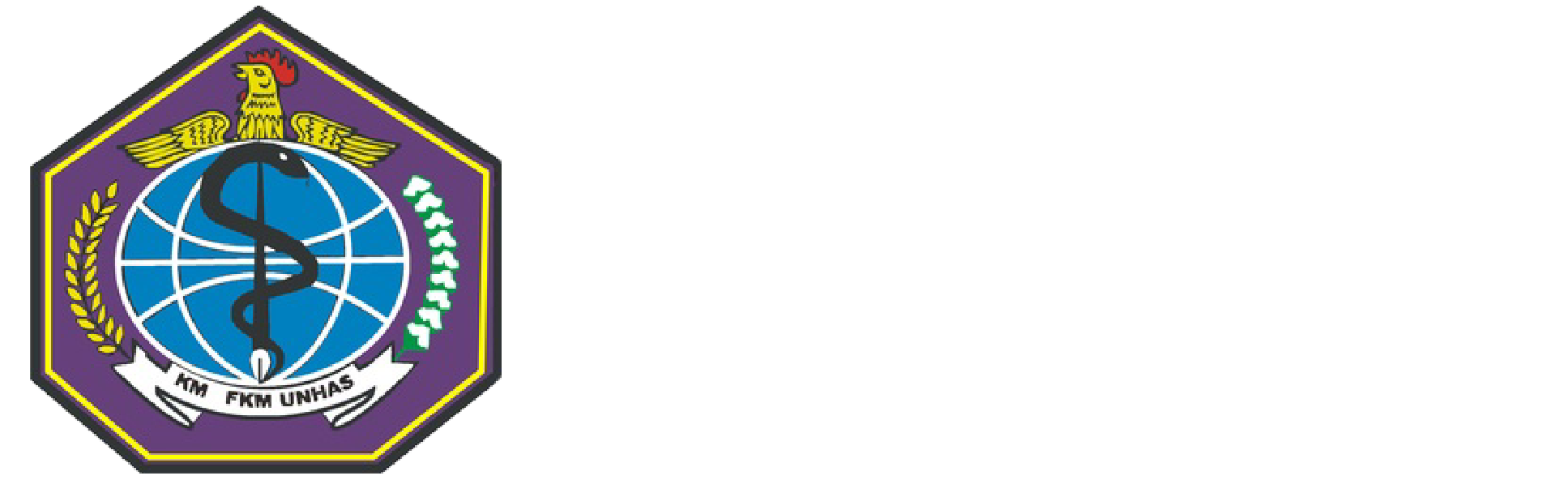Press Release: Membakar Demokrasi Semu: Perlawanan Mahasiswa terhadap Otoritarianisme Kampus
[Makassar, 13 Januari 2025] – Dalam diskusi terbuka bertajuk “Membakar Demokrasi Semu: Perlawanan Mahasiswa terhadap Otoritarianisme Kampus,” beberapa stakeholder dari berbagai fakultas di UNHAS membahas fenomena otoritarianisme yang mengekang kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Fenomena ini menjadi refleksi mendalam terhadap demokrasi kampus yang sering kali hanya menjadi formalitas tanpa substansi nyata.
Dalam beberapa hari terakhir, Universitas Hasanuddin (UNHAS) dihebohkan oleh kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen sebagi pelaku. Kasus ini memicu gelombang perlawanan dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang menuntut keadilan bagi korban. Respons mahasiswa terhadap kasus ini merupakan bentuk solidaritas serta upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas kampus dalam menangani tindak kekerasan seksual. Namun, setiap aksi dan upaya mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan selalu dihadapkan pada keterlibatan aparat kepolisian. Kehadiran mereka yang diklaim untuk menjaga ketertiban justru menjadi sumber ketegangan baru. Pertanyaan besar muncul: siapa yang sebenarnya ingin diamankan? Pelaku, korban, atau suara-suara yang menuntut keadilan?
Dalam peristiwa ini, berbagai organisasi mahasiswa berupaya menggelar aksi demonstrasi serta diskusi publik sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang terjadi. Namun, hampir setiap aksi yang digelar dihadapkan pada pengamanan ketat, bahkan tak jarang aparat kepolisian turut serta dalam memantau dan membubarkan kegiatan yang seharusnya menjadi hak dasar mahasiswa sebagai bagian dari kebebasan akademik. Alih-alih memberikan perlindungan terhadap korban dan mendukung upaya mahasiswa dalam menuntut keadilan, keberadaan aparat justru lebih sering dikaitkan dengan praktik intimidasi. Mahasiswa yang menyuarakan aspirasi mereka merasa diawasi, dicatat, bahkan beberapa mengalami tindakan represif secara langsung.
Selain itu, keterlibatan aparat dalam menangkap jurnalis pers mahasiswa juga menjadi sorotan tajam. Dalam beberapa hari terakhir, seorang jurnalis dari pers mahasiswa dituduh sebagai pelaku pengrusakan dalam rangkaian kejadian yang mengguncang UNHAS. Langkah yang diambil pihak kampus terkesan terburu-buru dan tidak transparan, seolah-olah mencari jalan pintas dengan membungkam suara kritis mahasiswa. Pers mahasiswa, yang seharusnya berperan sebagai pilar kebebasan informasi dan media independen di lingkungan akademik, justru menjadi korban represi. Tidak hanya mengalami penangkapan yang sewenang-wenang, mereka juga menghadapi intimidasi berulang dari pihak berwenang yang bekerja sama dengan kepolisian dalam mengintervensi narasi yang berkembang. Ini menandakan adanya upaya sistematis untuk mengontrol informasi yang beredar di dalam kampus, membungkam kritik, dan menghalangi transparansi terhadap berbagai isu penting.
Keterlibatan aparat kepolisian yang diklaim untuk menjaga keamanan semakin dipandang sebagai bentuk kontrol terhadap kebebasan berekspresi. Ruang gerak mahasiswa untuk menyampaikan pandangan kritis semakin terbatas akibat pengawasan yang berlebihan. Hal ini berdampak pada menurunnya partisipasi mahasiswa dalam berbagai gerakan sosial, karena ketakutan akan adanya tindakan represif yang bisa berdampak pada akademik maupun kehidupan pribadi mereka. Dengan adanya pengawasan ketat dari aparat, banyak kegiatan mahasiswa tidak dapat berjalan secara optimal. Aksi demonstrasi, diskusi terbuka, bahkan kegiatan akademik yang membahas isu-isu sensitif sering kali mendapat intervensi, baik secara langsung maupun melalui regulasi kampus yang semakin membatasi ruang demokrasi.
Dengan kondisi seperti ini, kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan menyuarakan kebenaran justru berubah menjadi ruang yang penuh tekanan dan pengawasan. Demokrasi kampus yang idealnya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta menyampaikan pendapat, kini semakin kehilangan substansinya. Keterlibatan aparat kepolisian dalam setiap gerakan mahasiswa harus dipertanyakan, terutama ketika kehadiran mereka lebih sering digunakan untuk membatasi ekspresi mahasiswa daripada melindungi hak-hak mereka. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam mencetak generasi intelektual yang kritis dan berani memperjuangkan kebenaran, justru akan menjadi sarang ketakutan dan kepatuhan buta terhadap otoritas.
Mahasiswa sebagai bagian dari intelektual muda memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan akademik dan demokrasi kampus. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi hari ini bukan hanya berasal dari tekanan eksternal, tetapi juga dari internal gerakan mahasiswa itu sendiri. Fragmentasi gerakan menjadi salah satu masalah mendasar yang menghambat efektivitas perjuangan mahasiswa dalam menuntut kebijakan yang lebih adil.
Saat ini, banyak gerakan mahasiswa yang bergerak di ranahnya masing-masing tanpa membangun sinergi dengan kelompok lain. Misalnya, kelompok yang berfokus pada isu lingkungan sering kali tidak berkolaborasi dengan kelompok yang bergerak dalam isu sosial atau demokrasi kampus. Padahal, setiap isu memiliki keterkaitan yang erat dan bisa diperjuangkan secara lebih efektif dengan gerakan yang solid dan inklusif. Tanpa adanya koordinasi yang baik, gerakan mahasiswa justru cenderung eksklusif dan tidak memiliki daya tekan yang cukup terhadap kebijakan kampus.
Selain itu, gerakan mahasiswa sering kali terjebak dalam ruang diskursif tanpa mengambil langkah konkret dalam penyusunan kebijakan. Diskusi memang penting untuk membangun kesadaran kritis, tetapi tanpa aksi nyata, perubahan tidak akan terjadi. Salah satu pendapat yang hadir terkait kendala utama adalah ketergantungan terhadap struktur formal seperti Majelis Wali Amanat (MWA). Mahasiswa kerap mengandalkan perwakilan mereka di MWA sebagai satu-satunya cara untuk menyuarakan aspirasi. Padahal, realitanya, ruang representasi mahasiswa di MWA sangat terbatas. Hanya ada satu kursi bagi mahasiswa, sementara kebijakan yang dibuat mencakup seluruh aspek kehidupan akademik dan kesejahteraan mahasiswa. Dengan keterbatasan ini, harapan bahwa perjuangan mahasiswa bisa sepenuhnya disalurkan melalui jalur formal adalah sebuah ilusi.
Ketergantungan berlebihan pada struktur formal juga menghambat fleksibilitas gerakan mahasiswa dalam merespons isu-isu yang muncul secara cepat. Kritik terhadap pola gerakan yang terlalu spontan dan tidak organik semakin relevan dalam kondisi ini. Gerakan yang muncul secara tiba-tiba tanpa perencanaan strategis cenderung tidak memiliki dampak jangka panjang. Misalnya, banyak aksi protes yang dilakukan sebagai bentuk respons cepat terhadap suatu kejadian, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut yang konkret untuk memastikan perubahan kebijakan yang diharapkan. Ketidaksiapan dalam menyusun strategi membuat banyak gerakan kehilangan arah dan akhirnya melemah dengan sendirinya.
Pola pikir mahasiswa yang terlalu bergantung pada struktur formal juga menghambat inovasi dalam gerakan mahasiswa. Mahasiswa perlu memahami bahwa gerakan yang efektif tidak harus selalu beroperasi dalam jalur birokrasi kampus. Justru, banyak perubahan besar dalam sejarah gerakan mahasiswa terjadi ketika mahasiswa memilih untuk bertindak secara mandiri, tanpa menunggu persetujuan dari struktur formal yang ada. Jika mahasiswa terus-menerus mengandalkan sistem yang ada tanpa menciptakan alternatif, maka perjuangan mereka akan selalu dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh pihak yang mereka kritisi.
Kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi juga harus menjadi bagian dari refleksi gerakan mahasiswa hari ini. Setiap langkah yang diambil, baik itu aksi demonstrasi, penyusunan kajian kebijakan, atau upaya advokasi lainnya, pasti akan berhadapan dengan tantangan. Namun, justru di sinilah pentingnya keberanian dalam menghadapi risiko. Jika mahasiswa ingin memperjuangkan demokrasi yang lebih sehat di lingkungan kampus, mereka tidak bisa hanya menunggu dan berharap pada mekanisme yang sudah ada. Mereka harus mulai mengambil inisiatif sendiri, membangun gerakan yang lebih sistematis, dan tidak bergantung pada jalur yang telah disediakan oleh otoritas kampus.
Di beberapa kampus, bahkan yang memiliki sistem MWA yang dianggap baik, praktik demokrasi masih sering kali bersifat prosedural tanpa substansi yang nyata. Mahasiswa hanya diberi ruang yang sangat terbatas untuk berpartisipasi, sementara keputusan tetap didominasi oleh kepentingan pihak kampus dan birokrasi. Oleh karena itu, mahasiswa tidak bisa hanya meminta agar demokrasi diberikan kepada mereka—mereka harus merebutnya.
Merebut demokrasi bukan berarti melakukan tindakan anarkis atau destruktif, tetapi membangun gerakan yang berbasis pada strategi jangka panjang. Gerakan mahasiswa harus mampu menciptakan mekanisme kontrol terhadap kebijakan kampus secara independen. Mereka harus berani membangun forum-forum alternatif, menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif, serta melakukan tekanan yang berkelanjutan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada mahasiswa.
Diskusi ini menghasilkan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian bersama. Mahasiswa harus membangun gerakan yang lebih matang dan inklusif. Mereka harus melepaskan ketergantungan pada struktur formal yang sering kali tidak efektif dan memperjuangkan demokrasi kampus melalui berbagai cara yang lebih mandiri. Perjuangan melawan otoritarianisme kampus harus dilakukan secara kolektif, tidak hanya melalui wacana, tetapi juga aksi nyata yang berdampak. Langkah ini bukanlah akhir, melainkan awal dari gerakan mahasiswa yang lebih berdaya guna. Jika mahasiswa ingin menciptakan demokrasi kampus yang lebih substansial, adil, dan inklusif, mereka harus berani mengambil inisiatif, menyusun strategi yang lebih sistematis, dan membangun solidaritas yang lebih kuat. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya—mahasiswa harus memperjuangkannya dengan kesadaran penuh bahwa mereka adalah aktor utama dalam membentuk masa depan kampus yang lebih demokratis.