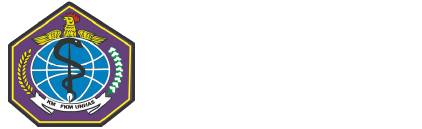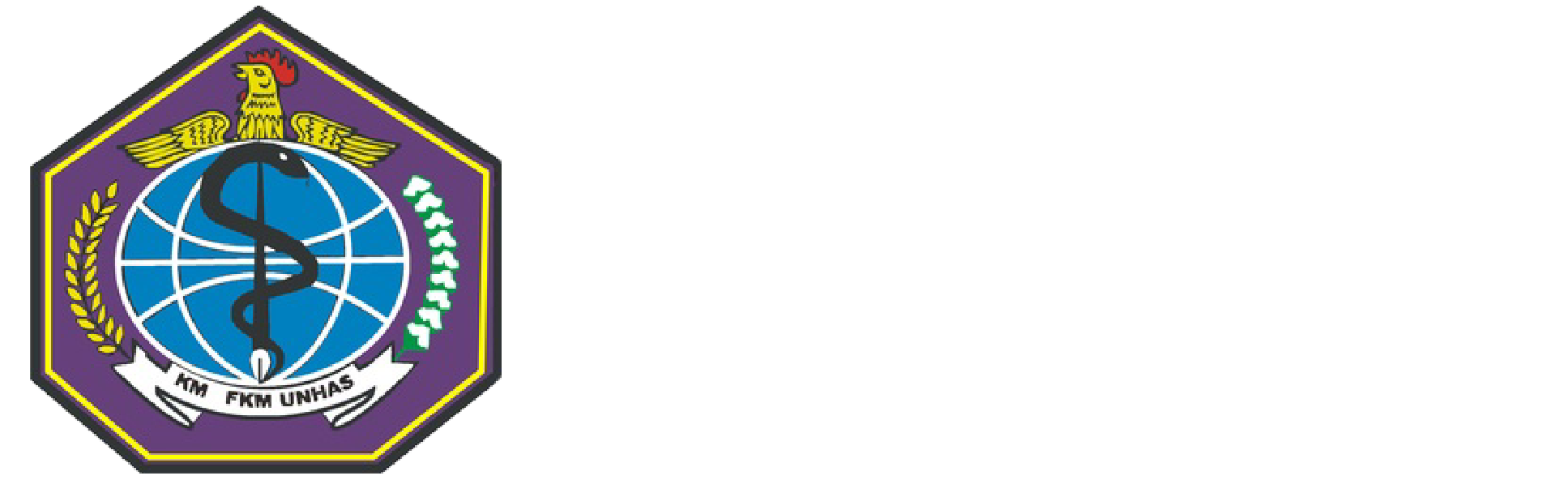Menelusuri Akar Neoliberalisme
Neoliberalisme merupakan salah satu ideologi ekonomi-politik paling berpengaruh dalam sejarah kontemporer. Sejak akhir abad ke-20, ia tidak hanya menjadi model kebijakan ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, tetapi juga merembes ke negara-negara berkembang melalui mekanisme globalisasi, lembaga keuangan internasional, serta tekanan politik. Pemahaman mengenai sejarah dan akar neoliberalisme penting karena ia tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan lahir dari pergulatan panjang antara ide, krisis ekonomi, dan perubahan struktur sosial. Dalam konteks global, neoliberalisme berperan besar dalam membentuk wajah masyarakat modern, baik melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi maupun melalui ketimpangan sosial yang semakin melebar (Harvey, 2005; Kotz, 2015).
Secara definisi, neoliberalisme sering dipahami sebagai sebuah proyek politik yang berupaya mengembalikan kondisi akumulasi modal dan kekuasaan kelas kapitalis melalui mekanisme pasar bebas (Harvey, 2005). Neoliberalisme menekankan liberalisasi perdagangan, privatisasi sektor publik, deregulasi pasar, serta pengurangan intervensi negara dalam kehidupan ekonomi. Menurut Kotz (2015), tiga pilar utama neoliberalisme dapat diringkas dalam trilogi kebijakan: liberalisasi, privatisasi, dan stabilisasi. Karakter ini menjadikan neoliberalisme berbeda dari liberalisme klasik, karena neoliberalisme bukan sekadar membela kebebasan pasar, tetapi juga menginstitusionalisasikannya sebagai doktrin kebijakan publik. Dalam perspektif Arianto Sangaji (2009), neoliberalisme bahkan sering tampil sebagai bentuk “fundamentalisme pasar”, di mana kebebasan individu dan persaingan pasar dijadikan nilai tertinggi, meski sering mengorbankan keadilan sosial.
Akar pemikiran neoliberalisme dapat ditelusuri dari tradisi liberalisme klasik, khususnya gagasan Adam Smith tentang “invisible hand” pasar yang diyakini mampu menciptakan keseimbangan secara alami. David Ricardo kemudian memperkuatnya dengan teori keunggulan komparatif yang mendorong perdagangan bebas. Namun, bentuk neoliberalisme modern lebih banyak dipengaruhi oleh pemikir seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman. Mereka menolak intervensi negara yang terlalu besar, yang dianggap membatasi kebebasan individu dan efisiensi pasar. Pada tahun 1947, Hayek bersama sekelompok intelektual mendirikan Mont Pèlerin Society, yang kemudian menjadi wadah penting penyebaran ide-ide neoliberal ke seluruh dunia (Harvey, 2007). Dari sinilah neoliberalisme memperoleh legitimasi intelektual yang sistematis.
Sejarah perkembangan neoliberalisme erat kaitannya dengan dinamika krisis ekonomi global. Pasca-Perang Dunia II, dunia lebih banyak dipengaruhi oleh Keynesianisme, yang menekankan peran aktif negara dalam menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Namun, model Keynesian mulai goyah pada dekade 1970-an ketika dunia dilanda krisis minyak dan stagflasi. Kegagalan negara dalam mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi membuka ruang bagi kebangkitan neoliberalisme. Pada era Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, neoliberalisme diinstitusionalisasi melalui kebijakan deregulasi, privatisasi BUMN, pemangkasan subsidi, serta pelemahan serikat pekerja (Kotz, 2015). Sejak saat itu, neoliberalisme menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi global.
Di tingkat internasional, lembaga-lembaga Bretton Woods seperti IMF dan Bank Dunia berperan besar dalam menyebarkan neoliberalisme. Melalui paket kebijakan Structural Adjustment Program (SAP) dan Washington Consensus, negara-negara berkembang dipaksa untuk membuka pasar domestik, melakukan privatisasi, dan memangkas belanja sosial sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan finansial. Menurut Sangaji (2009), mekanisme ini menunjukkan bagaimana neoliberalisme tidak hanya hadir sebagai teori ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen dominasi politik dan ekonomi global.
Dampak neoliberalisme bersifat ambivalen. Di satu sisi, kebijakan neoliberal telah mendorong integrasi ekonomi global dan pertumbuhan pasar internasional. Beberapa indikator menunjukkan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara global sejak 1980-an (New Yorker, 2023). Namun, di sisi lain, neoliberalisme juga memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi, melemahkan perlindungan negara terhadap warga, dan memperluas komodifikasi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan (Harvey, 2005). Sangaji (2009) menegaskan bahwa idiom “kemerdekaan” dalam neoliberalisme memiliki tafsir yang timpang: apa yang dipandang sebagai kebebasan oleh kelompok elit seringkali justru menjadi penderitaan bagi kelompok marjinal.
Sebagai kesimpulan, neoliberalisme merupakan hasil pergulatan panjang antara ide, krisis, dan politik global. Ia lahir dari tradisi liberalisme klasik, diperkuat oleh pemikir abad ke-20, lalu menjadi dominan sejak 1980-an melalui dukungan negara-negara besar dan lembaga internasional. Meski berhasil mendorong globalisasi ekonomi, neoliberalisme juga membawa konsekuensi serius berupa ketimpangan, eksklusi sosial, dan krisis ekologi. Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah neoliberalisme masih relevan sebagai model pembangunan global, atau justru sedang mengalami krisis legitimasi yang akan melahirkan paradigma baru.
REFERENSI
Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
Harvey, D. (2007). Neoliberalism as Creative Destruction. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 610(1).
Kotz, D. M. (2015). The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism. Harvard University Press.
Sangaji, A. (2009). Neoliberalisme (1). IndoProgress.