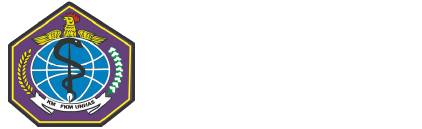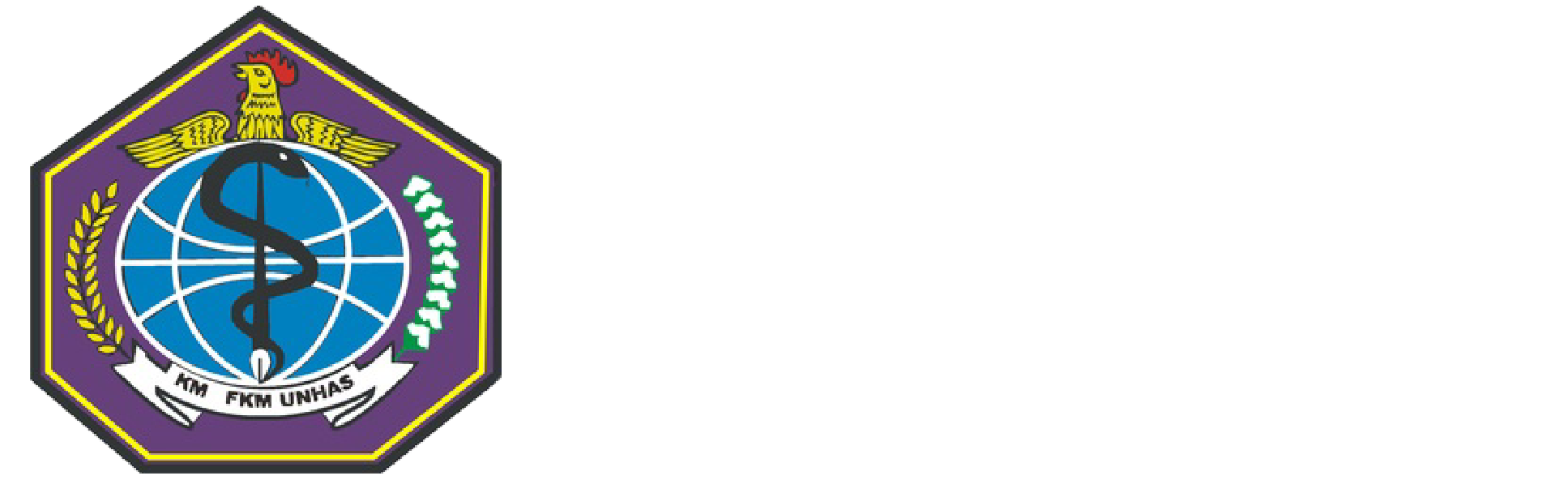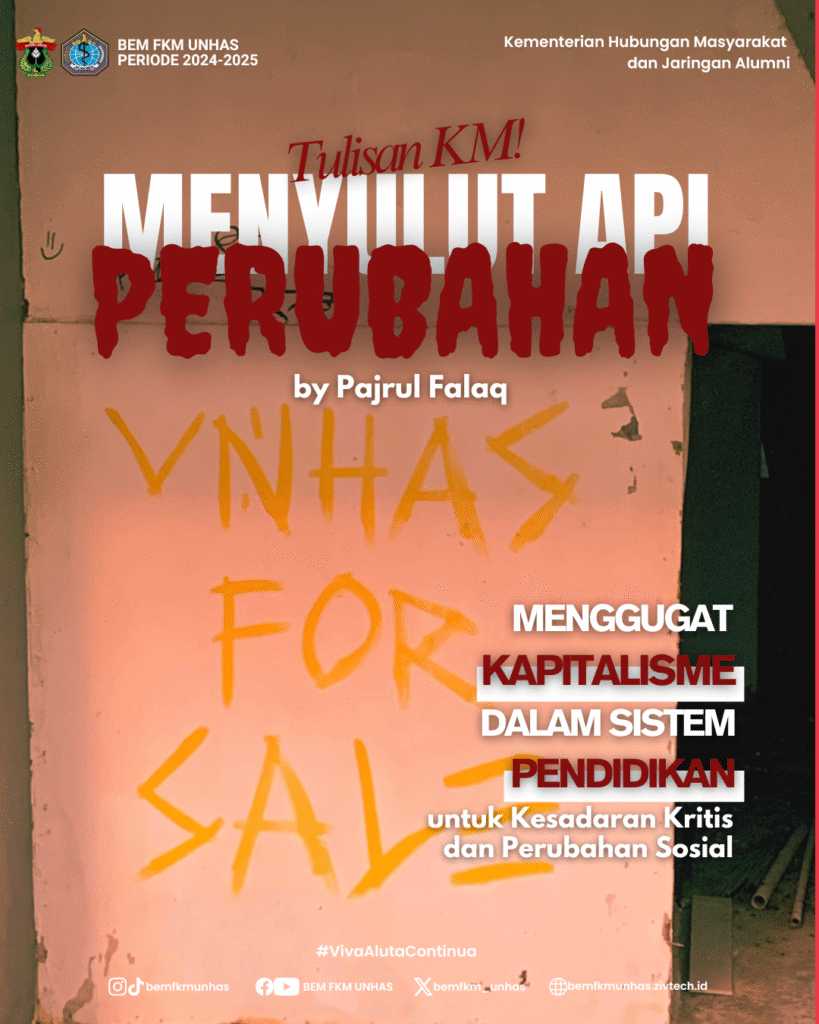
Menyulut Api Perubahan: Menggugat Kapitalisme dalam Sistem Pendidikan untuk Kesadaran Kritis dan Perubahan Sosial
Dalam konsepsi idealnya, institusi pendidikan dianggap sebagai lembaga yang memiliki peran vital dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kemajuan masyarakat. Pendekatan pendidikan harus mengarahkan individu menuju kesadaran kritis dan mengoptimalkan potensi mereka. Sebagai hasilnya, SDM yang telah melalui proses pendidikan diharapkan dapat berkontribusi kembali ke masyarakat untuk membangun peradaban secara kolektif menuju perubahan yang lebih baik. Namun, realitas yang diamati menunjukkan anomali yang mencolok dalam masyarakat saat ini. Masyarakat cenderung memiliki pola pikir pragmatis dan mengalami krisis nalar kritis. Mereka cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi, minim idealisme, dan pasif terhadap masalah yang ada di sekitar mereka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis tentang peran aktual institusi pendidikan dalam masyarakat saat ini. Apakah institusi pendidikan masih memainkan peran sesuai dengan proyeksi idealnya? Bagaimana memengaruhi pola pikir masyarakat saat ini?
Dalam “Dark Academia: How Universities Die”, Peter Fleming menjelajahi dampak negatif dari struktur birokrasi dan neoliberalisme di lingkungan akademis, yang mengubah universitas menjadi lingkungan kerja yang tidak sehat. Buku ini secara tajam menggambarkan rasa putus asa dan kekecewaan karena kehilangan lingkungan intelektual yang diharapkan oleh para akademisi, seperti yang ditulis oleh Chelsea Guo, namun dia juga mempertanyakan apakah institusi akademis tradisional pernah benar-benar menjadi tempat perlindungan bagi semua orang. Arya Hadi Dharmawan memberikan analisis mendalam tentang sisi gelap kampus dengan menguraikan delapan fenomena yang telah dijelaskan oleh Fleming:
- Elitisme. Kampus menjadi semakin elit sehingga terisolasi dari masyarakat luas. Di Indonesia, para peneliti dan dosen sering kali jauh dari memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan inovasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat bisa merasa tersinggung oleh elitisme ini jika peneliti terus-menerus berusaha untuk mempertahankan posisi puncak.
- Pabrik pengetahuan. Kampus dianggap sebagai semacam pabrik pengetahuan. Di Indonesia, kinerja akademisi sering diukur melalui indeks kinerja utama sehingga penelitian sering dianggap sebagai produksi barang.
- Birokrasi kampus. Universitas sering terjebak dalam struktur organisasi yang birokratis. Alih-alih menjawab permasalahan masyarakat, para ilmuwan sering kali sibuk mengejar angka kredit untuk memenuhi persyaratan birokrasi.
- Angka kredit. Capaian kinerja sering kali diukur melalui angka-angka tertentu yang harus dipenuhi oleh para dosen. Jumlah publikasi dan jabatan akademis menjadi yang utama, bukan pada substansi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- Homo academicus. Ada kecenderungan terjadi kompleksitas masalah mental pada para dosen karena kurangnya interaksi sosial, kesepian, stres, dan masalah kesehatan mental lainnya yang disebabkan oleh fokus pada penelitian dan pemenuhan tuntutan birokrasi kampus. Di Indonesia, gejala ini belum begitu mencolok.
- Kontrol negara. Kebebasan akademik sering kali terbatasi karena campur tangan negara dalam menentukan kebijakan akademik dan penunjukan pejabat kampus. Pengawasan akademik juga dilakukan melalui angka-angka yang harus dipenuhi oleh para dosen.
- Selebritas akademik. Terdapat sindrom popularitas di kalangan dosen yang termanifestasi dalam cara mereka memperlihatkan diri dan pendapat mereka di berbagai forum. Di Indonesia, fenomena ini kadang-kadang lebih parah karena popularitas dianggap sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
- Krisis keuangan mahasiswa. Di negara-negara barat, fenomena ini umum terjadi karena mahasiswa sering kali harus meminjam uang dari bank untuk membayar biaya kuliah yang tinggi. Meskipun di Indonesia fenomena ini belum sebegitu parah, tetapi beberapa orang tua mahasiswa telah mengalami kesulitan finansial dan terjerat dengan pinjaman dari rentenir karena tidak mampu membayar uang pangkal atau SPP anak mereka.
Dengan munculnya fenomena-fenomena tersebut, hak atas pendidikan tidak lagi menjadi hak yang dapat diakses oleh setiap individu. Perguruan tinggi telah berubah menjadi entitas bisnis yang membuat akses ke pendidikan tinggi tidak lagi mudah dijangkau oleh semua orang. Bahkan, ketimpangan yang seharusnya diselesaikan oleh sektor pendidikan justru semakin merajalela di dalamnya. Hariadi Kartodihardjo menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Fleming adalah hasil dari modernisasi perguruan tinggi yang berujung pada konsekuensi yang fatal. Menurut Hariadi, ada tiga aspek yang menjadi penyebab terjadinya fenomena gelap di kampus, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fleming:
Pertama, masalah kebebasan. Pasal-pasal dalam konstitusi dan undang-undang pendidikan sebelumnya menjamin kebebasan berpendapat dalam segala hal. Namun, upaya untuk menghapus pasal-pasal ini dilakukan melalui omnibus law UU Cipta Kerja.
Kedua, konflik kepentingan dan korupsi telah mengakibatkan hilangnya kebebasan berpendapat. Jabatan di sektor pendidikan bahkan diperjualbelikan, sehingga para pelaku di dalamnya tidak dapat lagi menyuarakan anti-korupsi karena mereka sendiri terlibat dalamnya.
Hariadi merujuk pada data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2021), yang menemukan bahwa jabatan dalam pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, dijual dengan tarif tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana korupsi telah merasuki sektor pendidikan.
Ketiga, daya tahan personal. Dalam era liberalisasi, setiap peneliti dan dosen harus memiliki daya tahan yang kuat untuk mempertahankan kebebasan berpendapat. Namun, seringkali kebebasan tersebut diisi oleh oligarki dan politisi yang memiliki kepentingan tertentu.
Sebagai akibatnya, kebebasan yang seharusnya dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk menghasilkan inovasi dipenuhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, RUU Cipta Kerja menjadi simbol dari bagaimana kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh politisi dan oligarki untuk memenuhi kepentingan mereka. sepakat bahwa masalah sisi gelap universitas telah mulai muncul di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan fundamental di dalam kampus dan peningkatan daya tahan personal bagi setiap ilmuwan untuk mengisi kebebasan berpendapat dengan ilmu dan pengetahuan guna mencegah kepentingan lain menguasainya.
Selanjutnya mari kita mencoba melacak relasi dalam proses berpengetahuan kita hari ini.Mengutip Herbert Marcuse dalam bukunya, “Manusia Satu Dimensi,” Herbert Marcuse menggambarkan peradaban industri kapitalisme sebagai sebuah masyarakat yang kehilangan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Ini terlihat dari manusia yang terperangkap dalam kesadaran palsu, melihat status quo dan masalah sekitarnya sebagai sesuatu yang alami dan wajar, tanpa menyadari bahwa kondisi tersebut adalah hasil dari kekuasaan kapitalisme. Kehilangan kemampuan berpikir kritis oleh individu dalam masyarakat ini berkaitan erat dengan cara represi yang dilakukan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Tidak seperti kapitalisme negara yang menggunakan represi fisik dan penindasan secara langsung, kapitalisme industri menggunakan berbagai bentuk ekspresi represif yang lebih terselubung. Institusi-institusi seperti pendidikan, media, gaya hidup, dan seni menjadi alat untuk menciptakan kesadaran palsu.
Untuk memahami peran pendidikan dalam membentuk kesadaran pasif individu dalam masyarakat, konsep filosofis Louis Althusser tentang RSA (Repressive State Apparatus) dan ISA (Ideological State Apparatus) dapat menjadi pedoman. Althusser membagi institusi negara menjadi dua kategori: RSA yang bertanggung jawab atas pendisiplinan fisik melalui kekerasan seperti polisi dan tentara, dan ISA yang bertanggung jawab atas penanaman kesadaran palsu melalui pendidikan, media, dan seni. Dalam konteks ini, pendidikan berperan dalam menciptakan kesadaran palsu dengan mengurangi kemampuan berpikir kritis individu. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendorong rasionalitas instrumental, menekankan pada ilmu pengetahuan teknis dan praktis yang terpisah dari realitas. Ini menghambat pertumbuhan kesadaran dengan mengabaikan ilmu pengetahuan emansipatoris yang berbasis pada realitas.