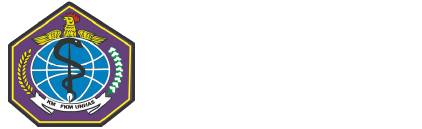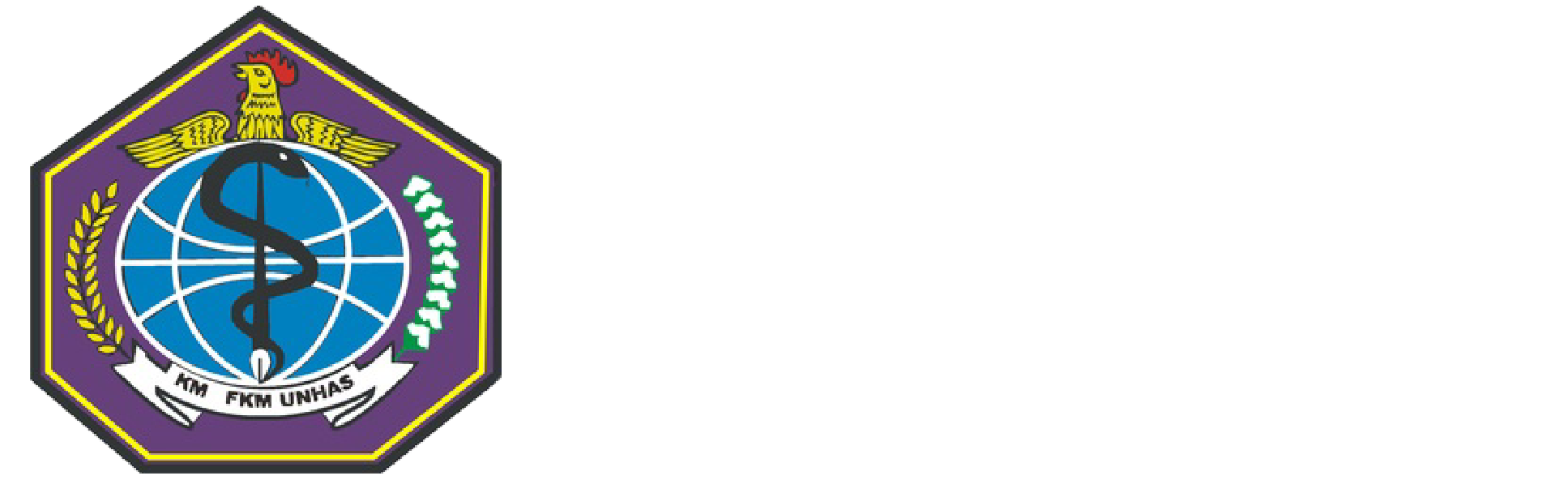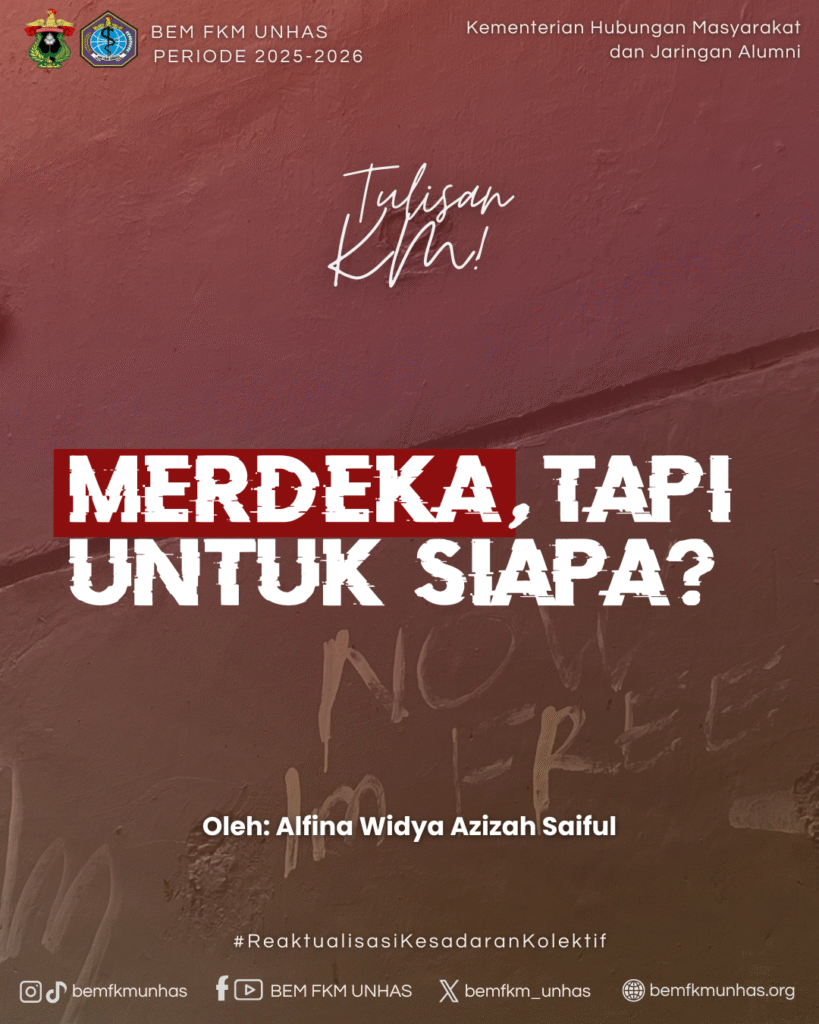
Merdeka, Tapi Untuk Siapa?
Pendahuluan
Setiap tanggal 17 Agustus, kita dihadapkan pada peringatan yang sakral yakni hari kemerdekaan. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dikumandangkan, dan pidato-pidato kemenangan dibacakan dengan penuh semangat. Namun, dalam gegap gempita seremoni itu, muncul satu pertanyaan yang tak kunjung usai: apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau jangan-jangan, kemerdekaan yang kita rayakan hanya sebatas simbol, sementara realitas sehari-hari masih diwarnai oleh ketimpangan, penindasan, dan dominasi kekuasaan yang bersalin rupa?
Dalam konteks pendidikan tinggi, pertanyaan ini menjadi semakin relevan. Kampus yang seharusnya menjadi ruang pembebasan intelektual kini justru dipenuhi dengan logika pasar, komersialisasi pendidikan, dan tekanan administratif yang mengekang. Mahasiswa yang idealnya menjadi subjek aktif dalam proses berpikir dan bertindak, perlahan diarahkan menjadi konsumen pengetahuan, dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan industri, bukan untuk membebaskan masyarakat. Maka, kemerdekaan dalam kampus hari ini bukan hanya dipertanyakan, tetapi harus digugat secara mendasar.
Realitas ini memunculkan satu kesadaran penting bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja sebagai hadiah sejarah, melainkan harus terus diperjuangkan secara kritis dan kolektif. Gerakan mahasiswa, dalam hal ini, memainkan peran penting sebagai pengingat dan pendorong arah perubahan. Namun perjuangan tersebut tak boleh berhenti pada tuntutan-tuntutan administratif semata. Ia harus berkembang menjadi perjuangan emansipatoris yang menyasar akar persoalan relasi kuasa, struktur ekonomi-politik, dan ideologi yang membentuk wajah kampus hari ini.
Dari sinilah kita perlu bertanya ulang, bukan hanya soal siapa yang “belum merdeka”, tapi juga apa arti merdeka itu sendiri. Apakah sekadar bebas memilih jurusan? Bebas berpendapat di kelas? Atau justru lebih dalam bebas dari penindasan sistemik yang menjadikan pendidikan sebagai alat dominasi?
Menelisik Jejak Masalalu
Neoliberalisme adalah sebuah paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu melalui mekanisme pasar bebas, perdagangan bebas, dan pengakuan mutlak terhadap kepemilikan pribadi. Paham ini dapat dimaknai sebagai perpaduan antara prinsip liberalisme yang mengedepankan otonomi personal, dan doktrin pasar bebas dari tradisi ekonomi neoklasik. Para pendukungnya menempatkan martabat manusia dan kemerdekaan individu sebagai “nilai sentral peradaban”. Bagi kaum neoliberal, campur tangan pemerintah, sekecil apa pun, adalah ancaman terhadap kebebasan sejati.
Secara garis besar, neoliberalisme merupakan bentuk kapitalisme yang paling ekstrem, di mana peran pemerintah dalam urusan ekonomi diminimalisir dan diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar. Asumsinya sederhana, yakni pasar memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa perlu campur tangan siapapun. Segala bentuk intervensi pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan pasar, bahkan merusak mekanisme alamiahnya. Dalam praktiknya, doktrin ini diwujudkan melalui liberalisasi perdagangan, keuangan, dan investasi swasta, termasuk privatisasi tanggung jawab sosial yang sebelumnya diemban oleh pemerintah. Tujuannya jelas untuk memastikan arus barang dan jasa, pergerakan modal, serta kebebasan berinvestasi dapat berlangsung tanpa hambatan di kancah global.
Meski digadang-gadang sebagai sistem yang paling efisien, neoliberalisme pada dasarnya bersifat utopis. Belum ada bukti sejarah yang menunjukkan pasar dapat beroperasi tanpa intervensi pemerintah. Justru sebaliknya, pasar dapat berfungsi melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Artinya, apa yang disebut “pasar bebas” atau “perdagangan bebas” bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan produk dari keputusan-keputusan politik yang disepakati di parlemen, kementerian, atau bahkan di hotel-hotel mewah. Ironisnya, hal ini berlaku bagi pemerintah mana pun, baik yang terpilih secara demokratis maupun yang berkuasa melalui kudeta. Bahkan, demi kepentingan pasar, berbagai bentuk pemerintahan bisa menyebar teror dengan beragam cara untuk memastikan sistem ini berjalan lancar.
Dalam sejarah, Polanyi menunjukkan bahwa laissez-faire sejatinya dilindungi oleh negara, dimana pasar tidak pernah tumbuh secara alamiah, melainkan melalui campur tangan pemerintah. Lebih jauh, David Harvey mengungkapkan bahwa masalah paling mendasar dari neoliberalisme adalah pengerukan aset dan kekayaan dari masyarakat luas ke tangan segelintir elite, serta dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya. Ia menyebut proses ini sebagai “akumulasi melalui perampasan” (accumulation by dispossession). Proses ini mencakup komodifikasi dan privatisasi tanah yang disertai penggusuran paksa, konversi hak milik bersama menjadi milik pribadi eksklusif, pelarangan paksa atas kepemilikan komunal, komodifikasi tenaga kerja dan penghapusan model produksi alternatif, pengambilalihan aset secara kolonial/neo-kolonial/imperial (termasuk sumber daya alam), monetisasi nilai tukar dan tanah, hingga praktik pinjaman berbunga mencekik dan penggunaan sistem kredit yang merusak. Negara, dengan monopolinya atas kekerasan dan pembuatan aturan, memainkan peran penting dalam mendukung proses eksploitatif ini.
Di Indonesia, ide-ide neoliberalisme telah berkembang secara bertahap, setidaknya sejak awal Orde Baru, dan semakin pesat setelah era Reformasi. Ini terlihat dari rantai kebijakan pro-pasar yang terus-menerus diterapkan sejak kejatuhan rezim Soekarno hingga pasca-Soeharto. Salah satu contoh paling mencolok adalah perkembangan masif industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan. Eksploitasi kekayaan di sektor-sektor ini semakin intensif setelah liberalisasi investasi dan perdagangan, penguatan hak milik pribadi, dan bahkan penggunaan aparat bersenjata untuk mengamankannya. Pergantian rezim dari Orde Baru yang diktator ke era Reformasi ternyata tidak banyak mengubah substansi hubungan antara negara dan modal. Kedua rezim tersebut, pada dasarnya, tetap berfungsi untuk mengurusi kepentingan kaum borjuis, melakukan apa saja demi kelangsungan proses pengerukan kekayaan.
Dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, neoliberalisme tampak nyata melalui berbagai kebijakan yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas, bukan lagi sebagai hak dasar warga negara. Pendidikan tinggi, khususnya, telah mengalami komersialisasi yang sangat masif. Biaya kuliah yang terus meningkat, sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin memberatkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta berkembangnya status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) adalah contoh konkret dari penerapan prinsip pasar dalam dunia akademik. Prinsip efisiensi dan profitabilitas menggantikan semangat pelayanan publik, di mana institusi pendidikan dituntut untuk mencari “pendapatan sendiri” melalui kerjasama dengan sektor swasta, pengembangan unit bisnis, hingga pemberlakuan biaya tinggi untuk layanan akademik maupun non-akademik. Kampus yang seharusnya menjadi ruang produksi ilmu pengetahuan dan pembebasan justru berubah menjadi “korporasi pendidikan” yang tunduk pada logika pasar dan kepentingan modal. Dalam situasi ini, akses terhadap pendidikan bermutu menjadi semakin eksklusif, hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki segelontor uang untuk dibayarkan, sementara kelompok yang memiliki keterbatasan terhadap nilai jual pendidikan yang menjadi syarat tersebut semakin terpinggirkan dan berujung tertinggal. Akibatnya, ketimpangan sosial dalam akses pendidikan semakin melebar, dan perguruan tinggi tidak lagi berfungsi sebagai alat mobilitas sosial, melainkan memperkuat struktur kelas yang timpang. Hal ini menegaskan bahwa neoliberalisme dalam pendidikan tidak hanya menggerus semangat keadilan sosial, tetapi juga mengancam makna sejati dari pendidikan itu sendiri sebagai alat emansipasi.
Menerka Raut Wajah Kampus Hari Ini
Jika kita mencermati wajah kampus hari ini, kita akan menemukan sebuah paradoks yang kontras dengan idealisme awal pendidikan nasional. Karl Marx dan Friedrich Engels, dalam Communist Manifesto (1888), pernah menegaskan bahwa pendidikan itu sejatinya bersifat sosial, dibentuk oleh kondisi masyarakat serta intervensi langsung atau tidak langsung dari institusi pendidikan itu sendiri, yakni mereka berupaya menyelamatkan pendidikan dari pengaruh kelas penguasa. Sayangnya, pemikiran ini menjadi sangat relevan saat kita menyaksikan realitas di kampus sekarang. Hierarki kekuasaan, yang bisa diartikan sebagai “pihak-pihak yang gelap mata”, justru tercipta dari melambungnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Setiap tahun, seolah-olah selalu ada kebijakan yang tidak masuk akal, yang secara bertahap mengikis simpati publik hingga habis tak bersisa akibat dominasi oligarki. Nominal satu rupiah pada biaya pendidikan kini berpotensi melambung tanpa batas jika tidak segera dijegal. Berbagai indikator yang diklaim menjadi dasar kenaikan biaya tersebut seakan salah sasaran. Anggaran yang seharusnya memungkinkan mahasiswa memperoleh pendidikan yang layak, bahkan tak berbayar, kini tersembunyi di balik kabut kerakusan para penguasa yang ironisnya juga mengaku sebagai “orang berpendidikan”. Inilah realitas pahit di kampus hari ini, di mana pendidikan yang seharusnya menjadi hak publik, justru bertransformasi menjadi alat pemisah dan penentu status sosial, jauh dari cita-cita mulia dari sistem pendidikan itu sendiri.
Bagaimana seharusnya wujud dari pendidikan ideal di tubuh kampus yang kita pijak hari ini? Tentu, kita bisa memulai dengan menengok kembali cita-cita luhur yang menjadi landasan pendidikan nasional. Pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia sejatinya digagas untuk memperbaiki visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan tantangan zaman. Visi utamanya adalah membentuk sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, yang mampu memberdayakan seluruh warga negara. Melalui pendidikan, setiap individu diharapkan dapat berkembang menjadi insan berkualitas, cakap, dan proaktif dalam menghadapi dinamika global yang senantiasa berubah. Untuk mewujudkan visi ini, pendidikan nasional mengemban misi penting mulai dari memperluas dan memeratakan akses pendidikan bermutu, memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh dari usia dini hingga akhir hayat, meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk membentuk kepribadian yang bermoral, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan, hingga memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan akhir menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Wujud seperti itu yang semestinya menjadi gambaran ketika kita berkaca pada kondisi pendidikan di kampus hari ini, akan tetapi serpihan kaca dari pengkhianatan atas pendidikan ideal itu sendiri yang seakan menyadarkan kita bahwa wajah kampus hari ini telah terhiasi oleh ‘luka’ yang sangat tidak elok nampaknya.
Peningkatan biaya pendidikan adalah manifestasi nyata dari ideologi neoliberal yang berupaya mengkomodifikasi pengetahuan. Paradigma pendidikan tinggi tidak lagi berlandaskan pada implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, melainkan lebih pada penghambaan terhadap mekanisme pasar. Dari perspektif negara, pendidikan tinggi telah bertransformasi menjadi “commercial goods” dan bukan lagi “public goods” yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, akses terhadap pendidikan menjadi semakin eksklusif karena telah bermetamorfosis menjadi komoditas mewah. UKT kini berfungsi sebagai filter dan alat kontrol terhadap mahasiswa. Ketika mahasiswa kesulitan membayar biaya kuliah yang tinggi, berbagai bantuan bersyarat, yang hanya merupakan solusi semu yang dalam keberlanjutannya segala rugi akan berbalik pada mahasiswa itu sendiri.
Permasalahan biaya yang tinggi tersebut turut juga dirasakan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin, yang mana telah dikeluarka kebijakan terbaru dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 03648/UN4.1/KEP2025 Tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Sarjana Terapan Tahun Akademik 2025/2026. Hal ini masih menjadi momok berat yang menjegal kemampuan setiap orang untuk mengakses pendidikan dalam hal ini konteksnya pada pendiikan tinggi dalam sebuat universitas. Dari peraturan tersebut didapati bahwa UKT di golongan atau kelompok I masih teteap berjumlah Rp. 500.000 sama dengan tahun sebelumnya dan meskipun kebijakan penambahan golongan sembilan yang sempat terjadi di tahun 2024 tidak jadi diterapkan, akan tetapi UKT di golongan atau kelompok VIII secara nominal masih tetap tinggi tergantung BKT yang sama saja tidak realistisnya untuk sebuah syarat bagi tiap orang mengakses sebuah pendidikan. Kebijakan tersebut tentunya tidak hanya berjalan dan menjadi keresahan mahasiswa di Universitas Hasanuddin saja, begitupun di kampus lain yang juga menyandang status PTN-BH. Hal tersebut merupakan akibat dari kebijakan yang masih digunakan dari kemendikbudristek yang tercantum dalam Permendikbudristek RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kemendikbudristek.
Ini adalah wajah kampus yang kehilangan idealismenya, dimana tidak ada seorang pun yang ingin berlama-lama di kampus dengan beban biaya yang begitu besar. Oleh karena itu, tuntutan agar pendidikan tinggi haruslah gratis atau setidaknya sangat aksesibel bagi seluruh kelompok masyarakat menjadi relevan. Meskipun disadari bahwa menuntut pendidikan gratis bukanlah solusi tunggal terhadap infiltrasi neoliberalisme global, dan untuk menghilangkan neoliberalisasi pendidikan tinggi diperlukan penyerangan terhadap berbagai prakondisi yang memungkinkan lahirnya paham tersebut, tuntutan pendidikan gratis dapat dipandang sebagai langkah awal yang fundamental untuk meruntuhkan neoliberalisme secara utuh. Jadi, dengan memahami realitas wajah kampus hari ini, menjadi realistis untuk terus menyuarakan dan memperjuangkan pendidikan gratis tersebut.
Meraba Celah Pembebasan: Dari Realitas, Menuju Emansipatoris
Di tengah gelombang komodifikasi pendidikan yang kian dalam, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang arah gerakan mahasiswa agar tidak semata-mata menjadi reaksi atas gejolak kebijakan, melainkan bergerak sebagai kekuatan historis yang sadar akan posisi dan perannya dalam medan perjuangan sosial. Gerakan mahasiswa hari ini tidak cukup hanya bermuara pada tuntutan administratif seperti penurunan UKT atau transparansi anggaran, tetapi harus mampu menggali akar struktural dari persoalan tersebut yakni relasi kuasa antara negara, pasar, dan pendidikan. Disinilah celah pembebasan dapat mulai diraba bukan sekadar dari reaksi terhadap kebijakan yang hadir, tetapi dari kesadaran ideologis untuk mendobrak sistem yang membuat pendidikan tunduk pada logika pasar.
Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak lagi cukup diposisikan hanya sebagai korban dari kebijakan yang merugikan. Mahasiswa perlu melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok yang sadar dan mampu mengambil sikap terhadap kondisi yang terjadi. Untuk bisa bergerak menuju pembebasan, cara berpikir yang digunakan juga harus lebih dalam dan tidak hanya melihat mahalnya UKT atau sulitnya akses pendidikan sebagai masalah tunggal, tapi memahami bahwa semua itu berhubungan erat dengan sistem ekonomi global yang menempatkan pendidikan sebagai ladang keuntungan. Oleh karena itu, perjuangan mahasiswa tidak cukup hanya menuntut perubahan aturan, tapi juga harus berani mengkritisi dasar-dasar pemikiran yang menjadikan pendidikan sebagai barang dagangan. Inilah langkah awal menuju bentuk pendidikan yang membebaskan, di mana kampus tidak lagi dianggap tempat yang netral, melainkan sebagai ruang perjuangan gagasan yang menentukan arah masa depan masyarakat.
Dengan demikian, orientasi gerakan mahasiswa semestinya tidak hanya reaktif, tetapi juga transformatif. Gerakan tersebut harus melampaui sekadar mobilisasi massa atau aksi turun ke jalan, dan mulai mengonsolidasikan basis-basis pengetahuan kritis di ruang-ruang diskusi, pendidikan alternatif, hingga pengorganisasian komunitas. Emansipasi bukanlah utopia, tetapi suatu proses pembebasan yang dilakukan secara sadar, terus-menerus, dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam bingkai ini, ilmu pengetahuan tak lagi menjadi menara gading yang steril dari realitas, melainkan alat perjuangan yang berpihak dan membebaskan. Gerakan mahasiswa pun harus berani menjawab pertanyaan besar ini: apakah kampus masih menjadi tempat produksi kebenaran dan keadilan, atau telah berubah menjadi pabrik pencetak tenaga kerja yang tunduk pada pasar?
Dalam diri emansipatoris tersebut, keberpihakan menjadi arahan untuk menciptakan kesetaraan bagi subyek yang diperjuangkan. Selain itu, keberpihakan menjadi jaminan jika perjuangan mahasiswa bukanlah hal yang bebas nilai dan nihil. Terdapat subyek yang menjadi dasar analisa bagaimana perjuangan diarahkan dan ukuran kemenangannya. Sedangkan, aspek keterlibatan dalam penyelesaian masalah menjadi domain pembebasan bagi yang diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa. Pembebasan ini merupakan langkah humanisasi dari belenggu permasalahan ‘real’ di atas. Dalam perjuangan emanispatoris ini, gerakan mahasiswa dituntut untuk terus berkelanjutan dalam denyut gerakan sosial masyarakat.
Perjuangan emansipatoris menuntut bahwa mahasiswa bukan hanya berteriak melawan, tetapi juga merumuskan gagasan alternatif. Ini bisa dimulai dengan membangun narasi tanding terhadap dominasi neoliberalisme pendidikan yakni narasi yang membela pendidikan sebagai hak, bukan layanan, sebagai ruang pembebasan, bukan investasi. Gagasan-gagasan ini dapat memperkuat posisi mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual yang mampu mendorong transformasi struktural. Maka, meraba celah pembebasan bukan sekadar retorika, tetapi panggilan untuk menegaskan posisi politik mahasiswa: berpihak pada yang tertindas, bersuara untuk yang dibungkam, dan bertindak untuk yang dilupakan. Dari titik ini, perjuangan menuju kampus yang demokratis, inklusif, dan humanis dapat mulai ditapaki harusnya bukan sebagai mimpi, melainkan sebagai keniscayaan yang diperjuangkan bersama.
Merdeka Yang Sejati Itu, Seperti Apa?
Pada titik ini, kita patut bertanya ulang, benarkah semua bentuk gerakan perlawanan, perjuangan, dan konsolidasi yang dilakukan selama ini telah mengarah pada kebebasan yang sejati? Ataukah semua itu hanya bagian dari siklus perlawanan yang terus berputar, tanpa pernah benar-benar menyentuh akar persoalan? Wacana emansipasi, perlawanan terhadap neoliberalisme, bahkan kritik atas birokrasi kampus seringkali hadir sebagai retorika yang menggugah, namun dalam praktiknya tetap berhadapan dengan tembok kekuasaan yang kokoh dan sulit ditembus. Maka, pertanyaan soal “kemerdekaan pada konteks pendidikan hari ini” tidak bisa dijawab secara gegabah, sebab makna dari merdeka itu sendiri kini menjadi kabur dan terkooptasi oleh narasi kekuasaan.
Kemerdekaan yang sejati mestinya berarti bebas dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan yang tidak kasat mata, seperti tekanan ekonomi, ketidakadilan struktural, hingga manipulasi ideologi lewat sistem pendidikan. Akan tetapi, ketika kampus yang seharusnya menjadi ruang aman dan bebas justru berubah menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial, bisakah kita benar-benar menyebut diri kita “merdeka”? Jika mahasiswa harus berjuang mati-matian hanya untuk bertahan di bangku kuliah, jika akses pendidikan ditentukan oleh latar belakang ekonomi, dan jika ilmu pengetahuan hanya diproduksi untuk kepentingan pasar, maka jelas masih banyak yang harus diperjuangkan. Merdeka bukan sekadar tidak dijajah secara fisik, melainkan terbebas dari segala bentuk dominasi yang membelenggu potensi dan martabat manusia.
Maka dari itu, penting untuk menyadari bahwa perjuangan menuju kemerdekaan sejati bukanlah perjalanan yang linear dan selesai dalam satu generasi. Ia adalah proses panjang yang menuntut kesadaran kolektif, keberanian mengambil risiko, dan kemauan untuk menyatukan kekuatan lintas sektor. Gerakan mahasiswa yang berangkat dari realitas sosial harus berani melampaui batas-batas sektoralnya dan membangun solidaritas dengan kelompok lain yang mengalami ketertindasan serupa. Sebab problem ‘real’ yang dihadapi bukan hanya milik mahasiswa, tetapi juga buruh, petani, perempuan, masyarakat adat, dan kelas-kelas tertindas lainnya. Dalam kebersamaan inilah kita bisa mulai menapaki jalan panjang menuju pembebasan yang sejati.
Namun sampai di sini pun kita belum bisa menjawab secara pasti: apakah kebebasan itu betul-betul mungkin, atau hanya utopia yang terus kita kejar? Mungkin jawabannya justru terletak pada keberanian untuk terus bertanya, terus menggugat, dan terus bergerak. Merdeka yang sejati bukanlah titik akhir yang bisa ditandai dalam sejarah, melainkan sebuah proses sadar untuk tidak berhenti melawan ketidakadilan, dalam bentuk apa pun. Maka tugas kita hari ini bukan hanya merayakan kemerdekaan, tapi memastikan bahwa kata “merdeka” tidak kehilangan maknanya, bahwa ia hidup di setiap ruang kelas, di setiap mimbar bebas, dan di setiap suara yang berani bersuara, meski sendirian.
Referensi:
Pontoh, C. Husain dan Sangadji, A. (2021). Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di Indonesia.
Ananta, D. Dwi. (2013). Gerakan Mahasiswa: Berangkat dari Mana dan Menuju ke Mana?. indoprogress.com.
Marx, K., Engels, F., Weick, R. (2019). The Communist Manifesto and Das Kapital. United
States: Knickerbocker Classics.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 03648/UN4.1/KEP2025 Tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Sarjana Terapan Tahun Akademik 2025/2026.
Permendikbudristek RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kemendikbudristek.
Makmuralto, A. (2007). Dalam Diam Kita Tertindas.