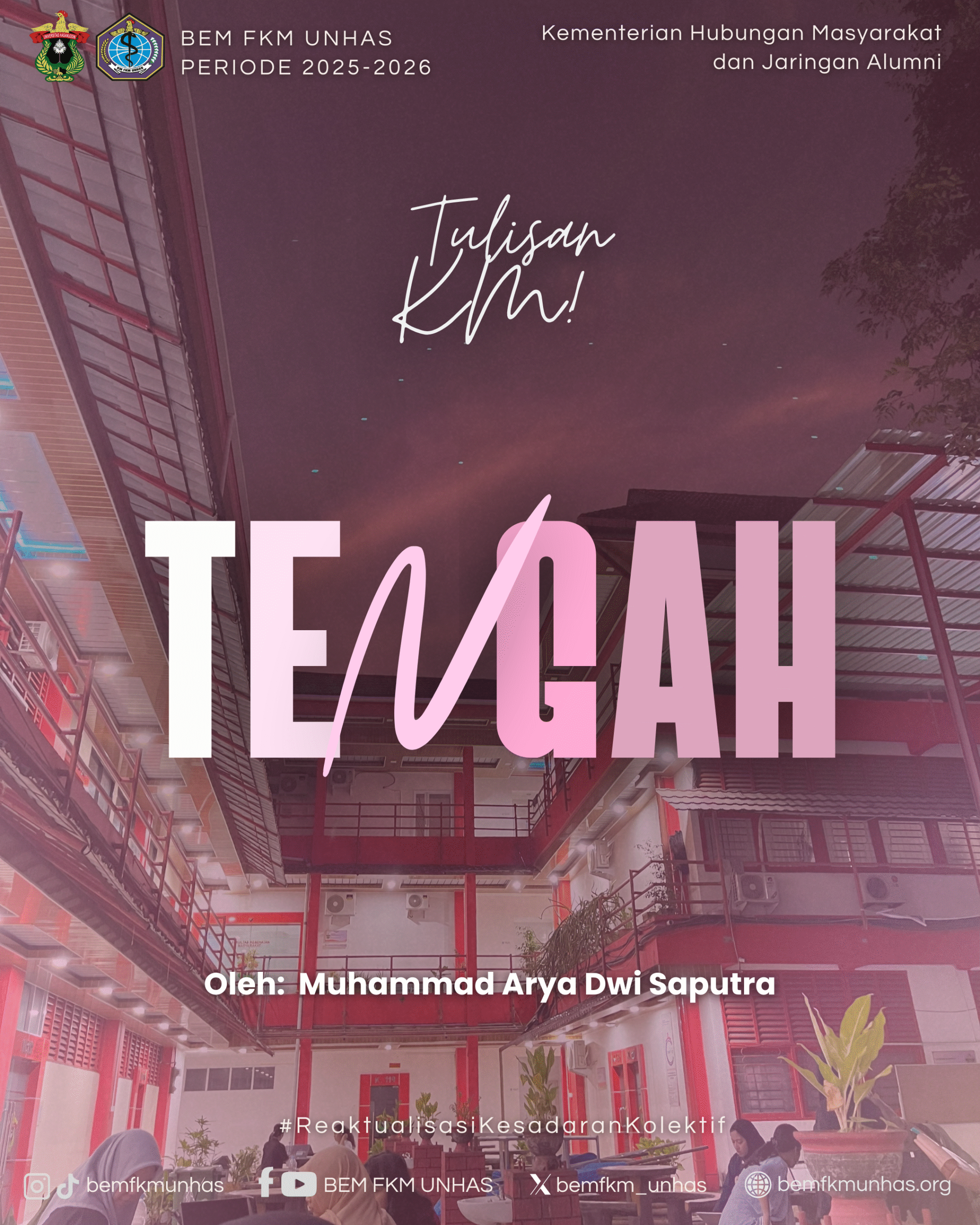Netralitas Politik dalam Pendidikan Tinggi, Rektor Tidak Boleh Berpolitik !!!
Dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, rektor memegang posisi strategis bukan hanya sebagai pemimpin administratif tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai etik, integritas akademik, dan otonomi keilmuan. Karena peran ini bersifat fundamental bagi keberlangsungan kualitas pendidikan tinggi, hukum nasional secara tegas maupun implisit memberikan batasan terhadap tindakan politik praktis oleh rektor, termasuk dukungan verbal, simbolik, maupun struktural kepada partai politik. Larangan tersebut semakin diperkuat oleh regulasi terbaru yang menuntut netralitas dan independensi seluruh pejabat publik dan pimpinan lembaga pendidikan.
Pengaturan paling mutakhir dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib menjamin keberlangsungan lingkungan belajar yang bebas dari intimidasi, tekanan, dan pengaruh eksternal yang menghambat otonomi akademik. Semangat UU ini memperjelas bahwa lembaga pendidikan harus dijauhkan dari konflik politik elektoral yang berpotensi merusak proses belajar-mengajar, merusak objektivitas ilmiah, dan menimbulkan polarisasi di antara sivitas akademika. Walaupun UU 20/2023 tidak memuat larangan eksplisit untuk rektor, prinsip penyelenggaraan pendidikan yang bebas tekanan politik memberi dasar normatif yang kuat bahwa pimpinan perguruan tinggi tidak boleh melakukan tindakan dukungan terhadap partai politik—sebab tindakan itu sendiri adalah bentuk tekanan struktural terhadap lingkungan pendidikan.
Sejalan dengan UU Sisdiknas terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang masih berlaku, menempatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai pilar penyelenggaraan perguruan tinggi. Dalam kerangka itu, rektor bertanggung jawab penuh menjaga independensi institusi dari intervensi politik apa pun. Dukungan rektor terhadap partai politik dapat dipandang sebagai ancaman langsung bagi otonomi akademik, karena berpotensi menciptakan relasi kuasa yang bias kepentingan, menekan kebebasan berpendapat dosen dan mahasiswa, serta membatasi ruang kritik terhadap kebijakan negara atau aktor politik tertentu. Dengan demikian, keterlibatan politik praktis oleh rektor bertentangan dengan mandat UU 12/2012 untuk memastikan ruang akademik tetap netral, otonom, dan bebas kepentingan.
Dari sisi pemerintahan pendidikan tinggi, PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi masih menjadi rujukan paling kuat terkait etika kepemimpinan perguruan tinggi. Aturan ini secara tegas mensyaratkan bahwa pimpinan perguruan tinggi harus menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan kelompok atau golongan. Ketika seorang rektor memberikan dukungan terbuka kepada partai politik, tindakan tersebut secara hukum dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan jabatan untuk kepentingan golongan, sehingga melanggar prinsip tata kelola yang diamanatkan PP 4/2014. Artinya, dukungan politik oleh rektor tidak hanya keliru secara etika, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum administratif.
Larangan yang lebih tegas muncul bagi rektor yang berstatus ASN, karena UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan perubahan regulasi turunannya telah diperbaharui melalui PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN, serta dipertegas kembali melalui SE KASN tahun 2023 dan 2024. ASN diwajibkan menjaga netralitas dari segala bentuk politik praktis dan dilarang memberikan dukungan kepada partai politik, peserta pemilu, serta dilarang menggunakan atribut, menghadiri deklarasi politik, atau menyampaikan pernyataan dukungan dalam bentuk apa pun. Rektor PTN yang merupakan ASN terikat penuh pada aturan ini; sehingga dukungan politik bukan hanya bertentangan dengan etika akademik, melainkan juga merupakan pelanggaran disiplin berat yang dapat berujung pada pemberhentian.
Selain itu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang masih berlaku dan menjadi rujukan terbaru dalam kontestasi politik, melarang penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye. Pelanggaran tidak harus berupa penggunaan ruang fisik; dukungan politik oleh rektor dapat dengan sendirinya dianggap sebagai bentuk politisasi fasilitas pendidikan karena otoritas jabatan rektor tidak bisa dipisahkan dari institusinya. Dalam banyak kasus, keberpihakan politik rektor akan menyeret nama universitas dan menjadikan kampus sebagai arena legitimasi politik elektoral, yang jelas dilarang oleh UU Pemilu dan bertentangan dengan norma netralitas lembaga pendidikan.
Seluruh regulasi terbaru ini memperlihatkan satu garis merah yang konsisten: negara menuntut agar pendidikan tinggi tetap steril dari intervensi politik praktis. Secara akademik, alasan ini sangat jelas: keterlibatan politik rektor akan mengganggu kebebasan keilmuan, merusak suasana ilmiah yang inklusif, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kualitas dan objektivitas universitas. Secara kelembagaan, hal itu berisiko menimbulkan konflik kepentingan, polarisasi internal, dan tekanan politik terhadap sivitas akademika. Secara hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap tata kelola, etika jabatan, dan disiplin ASN.
Berangkat dari norma terbaru dalam UU Sisdiknas 20/2023, UU Pendidikan Tinggi 12/2012, PP 4/2014, UU ASN berikut PP Disiplin ASN 94/2021, serta UU Pemilu 7/2017, dapat disimpulkan bahwa posisi rektor sebagai pimpinan tertinggi perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari tuntutan netralitas politik. Dengan dasar hukum yang kuat dan terkini ini, jelas bahwa rektor tidak boleh terlibat dalam politik praktis, termasuk menyatakan dukungan kepada partai politik, calon tertentu, atau kegiatan politik elektoral apa pun.