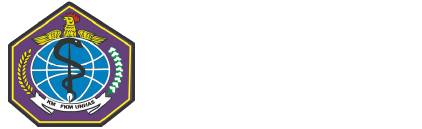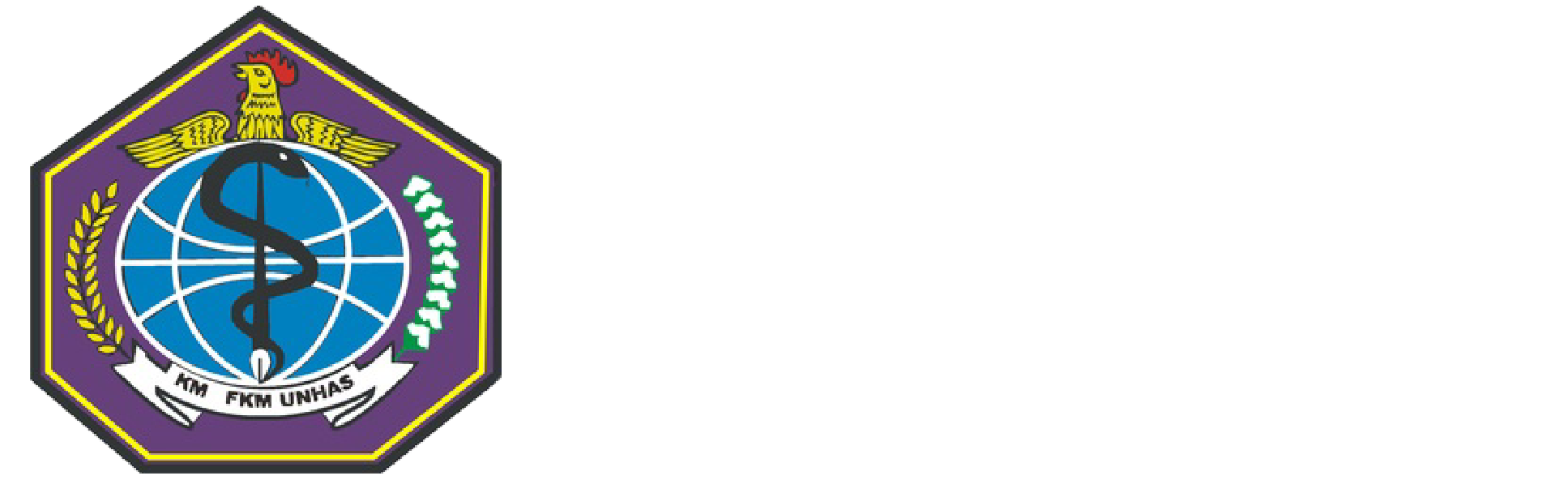Pendidikan Bukan Komoditas: Menggugat Neoliberalisme dalam Dunia Pendidikan
Pendidikan sejatinya adalah hak dasar setiap warga negara, bukan barang dagangan yang diperjualbelikan di pasar bebas. Namun, arus neoliberalisme telah menyeret dunia pendidikan masuk ke dalam logika pasar, di mana kualitas dan akses ditentukan oleh kemampuan ekonomi, bukan oleh hakikat keadilan sosial. Keberadaan HAM memiliki makna penting karena menjamin martabat dan kebebasan manusia dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Namun, bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan HAM tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Implementasinya harus selaras dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Salah satu bentuk hak warga negara yang sangat esensial adalah hak memperoleh pendidikan. Pendidikan yang layak merupakan kebutuhan utama untuk mengembangkan potensi diri sekaligus menjadi bekal menghadapi tantangan persaingan global yang semakin kompleks (Nadziroh et al., 2018). Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak atas pendidikan semakin dipengaruhi oleh arus neoliberalisme yang menekankan logika pasar, sehingga orientasi pendidikan kerap bergeser dari fungsi sosial menuju fungsi komersial. Neoliberalisme dalam pendidikan berlandaskan logika krisis yang menggeser orientasi akademik. Dampaknya, pendidikan semakin diarahkan pada komersialisasi, terutama melalui percepatan penggunaan pembelajaran digital. Seperti yang dijelaskan Teräs et al. (2020), pendekatan ini tidak berlandaskan pada praksis pedagogis yang menekankan kualitas instruksi, melainkan pada model bisnis yang menempatkan pendidikan sebagai sarana mencari keuntungan.
Neoliberalisme membawa sejumlah konsekuensi negatif bagi dunia pendidikan. Pergeseran orientasi akademik menuju logika pasar mendorong universitas dan sekolah berfungsi layaknya perusahaan, dengan tekanan tinggi pada kinerja guru serta orientasi pada ekonomi pengetahuan (Baltodano, 2012; Connell, 2013). Kebijakan neoliberal juga memicu korporatisasi lembaga pendidikan melalui program pelatihan guru jalur cepat, lahirnya pasar baru dalam pelatihan pendidik, serta melemahnya keahlian profesional, dan tata kelola lokal (Tucker & Fushell, 2021). Selain itu, penerapan model ekonomi neoliberal di berbagai negara, termasuk Eropa, memperburuk restrukturisasi sistem pendidikan yang berdampak langsung pada siswa, guru, dan sekolah (Muñoz, 2015; Hall & Pulsford, 2019). Secara lebih luas, neoliberalisme dikritik karena memunculkan privatisasi dan komodifikasi pendidikan, sehingga mengikis nilai pendidikan sebagai hak publik (Hill, 2012).
Munculnya neoliberalisme dalam pendidikan justru memperdalam kesenjangan sosial. Dengan logika pasar, sekolah tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai lembaga publik, melainkan dipaksa beroperasi layaknya perusahaan yang harus mencari keuntungan melalui komersialisasi dan marketisasi. Pola ini mengubah pendidikan menjadi komoditas, di mana akses dan kualitas sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi individu. Kondisi tersebut tampak jelas di Indonesia melalui diferensiasi tipe sekolah, seperti sekolah internasional, bilingual, unggulan, maupun label “sekolah favorit”. Program RSBI dan RSBN yang pernah dijalankan pemerintah pun akhirnya dibatalkan pada 2012 karena terbukti memperlebar ketidakadilan, di mana kelompok kaya lebih mudah mengakses pendidikan bermutu dibandingkan masyarakat kurang mampu. Tantangan semakin kompleks dengan hadirnya perdagangan bebas yang membuka arus tenaga kerja lintas negara. Jika kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik Indonesia tidak segera ditingkatkan, mereka berpotensi tersingkir dalam persaingan global. Hal ini menegaskan bahwa penerapan neoliberalisme tanpa kontrol justru berisiko mereduksi pendidikan menjadi instrumen pasar semata, alih-alih menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara (Adi Prastowo, 2017).
Meskipun kerap dikritik, neoliberalisme juga membawa sejumlah peluang positif bagi pendidikan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas memperkuat tata kelola yang lebih profesional dan terbuka bagi partisipasi publik. Di sisi lain, desentralisasi dan otonomi perguruan tinggi memberi fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Tekanan global mendorong pembaruan kurikulum yang lebih adaptif terhadap tuntutan dunia kerja, terutama dalam bidang vokasi dan teknologi. Selain itu, aliran investasi serta transfer teknologi dari luar negeri membantu modernisasi infrastruktur pendidikan dan memperluas akses belajar. Jika dimanfaatkan dengan tepat, potensi ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan menjadikan sistem pendidikan lebih kompetitif tanpa kehilangan pijakan pada nilai keadilan sosial dan kebangsaan. Jika orientasi pasar terlalu dominan, maka pemerataan akses akan terganggu. Pendidikan berpotensi hanya menguntungkan kelompok yang mampu secara ekonomi, sementara masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan layanan berkualitas. Dengan demikian, peluang yang dibawa neoliberalisme hanya bisa benar-benar bermanfaat apabila dikendalikan oleh kebijakan yang berlandaskan nilai keadilan sosial dan keberpihakan pada semua lapisan masyarakat.
Neoliberalisme dalam pendidikan membawa konsekuensi ganda di satu sisi membuka peluang transparansi, efisiensi, serta modernisasi melalui desentralisasi dan investasi global; namun di sisi lain memperdalam kesenjangan sosial dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas. Fenomena marketisasi sekolah, privatisasi, serta tekanan kompetisi global telah menjadikan akses dan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi individu. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pendidikan sebagai hak asasi manusia dan nilai keadilan sosial yang menjadi landasan Pancasila.
Untuk itu, negara perlu hadir secara lebih kuat sebagai pengendali arah pendidikan. Kebijakan publik harus menegaskan keberpihakan pada kelompok miskin dan rentan melalui subsidi pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta pemerataan sarana-prasarana. Selain itu, regulasi yang ketat perlu diterapkan agar dominasi logika pasar tidak mengikis esensi pendidikan sebagai hak dasar. Dengan demikian, peluang positif dari globalisasi dapat tetap dimanfaatkan, tetapi tanpa mengorbankan cita-cita utama pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata.
Referensi:
Andi Prastowo“Perubahan Mindset dan kesiapan guru sekolah dasar dalam persaingan Pendidikan di era MEA” Prosiding (2017)
Baltodano, M. 2012. Neoliberalism and the demise of public education: the corporatization of schools of education. International Journal of Qualitative Studies in Education, 25(4), 487–507.
Connell, R. 2013. The neoliberal cascade and education: an essay on the market agenda and its consequences. Critical Studies in Education, 54(2), 99–112.
Ferdino, M. F., & Sirozi, M. (2025). Dampak Ekonomi Neoliberal Terhadap Sistem Dan Tata Kelola Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains, 6(1), 80-88.
Hall, R., & Pulsford, M. 2019. Neoliberalism and primary education: Impacts of neoliberal policy on the lived experiences of primary school communities. Power and Education, 11(3), 241–251.
Muñoz, R. A. 2015. European Education Policy: A Historical and Critical Approach to Understanding the Impact of Neoliberalism in Europe. The Journal for Critical Education Policy Studies, 13, 19–42.
Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. Trihayu, 4(3), 259091.
Teräs, M., Suoranta, J., Teräs, H., & Curcher, M. (2020). Post-Covid-19 education and education technology ‘solutionism’: A seller’s market. Postdigital Science and Education, 2(3), 863-878.
Tucker, J., & Fushell, M. 2021. Neoliberal Influences: The Aftermath of Educational Reform-A Reflective Analysis. International Journal of Educational Reform, 30(4), 361–378.