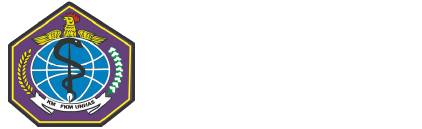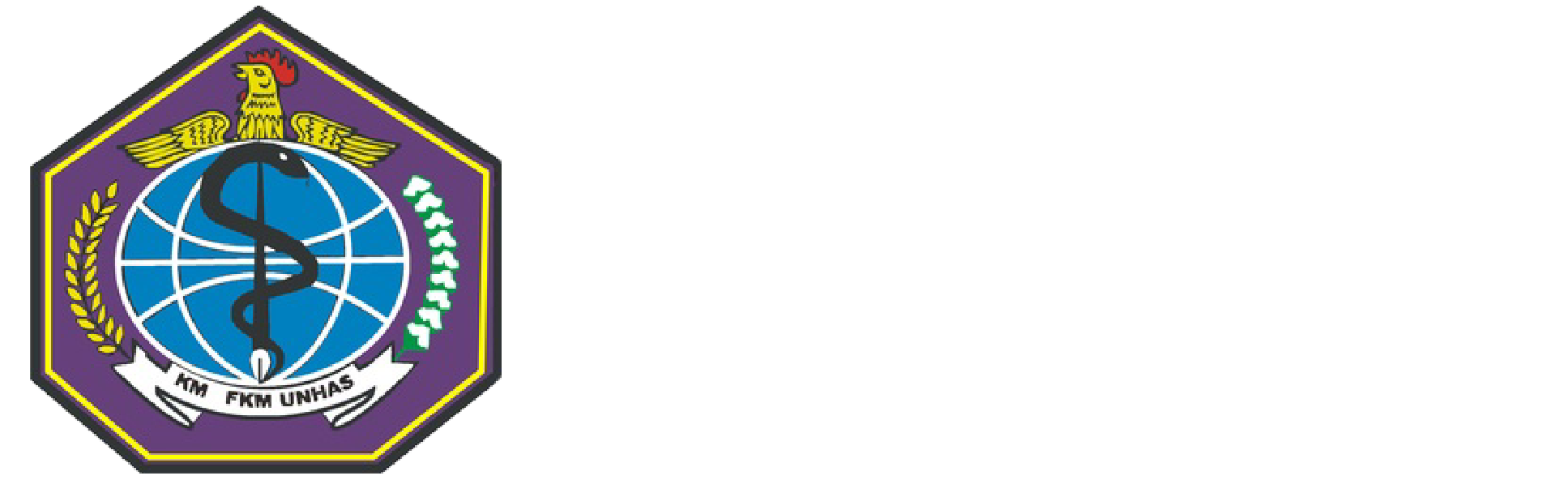Sehat sebagai Hak atau Barang Dagangan? Membongkar Logika Pasar di Sektor Kesehatan
Sejatinya, kesehatan adalah hak dasar setiap manusia yang telah menjadi kebutuhan universal dan tidak seharusnya bergantung pada status sosial atau kemampuan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, kesehatan sering kali berubah menjadi ladang bisnis, di mana tubuh manusia yang sedang kesakitan diperlakukan sebagai sumber keuntungan. Dengan adanya logika neoliberalisme ke dalam sektor publik, maka terjadilah perubahan cara negara dalam mengelola layanan publik termasuk sektor kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor kesehatan masuk ke dalam arus komodifikasi yang berakibat pada rumah sakit, obat-obatan, hingga skema asuransi diperlakukan layaknya sesuatu yang diperjualbelikan.
Pada awalnya, neoliberalisme muncul karena adanya keyakinan bahwa swasta lebih efisien daripada negara dalam mengelola layanan publik. Pandangan tersebut mengubah orientasi pelayanan kesehatan yang lebih berfokus pada keuntungan finansial dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Rumah sakit publik bertransformasi, dari yang sebelumnya berorientasi pelayanan kini ditekan untuk mencari pendapatan. Namun, di sisi lain, rumah sakit swasta tumbuh dominan dengan layanan premium yang menjadi simbol kelas sosial.
Pada bidang farmasi, harga obat-obatan ditentukan oleh perusahaan global yang dilindungi oleh hak paten. Hal tersebut memberi hak eksklusif kepada pemilik perusahaan untuk memproduksi dan menjual obat-obatan tersebut sehingga pesaing tidak boleh membuat versi generik yang lebih murah. Selanjutnya adalah sistem asuransi dan BPJS yang mewajibkan masyarakat untuk terus membayar. Dengan wajibnya membayar iuran tersebut, masyarakat membuat hak dasar berubah menjadi kewajiban finansial, dengan kualitas layanan berbeda antara peserta mandiri dan peserta subsidi. Masyarakat selalu diarahkan membeli “produk sehat” ketimbang mendapatkan layanan dasar yang murah dan merata.
Maka dari itu, muncul diskriminasi layanan bahwa pasien kelas VIP mendapat prioritas, sementara pasien reguler harus menunggu lama dengan fasilitas yang masih terbatas. Bagi rakyat kecil, pilihannya hanya ada dua, yaitu berutang demi biaya berobat atau membiarkan sakit berlarut tanpa penanganan. Secara nyata, kasus di Indonesia dapat dilihat dari data BPJS 2024 yang menunjukkan defisit Rp7,14 triliun, memicu kenaikan iuran dan persyaratan layanan yang semakin kompleks. Secara internasional, di India jutaan orang jatuh ke jurang kemiskinan setiap tahunnya. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, sekitar 66 juta orang mengalami kesulitan membayar biaya kesehatan, dan medical debt menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan keluarga. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa neoliberalisme menjadikan kesehatan sebagai tempat akumulasi profit.
Indonesia telah mencatat suatu kemajuan menuju Universal Health Coverage (UHC) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Dengan cakupan peserta yang sudah melebihi 98%, program ini berhasil memperluas akses layanan dan menurunkan risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan. Namun, tantangan serius masih muncul dalam hal pemerataan akses, keterbatasan tenaga medis dan fasilitas di daerah terpencil, defisit pembiayaan, serta kualitas layanan yang belum konsisten. Capaian kuantitatif ini berisiko menjadi semu jika tidak dibarengi dengan penguatan mutu, keberlanjutan finansial, dan tata kelola yang transparan.
Belajar dari negara lain, Indonesia dapat mengambil inspirasi untuk memperkuat UHC yang tidak hanya luas secara kuantitatif tetapi juga kokoh secara kualitas dan keberlanjutan. Jepang menekankan kendali mutu melalui sistem audit yang memastikan pasien memperoleh perawatan sesuai kebutuhan. Taiwan membuktikan efisiensi lewat single-payer berbasis teknologi informasi. Singapura menunjukkan perlunya diversifikasi pembiayaan melalui kombinasi tabungan wajib, subsidi pemerintah, dan asuransi tambahan agar sistem lebih tangguh menghadapi tekanan fiskal. Thailand berhasil menekan hambatan biaya dengan program layanan hampir gratis yang menjamin keterjangkauan riil bagi masyarakat miskin. Malaysia menjaga ketersediaan tenaga medis dengan investasi pendidikan dan distribusi tenaga kesehatan hingga ke daerah terpencil. Praktik-praktik tersebut menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat mutu layanan, membangun sistem digital terintegrasi, mengelola pembiayaan secara beragam, dan memastikan tenaga medis terdistribusi merata agar UHC benar-benar menjadi perlindungan kesehatan yang berkelanjutan.
Neoliberalisme dalam sektor kesehatan menghadirkan ironi: mutu layanan medis meningkat, tetapi akses terhadap layanan kesehatan semakin timpang. Kesehatan tidak bisa direduksi menjadi sekadar transaksi ekonomi. Sudah saatnya untuk merenungkan, apakah kita rela tubuh manusia dijadikan ladang profit, ataukah kita ingin mengembalikan kesehatan sebagai ruang solidaritas dan hak universal bagi semua?
Referensi
-
Lencucha, R., & Thow, A. M. (2019). How neoliberalism is shaping the supply of unhealthy commodities and what this means for NCD prevention. International Journal of Health Policy and Management, 8(9), 514.
-
Nurwahyuni, A. (2023). Strategi efisiensi rumah sakit di era JKN: literature review. Jurnal Kesehatan Tambusai, 4(2), 2579–2592.
-
Muis, L. S. (2019). Hak atas aksesibilitas obat paten bagi masyarakat. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 1(1), 36–64.
-
Wahyuni, N. W. A., & Widodo, S. (2021). Pelayanan kesehatan, pemilihan kelas perawatan dan sanksi layanan dengan kemauan membayar premi (Willingness to Pay) peserta mandiri (PBPU). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia, 2(2), 163–171.
-
Veratrisna, V., & Nurfitri, N. (2023). Regulasi iklan di Indonesia sebagai media promosi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Healthy: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan, 2(3), 162–177.
-
Sumadi, A. F., Mardiyoko, I., & Pratama, Y. Y. (2022). Perbedaan tingkat kepuasan pasien JKN dan pasien umum terhadap mutu pelayanan unit rawat inap: literature review. Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo, 8(1), 86–97.
-
Pernando, A. (2025). BPJS Kesehatan defisit Rp7,14 triliun, kenaikan iuran disebut jadi solusi selamatkan JKN. Bisnis.com. Diakses dari: https://finansial.bisnis.com/read/20250704/215/1890500/bpjs-kesehatan-defisit-rp714-triliun-kenaikan-iuran-disebut-jadi-solusi-selamatkan-jkn (Diakses pada: 11 September 2025).
-
Sriram, S., & Albadrani, M. (2022). Impoverishing effects of out-of-pocket healthcare expenditures in India. Journal of Family Medicine and Primary Care, 11(11), 7120–7128.
-
Consumer Financial Protection Bureau. (2022). Medical Debt Burden in the United States.
-
BPJS. (2025). Data JKN. Diakses dari: https://www.bpjs-kesehatan.go.id (Diakses pada: 12 September 2025).
-
Indriani, S., & Adisasmito, W. (2024). Perbandingan capaian penerapan cakupan kesehatan universal di Asia terhadap Indonesia. Syntax Idea, 6(5), 2181–2189.